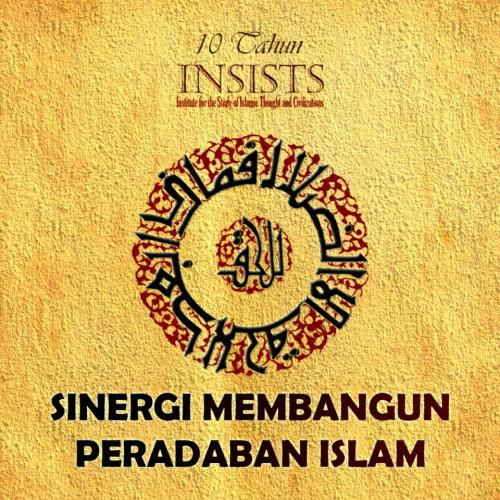Oleh: Kholili Hasib
BERBICARA ilmu di tengah kecamuknya adu senjata perang, seperti akhir-akhir ini terjadi di Timur Tengah, mungkin dianggap tidak bermanfaat, sia-sia, dan bahkan dicemooh sebagian orang sebagai tindakan meninggalkan jihad.
Itulah yang pernah dialami Imam al-Ghazali. Kenyataannya sekarang, kualitas kaum Muslimin turun dikarenakan ilmu yang rusak. Padahal, ilmu adalah modal dasar kebangkitan sebuah peradaban. Harap diingat, sejarah tidak bisa berbohong, bahwa generasi kader-kader didikan Imam al-Ghazali yang mengusung bendera kemenangan merebut al-Quds. Karena itu, tidak salah mengambil ibrah dari strategi jihad al-Ghazali ini.
Nidzamul Muluk, seorang menteri dari Dinasti Saljuk, selama 30 tahun menjabat, mencurahkan segala kekuasaan dan kemampuannya untuk menyokong para ulama. Tidak lain untuk menghidupkan kembali ilmu. Meski ia tidak memegang jabatan puncak dalam kesultanan, namun kekuasaan berada ditangannya. Ia memiliki pemikiran yang lurus. Tidak fanatik pada madzhab tertentu, berusaha mengakomodasi seluruh madzhab yang ada dan menghormatinya. Salah satu keunikannya, majelis Nidzamul Muluk tidak pernah sepi dari ulama dan fuqaha (ahli fikih).
Ada seseorang yang mempertanyakan kebiasaan ini kepadanya: “Sesungguhnya para ulama tersebut telah menyibukkanmu dari banyak urusan kenegaraan”. Namun, Nidzamul Muluk menjawab: “Mereka (para ulama) itulah perhiasaan dunia dan akhirat. Sekiranya mereka duduk di atas kepalaku, maka aku tidak akan menganggapnya berlebihan”(Majid Irsan al-Kilani, “Hakadza Dzahara Jil Shalhuddin wa Hakadza ‘Adat al-Quds” (Beginilah Generasi Shalahuddin Lahir dan Beginilah Palestina. Direbut kembali hal. 69).
Nidzamul Muluk adalah contoh penguasa yang mencintai ilmu dan menghormati ulama. Hujjatul Islam Imam al-Ghazali diangkat olehnya menjadi Guru Besar di Madrasah Nidzamiyah, Madrasah milik pemerintahan Nidzamul Muluk. Imam al-Ghazali diberi gelar kehormatan, Zainuddin Syaraf al-Aimmah. Kedudukan al-Ghazali sangat dihormati dan berpengaruh di kesultanan.
Imam al-Ghazali tidak segan-segan nahi munkar di dalam pemerintahan. Ia pernah menolak secara terbuka dan tegas rencana pelantikan Malik Mahmud sebagai sultan. Al-Ghazali melihat Malik Mahmud tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin Negara. Ketika, pemerintahan telah berbelok dari syariat, al-Ghazali menarik diri. Bagaimanapun, kedudukan tinggi tidak menghalangi Imam al-Ghazali mengkritisi fenomena formalitas di pemerintahan, kejahatan Negara ia buka, dan melakukan islah. Ia pernah menulis kitab al-Tibr al-Masluk fi Nasihati Muluk, dihadiahkan kepada sultan berisi nasihat dan kritikan.
Antara Nidzamul Muluk dan Imam al-Ghazali adalah gambaran baik tentang adab seorang penguasa dan tugas seorang ulama. Seorang kepala Negara harus mencintai ilmu dan menempatkan ulama sebagai poros utama dalam melakukan perbaikan masyarakat. Seorang ulama haruslah memiliki visi amar ma’ruf nahi munkar, tidak menjual agama, tidak penjilat, dan berani berkata ‘tidak’ pada kebijakan Negara yang menyalahi syariat. Sebuah kolaborasi yang porosnya adalah tradisi ilmu. Dan ternyata, kolaborasi dua komponen inilah menjadi penentu kebangkitan Islam.
Al-Ghazali mengingatkan seorang khalifah tidak boleh meninggalkan Ulama. Namun, seorang sultan juga harus cermat, tidak sembarang ulama yang harus diminta nasihat. Ulama Suu’ (ulama jahat) justru menjerumuskan negara pada kerusakan. Cirinya, mereka selalu memuji-muji raja secara tidak wajar, tujuan dakwahnya selalu mengarah pada duniawi. Sebalikanya seorang ulama sejati (ulama al-akhirah) ia sama sekali tidak mengharapkan balasan uang dari tangan seorang raja, ia memberi nasihat murni ikhlas karena meminginginkan perbaikan dalam diri raja, negara dan masyarakat.
Imam al-Ghazali hidup di masa Perang Salib. Beliau hidup antara tahun 1058 M-1111 M. Ketika kesultanan mengalami kekacauan, baik politik maupun akhlak, al-Ghazali menarik diri dan melepas jabatan dari guru besar madrasah Nidzamiyah. Al-Ghazali mengamati segenap tujuan dan perilaku pejabat dan ulama. Dan mendapati bahwa agama menjadi sekedar simbol kosong yang digunakan untuk mendapatkan kedudukan terhormat. Sementara afiliasi kepada madzhab tidak lebih dari alat untuk memperoleh jabatan politis dan keuntungan duniawi. Dua faktor ini dilihat sebagai penyebab, matinya ilmu. Dan matinya ilmu merupakan tanda matinya peradaban Islam. Matinya peradaban zaman itu salah satunya, ditandai dengan kekalahan dalam Perang Salib I dan perang saudara antar penguasa Muslim.
Selain aliran Mu’tazilah dan Syiah Batihiniyah, permusuhan dan fanatisme madzhab termasuk yang diperangi sehinga melahirkan hasud dan pertikaian antar pengikut madzhab fikih. Masyarakat terpecah sehingga melupakan persoalan genting yang sedang dihadapi. Penyakit jiwa ini berlanjut pada pengkafiran terhadap pengikut madzhab lainnya. Kitab Al-Fashlu al-Tafriqah baina al-Islam wa al-Zandaqah mendeskripsikan pengkafiran terhadap pengikut madzhab lain. Ia mengajukan kritik terhadap pengikut Hanbaliyah dan Asy’ariyah yang saling mengkafirkan dalam persoalan furu’. Kelompok utama yang ia kritik adalah para ulama. Terutama yang menjual agama demi merapup keuntungan duniawi dan pribadi.
Imam al-Ghazali menulis kitab Ihya’ Ulumuddin, artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dalam kitab tersebut, Imam al-Ghazali melakukan reformasi intelektual dan moral kaum Muslim dalam perspektif yang luas dan lengkap. Ia menemukan, kelemahan kaum Muslimin ternyata bermuara kepada kelemahan moral dan jiwa. Krisis politik dan militer disebabkan rusaknya jiwa kaum Muslimin. Dan kehancuran jiwa diakibatkan kekacauan ilmu.
Upaya al-Ghazali tersebut ternyata diakui oleh penulis Barat, Nikita Elissef. Elissef mengatakan, kelemahan spiritual kaum Muslimin pada Perang Salib I berhasil diberbaiki oleh al-Ghazali yang ketika itu mengajar di Damaskus. Ia menekankan jihad melawan nafsu untuk mereformasi jiwa. Ternyata, kata Elissef, 50 tahun kemudian, yaitu di masa Sultan Nuruddin Zanki, kaum Muslimin mampu bangkit dan melakukan jihad melawan Salib secara efektif. Satu persatu kota kunci berhasil ditaklukkan. Zanki membuka kota Edessia dan Aleppo, kota kunci menuju al-Quds. Diceritakan, Nuruddin Zanki juga membangun rumah-rumah sufi dan madrasah di sekitar negeri Syam.
Strategi Imam al-Ghazali untuk kebangkitan Islam tidak lepas dari poros perbaikan ilmu dan ulama. Ia fokus pada dua tugas; Pertama, melahirkan generasi baru ulama dan elit pemimpin yang mampu berbuat dengan pemikiran yang bersatu dan tidak terpecah-pecah, usaha mereka saling melengkapi dan tidak saling menjegal. Kedua, memfokuskan perhatian untuk mengatasi penyakit-penyakir krusial yang menggerogoti umat dari dalam dari pada sibuk dengan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut, yang di antaranya adalah ancama agresi militer musuh yang datang dari luar.
Kembali kepada ilmu dan ulama adalah kuci utamanya. Pejuang-pejuang yang jiwanya rusak dan kotor dikarenakan ilmu yang tidak mapan. Terhadap kelompok ini tentu Allah tidak ridha memberi amanah Islam. Allah swt hanya memberi amanah kepada kaum Muslimin yang jiwanya dan ridha atas ketentuan Allah swt. Persudaran Muslim hanya ditegakkan atas dasar tradisi ilmu.*
Penulis adalah Peneliti InPAS Surabaya, Wakil Sekretaris MIUMI Jawa Timur