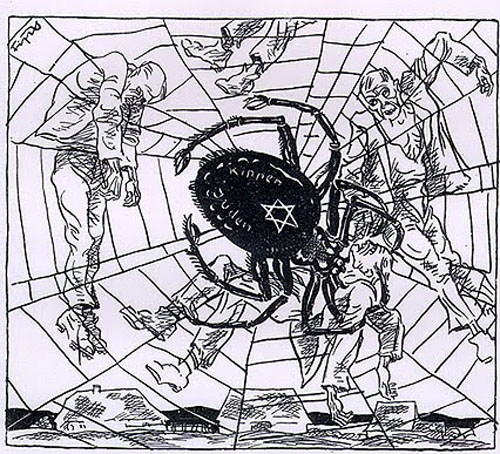Oleh: Qosim Nursheha Dzulhadi*
TUDUHAN demi tuduhan terhadap ummat Islam datang silih berganti. Dan, sepertinya enggan berhenti. Tuduhan sebagai penganut agama yang fanatik, tuduhan intoleran, bahkan tuduhan ‘garis keras’ datang bertubi-tubi. Tuduhan-tuduhan ini datang dari luar Islam (orang kafir, musyrik, atheis, dll) bahkan dari dalam (misal: kaum munafik, kaum liberal, sekular dan pluralis).
Jika tuduhan itu datang dari luar, tentu sangat wajar. Karena tugas mereka adalah menghancurkan umat Islam dan merusak agamanya. Tujuannya memurtadkan mereka atau, minimal, menghilangkan identitas mereka sebagai Muslim (QS. 2: 120, 217). Sehingga hilanglah kebanggaan mereka kepada Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna (QS. 3: 19, 85). Akhirnya, tidak lagi merasa terhina ketika Islam dihina. Tak lagi merasa malu ketika Islam dicela, difitnah, dan dituduh macam-macam. Ini namanya hilang Ghīrah, dalam bahasa Buya Hamka. Padahal Ghīrah terhadap agama inilah yang mampu bangkitkan kejayaan agama, bangsa dan negara.
Umat Islam, khususnya di Indonesia, seharusnya mulai sadar dan bangkit bergandengan tangan. Kenapa? Karena upaya menista Islam dan umatnya sudah mulai dikerjakan secara massif, terorganisir, bahkan brutal. Hebatnya lagi, dilakukan terang-terangan. Maka, umat Islam harus cepat sadar. Ayo, bangkitkan Ghīrah agamamu. Jangan diam! Sebagiamana dahulu para ulama dan tokoh umat ini tak rela Islam dinista dan dihina.
Tuanku Imam Bonjol bermaksud hendak mengundurkan dirinya dari medan perang. Tetapi setelah melihat masjid diambil menjadi kandang kuda beliau tidak jadi mengundurkan dirinya. Beliau menyentak pedangnya. Walaupun dia sudah tua! Tidak dihitungnya lagi apakah dia akan kalah atau akan menang. Apakah dia akan hidup atau akan mati. Tidak melawan itulah yang mati. Sebab tidak ada lagi Ghīrah! Yaitu tebal kuping dan tebal muka. Orang Islam bukanlah:
فطنا لكل مصيبة فى ماله #
وإذا يصاب بدينه لم يشعرى
“Sangat awaslah kalau harta bendanya tersinggung. Tetapi tidak ada perasaannya apabila agamanya kena musibah.”
Itulah bait syair pusaka Sayyidina Ali: ejekan kepada orang yang telah luntur rasa Ghīrah agamanya.
Semasa Belanda berkuasa dibuatlah propaganda bahwa orang Islam itu fanatik! Orang-orang yang terdidik dengan cara Belanda pun –lantaran cap– yang telah diberikan itu merasa dirinya rendah kalau kelihatan fanatik. Akhirnya anak Islam yang telah terdidik secara Barat tadi pun turut pula menuduh bangsanya dan kaumnya fanatik!
Diponegoro dengan niat hendak mendirikan Kerajaan Islam di tanah Jawa dan beliau “Amirul Mukminin” dituduh fanantik!
Perlawanan Imam Bonjol 16 tahun dengan gerakan Paderinya yang terkenal dituduh fanatik!
Perlawanan Cik Ditiro bahkan perlawanan rakyat Aceh selama 40 tahun, semuanya dituduh fanantik! Bahkan selama ummat Islam masih belum menerima penjajahan, selama itu pula mereka dituduh dan harus dicap fanantik.
Barulah akan hilang cap fanatik itu bila Ghīrah agamanya telah hilang. Baik dalam diri pribadinya ataupun dalam masyarakatnya. Barulah dia tidak dicap fanatik lagi setelah dia tak segan lagi makan babi, minum arak dan alkohol terang-terangan. Kalau dia duduk bersama-sama Belanda atau yang terdidik cara Barat di waktu Maghrib, malu dia hendak sembahyang, maka terpujilah ia sebagai orang yang “luas paham dan toleran”. Baru dipandang sebagai orang yang luas paham bila dia tidak datang ke mesjid lagi hari Jum’at. Padahal orang Belanda tetap ke gereja pada hari Minggu. Dan dia akan dicap fanantik kalau di rumahnya masih ada tikar sembahyang! Dan namanya akan dipopulerkan di mana-mana sebagai orang Islam yang maju, yang luas paham, yang progresif kalau ia telah turut pula memburuk-burukkan kiainya, mencela kehidupan santri, kaum santri itu kotor dan gudikan!
Tuan tahu apa sebabnya?
Sebab “Pesantren” itulah sumber tenaga kekuatan Islam di Indonesia selama ini. Maka pengaruhnya mesti dihilangkan; mesti ditimpakan kepadanya tuduhan-tuduhan dan cap fanatik. (Lihat, Buya Hamka, Ghirah dan Tantangan terhadap Umat Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 10-11).
Selama ini memang begitu. Tak sedikit yang mengaku dirinya Muslim tapi hobi menuduh saudaranya fanatik, bahkan menuduhnya sebagai ‘Islam garis keras’. Inilah realita umat Islam, khususnya di Indonesia. Getir memang, tapi harus kita telan. Pahit, tapi harus dinikmati. Inilah realitanya.
Satu realita yang menuntut ketegasan sikap dan sifat. Jangan sampai musuh ramai-ramai menyerang, sementara kita kehilangan Ghīrah terhadap agama ini.
Padahal, sudah tiba masanya umat Islam mengamalkan firman Allah, ‘Muhammadur-Rasūlullāh wal-ladzīna ma‘ahū asyiddā’u ‘alā’l-kuffāri ruhamā’u bainahum’ (Qs. Al-Fath: 29).
Itulah ketegasan sikap, yang tercermin dalam dua hal: persatuan keyakinan dan persaudaraan yang rapat, kata Buya Hamka.
“Dia sesama sendiri, bersatu aqidah, bersatu pandangan hidup adalah cinta-mencintai, seberat seringan, sehina semalu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dengan sesama beriman. Di antara ‘awak sama awak’ yang sepaham tidak ada soal. Tidak ada yang kusut yang tidak terselesaikan, tidak ada keruh yang tidak terjernihkan. Itulah yang dinamai ukhuwwah Islamiyah.” (Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar: 8/406-407).
Karena dengan kesatuan aqidah, pandangan hidup dan ukhuwwah itu Ghīrah bisa dibangkitkan dan musuh bisa digentarkan. Jika tidak, yang lahir adalah para pengkhianat dan kaum munafik. Mereka berani jual bangsa bahkan agamanya demi dunia yang singkat dan fana. Mereka sudah tidak mikir ‘regenerasi’. Karena yang penting adalah “beras hari ini”. Ironis!
Seharusnya bangsa dan negara ini bersyukur punya penduduk mayoritas Muslim. Yang Ghīrah-nya untuk bangsa dan negara sudah teruji dan terpatri. Jangan lagi diragukan. Dan seharusnya malu menuduh umat Islam fanatik, intoleran dan garis keras. Padahal, sejak zaman penjajahan dan sampai kapanpun justru inilah modal bangsa Indonesia dalam mempertahankan marwahnya. Tanpa Ghīrah umat Islam, maka takkan pernah ada kemerdekaan. Meskipun kenyataannya, setelah merdeka umat Islam selalu “dikorbankan”.
Tapi, Ghīrah umat Islam untuk agama dan bangsanya takkan pernah padam. Karena, kata Buya Hamka, bila Ghīrah telah mulai hilang, jiwa akan menjadi gelisah. Kulit menghendaki Barat padahal badan masih berada di Timur.
Dan apabila Ghīrah telah tak ada lagi, ucapkanlah takbir empat kali ke dalam tubuh ummat Islam itu. Kocongkan kain kafannya lalu masukkan ke dalam keranda dan hantarkan ke kuburan.
Kalau masih ada pemuda Islam yang merasa bangga dibuang 15 tahun, karena Ghīrah akibat saudara perempuannya diganggu, alamat bahwa sesungguhnya Islam belum kalah. (Buya Hamka, Ghīrah, 8).
Maka, sepatutnyalah kita pertanyakan Ghīrah ini dalam dada. Masih adakah? Jika melihat ummat Islam Indonesia terpinggirkan, padahal mereka yang memperjuangkannya dahulu, dan merasa sedih lalu bangkit, itu alamat Islam belum kalah. Jika merasa aman-aman saja, damai-damai saja, itu alamat Ghīrah telah mati. Itu pula alamat bangsa ini segera mati. Jangan sampai Indonesia sebagai negara masih ada, tapi sebagai bangsa sudah mati. Kenapa? Karena matinya Ghīrah umat Islam. Karena hanya umat Islam yang berani mati untuk agama dan bangsanya.[]
*Aktivis Muslim dan penulis buku pemikiran