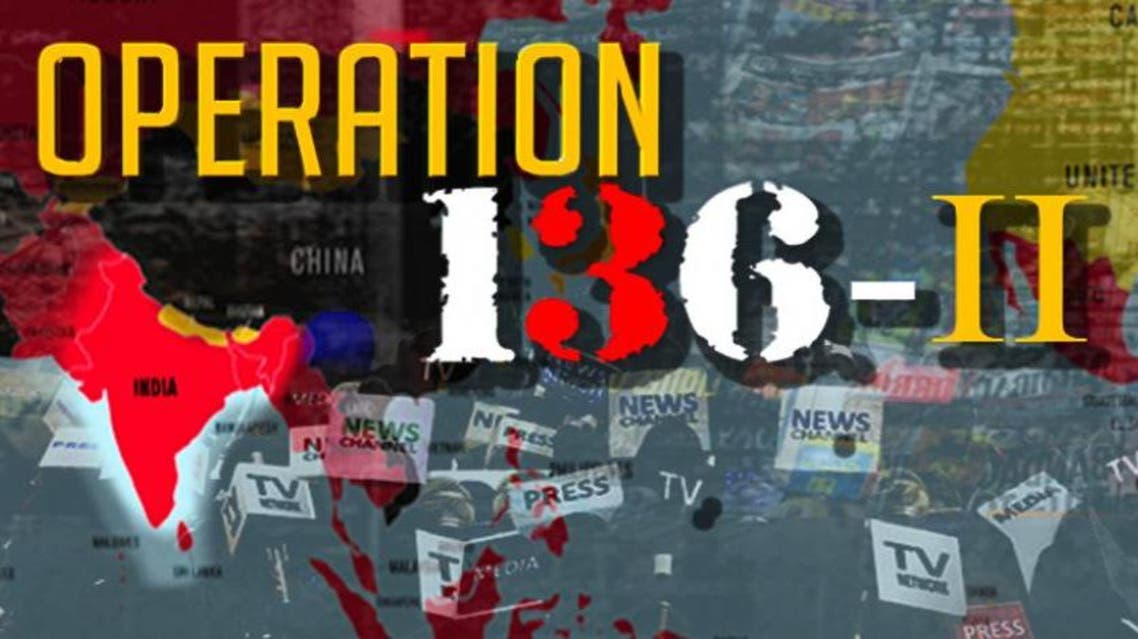Oleh: Ahmad Arif Ginting
MASUKNYA politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh, dalam persidangan kasus suap Wisma Atlet semakin menambah panjang “antrian” perempuan sebagai tersangka bahkan terdakwa dalam kasus korupsi di negeri ini. Uniknya, jika diperhatikan dengan seksama, hampir sembilan puluh sembilan persen (99%) mereka menggunakan simbol-simbol agama (khususnya Islam) berupa kerudung, tudung, jilbab, bahkan cadar. Apa yang bisa kita baca dari fenomena mutakhir di negeri zamrud khatulistiwa ini?
Feminisasi Korupsi?
Sangat menarik membaca tulisan Muhammad Afifuddin, “Feminisasi Korupsi” di Koran Republika (15/o2/2012) kemarin; “Dari yang telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa/tervonis, ada nama seperti Imas Diansari, hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung yang tertangkap basah menerima suap Rp 200 juta.
Selain itu, dua anggota DPR Ni Luh Mariani Tirtasari dan Engelina Pattiasina yang tersangkut kasus cek pelawat, Nunun Nurbaetie dan Miranda S Goeltom (kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI), serta Wa Ode Nurhayati (mafia banggar DPR). Sosok lainnya adalah Mindo Rosalina Manulang, Neneng Sri Wahyuni, hingga yang terbaru Angelina Sondakh dalam kasus suap Wisma Atlet.
Sedangkan dalam kasus suap Kemenakertrans, Dhanarwati malah sudah divonis dua tahun enam bulan. Bahkan, kalau mundur cukup jauh ke belakang, jangan kita lupakan `ratu sel mewah’ Artalyta Suryani (Ayin) yang juga resmi divonis sebagai koruptor. Sementara itu, perempuan yang sempat dikaitkan dengan berbagai skandal suap/mark up korupsi adalah Nining Indra Saleh (Setjen DPR), Athiyah Laila (istri Anas Urbaningrum dalam kasus suap Wisma Atlet), atau bahkan Sri Mulyani dalam kasus Century. Sedangkan, di luar komplotan mafia anggaran dan penyuap aparat negara tersebut, ada nama Malinda Dee yang sempat beken karena kiprahnya membobol uang nasabah Citibank. Masih ada beberapa nama lagi yang lain yang akan sangat memakan ruang jika harus dituliskan semuanya.
Apakah ini kebetulan semata? Asumsinya, uang tidak punya jenis kelamin. Siapa pun mempunyai `bakat’ korupsi asalkan menemukan momentum (niat dan kesempatan) yang tepat. Bisa jadi fenomena ini 100 persen sebuah kebetulan yang cantik. Namun, melihat rentetan kejadian kasus per kasus di mana keterlibatan perempuan menjadi variabel vital dalam skenario perampokan anggaran rakyat tersebut, tampaknya asumsi kebetulan sulit untuk dinalar.
Penulis buku “Korupsi Kepresidenan” (2005), George Junus Aditjondro, dalam sebuah seminar di UGM awal tahun ini mengutarakan, fenomena perempuan banyak tersangkut korupsi merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia. Tekanannya bukan pada persoalan kebetulan atau by design, melainkan lebih pada bagaimana kita memaknai perubahan sosiologis dalam konteks gender dan feminisme yang bersangkut paut dengan skandal-skandal keuangan tersebut.
Di bagian akhir tulisannya, Muhammad Afifuddin menegaskan, ketika akses ruang publik yang selama ini didominasi kaum laki-laki dibuka juga untuk perempuan, mereka ternyata sama rentannya dengan laki-laki. Pertanyaannya, mengapa kerentanan itu terjadi? Karena para `perempuan korup’ itu sedang terjangkit sindrom yang oleh bapak Psikoanalisis Sigmund Freud disebut sebagai histeria (euforia).
Efek fatal dari histeria itu adalah melemahnya fungsi superego sebagai pagar penjaga moralitas yang berkembang di kehidupan sosial seseorang oleh menguatnya ego secara berlebihan dan berciri destruktif. Manifestasi dari histeria ego adalah egoisme diri untuk kaya secara instan tanpa memedulikan nasib jutaan orang lainnya.
Padahal, hasil riset Bank Dunia tahun 1999 yang dilakukan Development Research Group/Poverty Reduction and Economic Management Network menemukan kenyataan menurunnya tingkat korupsi bersamaan dengan kian meningkatnya jumlah perempuan di tingkat parlemen nasional. Riset tersebut menjadi dasar bagi Bank Dunia untuk merekomendasikan agar semua negara memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan menduduki jabatan di pemerintahan dan parlemen karena keberadaan mereka berpotensi untuk menurukan tingkat korupsi (Neta S Pane, 2011).
Apa yang terjadi di Indonesia saat ini seakan mematahkan hasil penelitian Bank Dunia tersebut. Peran perempuan yang menduduki sejumlah jabatan penting di negeri ini tumbang satu per satu karena terlibat korupsi. Data ICW menyebutkan, pada 2008 dari 22 koruptor yang ditangkap, dua di antaranya perempuan. Kemudian, pada 2011 jumlahnya meningkat lebih dari tiga kali lipat. Fakta ini sekaligus membantah pernyataan mantan komisioner KPK M Jasin bahwa perempuan selama ini lebih berperan sebagai pendorong korupsi yang dilakukan laki-laki.
Alamat Religiositas?
Pertanyaan krusial lain adalah apakah tindakan mereka itu merupakan refleksi dari religiositas yang sedang melonjak naik? Atau, jangan-jangan tindakan mereka itu justeru bisa dimasukkan dalam kategori penistaan terhadap simbol-simbol keagamaan (Islam)?
Prof. Komaruddin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah saat ini menulis, “Jilbab Masuk Ruang Pengadilan”, (Koran SINDO, 10/2/2012) lalu. “Mengapa beberapa wanita yang menjadi tersangka korupsi cenderung mengenakan jilbab ketika masuk ruang pengadilan? Padahal sebelumnya mereka dikenal senang berpakaian yang modis dan bahkan seksi. Sekali lagi, berpakaian itu pilihan dan selera individu dengan mempertimbangkan tradisi dan norma sosial. Mengapa seseorang yang tersangkut korupsi dan memasuki ruang sidang pengadilan lalu memilih mengenakan jilbab, yang paling tahu dan merasakan adalah yang bersangkutan. Hanya saja bisa dimaklumi kalau orang lain lalu menafsirkan dan menduga-duga.
Mungkin saja merasa lebih nyaman dan sedikit meringankan beban batin mengingat jilbab dipahami sebagai pakaian religius. Orang berjilbab dikonotasikan sebagai orang baik-baik. Atau tengah intens mendekatkan diri pada ajaran agama, yang secara diametral berseberangan dengan tindakan korupsi. Secara lahiriah memang memunculkan pemandangan unik.
Ada orang tertuduh sebagai koruptor,tetapi penampilannya mengesankan religius karena di Indonesia ada kecenderungan menempatkan jilbab sebagai simbol kualitas keimanan dan keislaman seseorang. Jadi, jilbab di ruang pengadilan bisa menimbulkan multitafsir. Yang bersangkutan adalah orang religius yang tidak melakukan korupsi sehingga sangkaan dan tuduhan kepadanya sebagai koruptor tidaklah benar. Itu fitnah. Atau, yang bersangkutan melakukan kekhilafan, memang melakukan korupsi, dan sekarang tengah melakukan pertobatan yang ditandai antara lain dengan mengenakan jilbab. Tafsir lain, mungkin mengenakan busana religius di ruang pengadilan membuat yang bersangkutan merasa nyaman ketimbang pakaian lain tanpa berpretensi sok agamis.
Dalam bahasa agama, harta haram itu tak akan membawa berkah. Kembali ke soal jilbab. Sering kali jilbab digunakan sebagai modal untuk melakukan penipuan dengan mengesankan dirinya orang religius,baik,dan tepercaya.Padahal tak lebih kedok belaka.Tentu ini merusak citra dan norma keagamaan sehingga logis kalau ada orang yang kesal kepada mereka yang berjilbab, tetapi perilakunya tidak mencerminkan normanorma luhur keagamaan.
Ekses lebih jauh,muncul pandangan, jilbab tidak bisa dijadikan tolok ukur kesalehan seseorang. Namun sesungguhnya kasus serupa juga terjadi pada uniform militer atau polisi. Terdapat polisi atau tentara gadungan, mengenakan seragam dinas untuk menipu orang lain. Atau, bisa saja mereka polisi atau tentara beneran, tetapi perilakunya justru melawan etos dan norma kepolisian atau kemiliteran. Misalnya, polisi terlibat pengedaran narkoba.Jadi, pakaian itu sangat penting sebagai simbol dan perangkat peradaban, tetapi selalu saja ada orang yang memanipulasi untuk tujuan pribadi.”
Dengan nukilan tersebut, saya sepakat. Tapi, di akhir tulisannya, Prof. Komaruddin kembali memperlihatkan sikap ambigunya dengan menuliskan, “Lalu, bagaimana berjilbab di ruang pengadilan? Itu hak mereka, tak ada peraturan yang dilanggar”. Padahal jelas-jelas di awal tulisannya dia menulis sendiri kalimat berikut, “Sekali lagi, berpakaian itu pilihan dan selera individu dengan mempertimbangkan tradisi dan norma sosial”.
Stop Penistaan ini!
Pelarian di ujung kebengalan, itulah yang bisa dibaca dan dipelajari dari fenomena tersebut seperti ditegaskan dalam “Tudung Hitam”, judul editrorial Majalah Tarbawi dalam kasus “Xenia Maut”. Di detik ketika seseorang sadar bahwa kegilaannya dihentikan oleh trotoar atau besi-besi halte, sekelebat hadir perasaannya sebagai manusia yang lemah. Dan bila tudung hitam itu punya arti, kira-kira ia menjelaskan bahwa perempuan itu merasa perlu berlari kepada ‘simbol keterhubungan’ dengan Tuhan. Tapi terlalu ringkih untuk disebut sebagai kain hitam lambing pertaubatan.
Para perempuan itu tiba-tiba bertudung (berjilbab, bahkan bercadar) hitam. Kita tidak tahu pasti apa maksudnya. Tetapi setidaknya kita bisa bercermin. Bahwa terlalu banyak orang yang hanya berlari kepada Tuhan di tubir keruntuhannya. Dan, setelah kebejatannya memakan begitu banyak korban. Itu pun pelarian yang rapuh. Hanya simbol keterhubungan yang masih multi tafsir. Bahkan bila pun tudung hitam (berjilbab, bahkan bercadar) itu ingin diartikan sebagai sepotong rasa bersalah, itu masih menghajatkan sangat banyak pembuktian lanjutan.
Dari nukilan-nukilan di atas, kita meminta kepada pemerintah untuk memberhentikan tindakan penistaan simbol keagamaan yang telah berlangsung selama ini. Sesungguhnya masyarakat sudah terlalu jengah dengan semua dagelan itu. Sebagai gantinya, kita minta pemerintah untuk mewajibkan para pelaku kejahatan itu, apapun jenis kejahatannya, untuk memakai seragam penjara saja. Bukankah beberapa waktu lalu sempat hangat dibahas tentang rencana pembuatan seragam tersebut? Itu akan menjadi shock therapy paling efektif bagi mereka daripada berlaku sok suci dan atau sok religious! Wallahu a’lam bishshawab.*
Penulis adalah peminat kajian sosial keagamaan, berdomisili di Banda Aceh
Keterangan: Yulianis dan Oktarina Fury bergamis dan bercadar saat bersaksi dalam sidang kasus suap Wisma Atlit di Pengadilan Tipikor, Jakarta