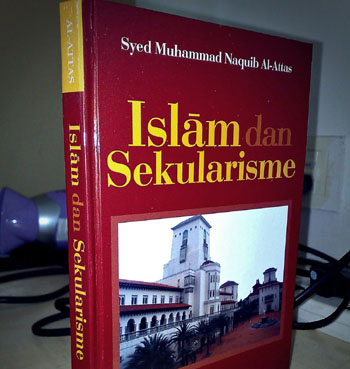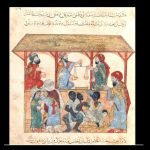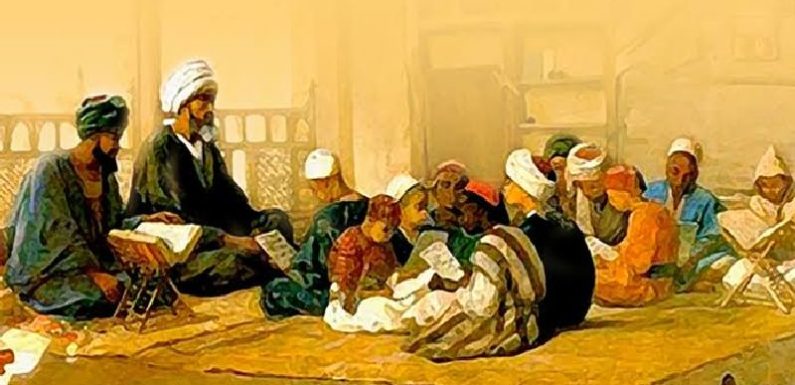Oleh: Qosim Nursheha Dzulhadi
PROF . al-Attas adalah pemikir kontemporer Muslim pertama yang mendefinisikan arti pendidikan secara sistematis, menegaskan dan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menurut Islam bukanlah untuk menghasilkan warga negara yang baik dan tidak pula pekerja yang baik (to produce a good man, not a good citizen) (Lihat, Prof. al-Attas, The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1996), hlm. ix. Lihat juga, al-Attas, “Introduction”, dalam al-Attas (ed.), Aims and Objectives of Islamic Education (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979), hlm. 1).
Memang, salah satu kejeniusan Prof. al-Attas adalah analisisnya yang mendalam terhadap konsep-konsep kunci dan mendasar dalam pemikiran Islam, utamanya tentang konsepsi pendidikan Islam. Konsepnya ini kemudian dikenal dengan istilah ta’dīb, bukan tarbiyah maupun ta‘līm. Konsep ta’dīb-nya inilah yang kemudian disalahpamahi oleh Prof. Nurcholish Madjid. Di mana menurutnya konsep ta’dīb Prof. al-Attas sebagai arbitrer, tidak ada dasarnya. Dengan sangat jelas Prof. Nurcholish menyatakan demikian:
“Yang dalam Al-Qur’an itu bukan adab semacam yang ia tafsirkan itu, tapi tarbiyah, Rabb-i irham-humā kamā rabbayānī saghī-an. Siapa yang mendidik kita lebih besar, lebih selektif melebihi orang tua? Itu tarbiyah dan tarbiyah itu meningkat.” (Lihat, Prof. Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer (Jakarta: Paramadina, cet. I, 1998hlm. 249).
Pernyataan Prof. Nurcholish bahwa konsep ta’dīb Prof. al-Attas arbitrer: tidak ada dasarnya adalah pernyataan yang terlalu dini anti-klimaks. Terlalu dini karena penilaiannya tidak objektif sama sekali. Ini tampaknya lahir dari pandangan Prof. Nurcholish yang melihat pendidikan secara terminologi saja, seperti tarbiyah. Dan menurutnya tarbiyah-lah yang tepat untuk mendefinisikan konsepsi pendidikan dalam Islam. (Prof. Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan, hlm. 249).
Anehnya, Prof. Nurcholish dengan nada menyindir – menurut penulis – mengatakan, “Saya tidak mengerti konsep adab itu. Katanya referensinya Hadits. Addabanī rabbī fa’ahsana ta’dībī.” Kalau soal referensi mengapa tidak Al-Qur’an sekalian saja. Kalau dalam Al-Qur’an itu tarbiyah, dan itu sama dengan tanmiyah atau development dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita tumbuh terus. (Prof. Nurcholish, Dialog Keterbukaan, hlm. 250).
Pernyataan Prof. Nurcholish di atas penting mendapat catatan, minimal dalam beberapa poin berikut ini:
Pertama, Prof. Nurcholish sepertinya memang belum memahami konsep adab yang dikemukakan oleh Prof. al-Attas. Padahal, konsepsi Prof. al-Attas sangat dalam mengenai ini: menukik kepada dasar yang lebih esensial dari tujuan pendidikan itu sendiri, adab. Maka istilah yang diambil pun menjadi berbeda, ta’dīb dan bukan tarbiyah seperti yang dikatakan oleh Prof. Nurcholish.
Dan penting diperhatikan bahwa sebelum menyampaikan konsep ta’dīb, Prof. al-Attas mengulas terlebih dahulu secara mendalam makna yang dikandung oleh tarbiyah maupun ta‘līm. Maka dapat dimaklumi jika pandangan Prof. Nurcholish kemudian miring. Sementara penulis lain banyak yang menilai bahwa konsep ta’dīb Prof. al-Attas abstrak dan sangat filosofis (Lihat, Kemas Badaruddin, Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Pemikiran Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II, 2009), hlm. 37-38). Penilaian bahwa konsepsi ta’dīb itu abstrak juga tidak mendalam. Bahkan, cenderung menapikan jika konsep ini real.
Dikatakan real karena contoh adab yang benar telah dicontohkan oleh Baginda Rasulillah Shallallahu ‘alaihi Wassalam: bukan saja di dalam Al-Qur’an tetapi juga di dalam sabda dan sunnah keseharian beliau. Karena, seperti ditulis oleh Prof. Wan Daud, Al-Qur’an menegaskan bahwa contoh ideal bagi orang yang beradab adalah Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wassalam, yang oleh kebanyakan sarjana Muslim disebut sebagai Manusia Sempurna atau Manusia Universal (al-insān al-kullī). Oleh karenanya pengaturan administrasi pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan Islam haruslah merefleksikan Manusia yang Sempurna. (Lihat, Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud, “Konsep al-Attas tentang Ta’dīb: (Gagasan Pendidikan yang Tepat dan Komprehensif dalam Islam)”, dalam Islamia, Th II No. 6/Juli-September 2005: 77).
Kedua, Prof. Nurcholish yang lebih memiliki tarbiyah karena disebutkan di dalam Al-Qur’an mengesankan bahwa Prof. al-Attas tidak mengulasnya. Tentu ini sangat keliru. Karena ulasan Prof. al-Attas tentang tarbiyah dan ta‘līm begitu mendalam. Berkaitan dengan istilah tarbiyah, dalam dalam bahasa Prof. Nurcholish sama denan development dalam bahasa Inggris, telah diulas secara mendalam oleh Prof. al-Attas. Di mana intinya menurut Prof. al-Attas, tarbiyah merefleksikan konsep Barat tentang pendidikan (Those who coined the term tarbiyah to mean education were in reality reflecting the Western concept of ‘education’…. (Prof. al-Attas, The Concept of Education in Islam, hlm. 28).
Dan, ini penting diingat, ayat yang dikutip oleh Prof. Nurcholish (Qs. Al-Isrā’ [17]: 24) bukan semata-mata berarti pendidikan itu mutlak diberikan oleh kedua orang tua. Karena makna rabbayānī yang dimaksud dalam Qs. 17: 24 itu adalah kasih-sayang (rahmah). Oleh karena itu kata nurabbika dari mulut Fir‘aun untuk nabi Musa tidak berarti Fir‘aun mendidiknya, tetapi maknanya adalah Fir‘aun yang membesarkan nabi Musa. Dan kata membesarkan di sini tidak serta-merta menanamkan ilmu pengetahuan di dalamnya (Tarbiyah simply means cherishing, without necessarily including the inculcation of knowledge in the cherishing). (Prof. al-Attas, The Concept of Education in Islam, hlm. 32). Dan kata tarbiyah yang jika diartikan sebagai pendidikan ternyata tidak serta-merta khusus untuk manusia: bisa kepada mineral (barang tambang), tanam-tanaman (plants), dan hewan (animals). (Prof. al-Attas, The Concept of Education in Islam, hlm. 29).
Ketiga, secara tegas al-Attas menyatakan bahwa di dalam ta’dībi sudah tercakup tarbiyah dan ta‘līm. Karena ta’dīb lebih komprehensif dari keduanya. Selain itu, pandangan al-Attas juga didasarkan kepada makna addaba yang berarti ‘allama, seperti yang dicatat oleh Ibn Manzhūr di dalam kamus Lisān al-‘Arab-nya. (Lihat, Ibn Manzhūr, Lisān al-‘Arab, tahqīq: ‘Abd Allāh ‘Alī al-Kabīr, Muhammad Ahmad Hasb Allāh, Hāsyim Muhammad al-Syādzilī (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, ttp), I: 43 dan bandingkan dengan Prof. al-Attas, The Concept of Education in Islam, hlm. 25-26).*/bersambung artikel berikutnya