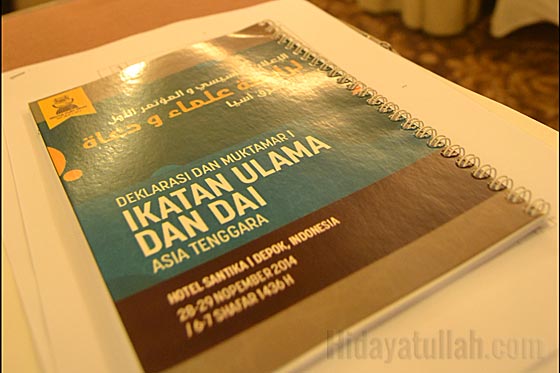Tulisan-tulisan sarjana Barat mengenai studi Al-Quran bertolak dari skeptisisme terhadap status kitab suci itu sebagai dokumen sejarah. Mereka tidak mencari kebenaran, tetapi hanya mencari pembenaran
Oleh: Dr Syamsuddin Arif
Hidayatullah.com | BEBERAPA TAHUN LALU, seorang staf pengajar sebuah universitas Jakarta menulis catatan di media massa. lsinya mengkritik buku Profesor Muhammad Mustafa Azami, The History of the Quran ic Text: from Revelation to Compilation (2003).
Menurut dia, Azami “tidak masuk ke jantung perdebatan diskursif yang berkembang di Barat, sehingga gagal merespons secara intelektual isu-isu penting dalam studi Al-Quran oleh kaum orientalis.” Staf Paramadina ini agaknya belum membaca buku tersebut secara keseluruhan.
la terkesan tidak adil dan tergesa-gesa dalam memberikan penilaian. la gagal menangkap objektif utama karya Azami yang sebenarnya ingin menjawab tiga pertanyaan penting (halaman 12).
Pertanyaan tersebut, pertama, apa yang dimaksud Al-Quran ? Kedua, apabila suatu saat ditemukan lagi naskah tulisan tangan (manuskrip) berisi sebagian atau seluruh ayat-ayat Al-Quran namun berbeda dengan versi yang sudah ada, apakah dampak penemuan itu terhadap teks Al-Quran?
Ketiga, soal otoritas. Siapa yang berhak dan layak untuk mengatakan sesuatu mengenai Al-Quran, Islam, dan segala aspeknya?
Jadi, tujuan utama Azami lebih pada upaya menjelaskan sejarah kompilasi dan kodifikasi Al-Quran, ketimbang memberikan respons mendalam dan menyelami korpus kesarjanaan Barat.
Baca: Dr. Syamsuddin Arif: Orientalis Tak Pernah Lepas dari Kepentingan
Al-Quran dalam Studi Barat
Konon, tidak semua orientalis berniat jahat hendak menghancurkan Islam dengan menebarkan keraguan terhadap Al-Quran dan hadits. Konon, ada juga yang bermaksud “baik” dan simpati kepada Islam. Beberapa nama pun disebut peneliti Jakarta itu sebagai counter examples (contoh-contoh yang bisa menjadi tandingan), seperti Fred Donner, William Graham, dan Wansbrough.
Padahal, justru di sinilah ia terlihat lugu (naif). Azami melewatkan begitu saja kritik para orientalis tersebut karena tulisannya memang tidak diperhitungkan sama sekali.
Bahkan kalangan spesialis studi Al-Quran di Barat sendiri mengabaikannya. Sama seperti Montgomery Watt, Alford Welch, atau Kenneth Cragg yang konon banyak menulis karya simpatik.
Sikap lunak itu justru mengurangi validitas dan kredibilitas karya-karya mereka di mata para koleganya. Kalau orientalis tersebut memang para meyakini kenabian Muhammad ﷺ, mengakui kebenaran Islam dan keaslian Al-Quran, mengapa mereka tidak masuk Islam saja?
Kalau sekadar wacana dan basa-basi (lips seroice), apalagi jika motivasinya demi menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam, maka itu merupakan pelacuran intelektual.
Bahwa para orientalis itu masih bertahan dengan agamanya masing-masing, semestinya membuka mata kita agar tidak bersikap Jugu dan pol dalam menyikapi tulisan sarian Islamologi Barat.
Membaca korpus orientalis seputar Al-Quran memang tidak mudah. Di samping penguasaan pelbagai bahasa (Eropa dan Semitik), juga diperlukan pengetahuan dan pemahaman van menyeluruh dan mendalam atas khazanah intelektual lslam itu sendiri bukan tahu sepotong-sepotong atau setengah-setengah.
Jika modal kita pas-pasan, amat besar kemungkinan terpukau oleh statemen-statemen yang sekilas meyakinkan, namun sesungguhnya rapuh secara metodologis maupun epistemologis. Tulisan-tulisan sarjana Barat mengenai Al-Quran seperti Noldeke dalam Geschichte des Qorans dan Mingana dengan artikelnya The Transmission of the Kuran, semuanya bertolak dari skeptisisme terhadap status AI-Quran sebagai dokumen sejarah.
Bagi mereka, Muhammad itu seorang impostor, bukan Nabi. Al-Quran itu hasil karangan Muhammad serta tim redaksi sesudahnya, bukan verbum dei (Kalamullah). Mereka seringkali mengabaikan data yang tidak mendukung asumsi-asumsinya dan memanipulasi bukti-bukti yang ada demi membenarkan teori-teorinya (of evidence).
Studi mereka berawal dan keraguan dan berakhir dengan keraguan pula. Walhasil, meskipun bukti-bukti yang ditemukan membatalkan hipotesisnya, tetap saja mereka akan menolaknya. Sebab, sesungguhnya yang mereka cari bukan kebenaran, akan tetapi pembenaran.
Baca: Orientalis Gagal Temukan adanya Filsafat Islam
Isu Integritas Teks Al-Quran
Diskusi tentang integritas teks Al-Quran bukan monopoli sarjana-sarjana Barat. Tapi hal ini sudah berlangsung sejak awal Islam berkembang.
Informasi seputar sejarah preservası, kompilasi, kodifikasi, dan transmisi Al-Quran telah direkam dan dibahas oleh para ulama terdahulu, seperti Abu Ubayd Al-Qasim ibn Sallam (wafat 224 H) dalam kitabnya Fadha’ il Al-Quran, Imam Al-Baqillani (403 H) dalam Al-Intishar li-Naqli Al-Quran, hingga Imam As-Suyuthi (911 H) dalam –ltqan fi ‘Ulumi Al-Quran, untuk sekadar menyebut beberapa contoh.
Kitab-kitab tersebut dapat dengan mudah diperoleh dan boleh dibaca oleh siapapun. Demikian pula adanya berbagai varian bacaan (qira’at) yang hingga kini masih terus dipelajari dan dihafal. Dari sanalah Azami bebas menulis bukunya itu.
Jadi, memang bukan merupakan hal yang tabu untuk diketahui atau didiskusikan. Darimana lagi para sarjana Barat memperoleh hampir seluruh data untuk studinya itu selain dari karya-karya ulama Islam? Namun, jika sumber datanya sama, mengapa kesimpulan para sarjana Barat itu berbeda dengan kesimpulan para ulama Islam?
Jawabnya, karena point of departure (titik keberangkatan) dan metodologinya memang beda. Mereka bertolak dari prasangka dan praduga, berjalan dengan kecurigaan, dan berakhir dengan keraguan. Seperti Sisyphus dalam mitologi Yunani kuno, yang dihukum oleh para dewa untuk mendorong bongkahan batu ke puncak bukit, lalu membiarkannya jatuh untuk kemudian didorongnya lagi, demikian seterusnya.
Persoalan yang dikemukakan mengenai sejumlah ayat yang konon missing (hilang) sebelum Al-Quran dikumpulkan, perbedaan antara mushaf Ubayy dan Ibn Mas’ud, dan lain sebagainya, sebenarnya telah cukup dijelaskan oleh Azami dalam bukunya itu (bab VI-XII). Saya khawatir justru pengkritik itu yang sengaja melewatkan begitu saja penjelasan panjang lebar yang dikemukakan Azami.
Satu hal yang cukup memprihatinkan adalah ungkapan “serampangan” di akhir tulisan sang peneliti itu. Menurutnya, Sayyidina ‘Umar Radhillahu ‘anhu dan sabahat terkemuka telah mengeluh setelah peresmian teks standar Utsmani, tanpa terlebih dahulu meneliti sumber dan keshahihan “keluhan” tersebut.
Padahal, ‘Umar telah lama wafat ketika Khalifah Utsman menggarap proyek kodifikasi dan standardisasi mushaf Al-Quran . Menurut Imam lbn Katsir (wafat 774 H), tidak lama setelah kodifikasi dan standardisasi kedua itu rampung, tim ahli yang terdiri atas para penghafal Al-Quran menyerahkan dan membacakan mushaf standard itu ke hadapan para sahabat, termasuk Khalifah ‘Utsman (Lihat Ibn Katsir, Fadhaa’il Al-Qur ‘an, dalam Tafsir Al-Qur ‘an Al-Azlhiim, 7 jilid, Beirut, 1966, 7:450).
Laporan umum dan terbuka ini sangat penting untuk menjamin keshahihan dan kemutawatiran Al-Quran . Setelah semua ahli dari kalangan sahabat itu setuju dan sepakat, maka ditulislah beberapa naskah acuan untuk dikirim ke kota Kufah, Basrah, Damaskus, Makkah, Mesir, Yaman, Bahrain, dan Al-Jazirah. Dan, sebuah naskah disimpan oleh Khalifah ‘Utsman di Madinah (Lihat Imâm Abu ‘Amr ad-Dani, al-Muqni’, halaman 19 dan al-Ya’qubi, Târikh, I: 170).
Sungguh amat disayangkan jika kaum Muslimin kini harus terbuang energinya untuk mengorek-orek perkara yang sudah jelas dan tuntas. Jauh lebih baik jika mereka berusaha memahami, mengamalkan, dan “membumikan” Al-Quran ketimbang meng gugat historisitas dan otentisitasnya.*
Peneliti di Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) dan pengajar di Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. Artikel tersebut pernah dimuat di Majalah Suara Hidayatullah tahun 2005
Baca: