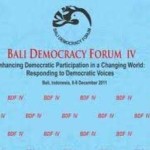Episode 1
Sudah Dipacu Belum?
“Ini masih goyang, Mas. Belum masuk panggul. Kalau sampai Selasa depan belum masuk juga, harus dicesar.”
Waduh! Kalimat yang bagiku terasa mengerikan itu meluncur begitu ringan dari Dokter Muzayyanah, SpOG.
Sejenak kulirik istriku yang tergolek lemah dengan perut mblendhuk (membesar) di kamar periksa ruang praktik bu dokter di Jalan Sultan Agung, Yogyakarta.
“Sudah final, Bu?” tentu saja rasa penasaranku masih belum hilang.
“Yaah, 90%-lah. Tapi kita tunggu perkembangannya sampai Selasa depan. Soalnya ini sudah mundur 10 hari. Kalau kelamaan, ketubannya jadi keruh dan gak baik bagi si baby,” jawab dokter berjilbab kelahiran Tuban yang sangat energik ini.
“Lagipula pada kelahiran pertama ada riwayat cesar. Ehm.. sudah dipacu belum?“ tanya beliau mengagetkanku.
“Eh…oh.., maksud njenengan? (Anda),” tanyaku plonga-plongo nggak mudheng (terbengong- bengong tidak mengerti).
“HUS Mas, HUS. Hubungan suami istri,” jawab bu dokter tersenyum penuh arti.
Weeeeladalah!
“Masih boleh to Bu?” tanyaku setengah suara.
Bu Dokter tidak menjawab. Di balik kacamatanya kulihat pandangan mata yang sangat ekspresif dan raut wajah yang setengah heran, setengah gemes, setengah geli, dan mungkin setengah mesakke. Tahu nggak mesakke? Kaciaaan deh lu!
“Nggih Bu, sendika dhawuh. Siap laksanakan tugas mulia!” kali ini jawabanku tegas, mantap, dan kuucapkan dengan sewibawa mungkin. Lagian, huh, siapa takut?
Episode 2
Wahnan ‘alaa wahnin
Tahun 1994-an, salah satu surat dalam al-Qur`an yang disuruh Pak Ustadz untuk dihafal para santri adalah Surat Luqman. Kenapa?
“Dihafal saja, sambil dicari tahu artinya. Pemahamannya biar Allah yang atur dan tancapkan dalam hatimu,” pesan Pak Ustadz.
Ya deh Pak Ustadz, sami’na wa atha’na. Namanya juga santri manutan (penurut).
Sekadar berbagi, membaca surat Luqman:14 ini kalau udah sampai ayat,
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِي
(wawashshainal insaani bi waalidaihi hamalathu ummuhuu wahnan ‘alaa wahnin wa fishaaluhu fii ‘aamaini anisykurli waliwaalidaika ilayyal mashiir) selalu terasa ada yang merinding dan bergetar di sanubari ini.
Ayat itu kurang lebih artinya, “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”
Tahun 2002, waktu anak pertamaku, si Abdurrahman Ihdal Husnayain, lahir dengan di-cesar pra kontraksi di RS PKU Muhammadiyah, rasa merinding dan getaran gempa di hati itu skalanya bertambah. Ya mungkin sekitar 5,8 pada skala richter.
Nah, 2006. Kali ini rasa itu betul-betul memporakporandakan dan meluluhlantakkan seluruh sisi relung hatiku.
Semula berawal dari kejang-kejang perut per 5 menit yang dirasakan istriku pada Jumat malam, 10 November 2006, sekitar pukul 10.00.
“Kayaknya seperti kontraksi pra kelahiran seperti yang dibilangin Bu Dokter, Bi,” kata istriku.
O ya, istriku biasa memanggilku dengan Abi.
“Posisinya juga semakin turun,” tambahnya.
Segera kusuruh istriku untuk telepon Bu Muzayyanah. Dokter yang satu ini memang jadi favorit para Muslimah Yogya, salah satunya karena keterbukaan komunikasinya yang luar biasa.
“Kalau sudah terasa kencang-kencang yang teratur, bawa ke klinik saja,” pesan bu Yanah–demikian beliau biasa dipanggil.
“Oke, ummi segera siap-siap. Kita segera datang ke Purwanggan saja!” kataku.
Purwanggan adalah nama sebuah jalan di belakang Puro Pakualaman Yogya. Bu Yanah punya klinik bersalin dan balai pengobatan di sini. Namanya “RB & BP Khadijah”.
Sampai di klinik, setelah diobservasi, hasilnya sungguh bikin dada jadi gemuruh.
“Kepala sudah bisa masuk panggul. Insya Allah kita coba lahirkan dengan spontan. Sudah bukaan 1,” kata Bu Yanah.
Entahlah, sampai kini bahkan aku belum Hong (paham), apa yang dimaksud dengan bukaan 1, bukaan 2, sampai bukaan 10 itu. Yang jelas, detik demi detik, menit demi menit, dan jam demi jam setelah itu betul-betul menjadi waktu yang sangat mengerikan bagiku. Apalagi, bagi istriku yang mengalaminya.
Tak terhitung lagi berapa kali jumlah helaan nafas, aduhan, rintihan, erangan, jeritan, gemeretak geraham, gigitan bibir, jambakan di rambut dan lengkung liuk tubuhnya yang menahan sakit. Ya, sakit sekali. Sakit yang terus bertambah-tambah.
Ya Allah…”.. hamalathu ummuhuu wahnan ‘alaa wahnin!”
Sabtu, sekitar pukul 12.00 siang, dari kamar pasien, kami (aku, istriku, ibuku) pindah ke ruang bersalin. “Sudah bukaan 5, tipis,” kata seorang perawat.
Dan, Gusti Allah, paringana pangapura (berikan pengampunan). Kok ya ndadak (tiba-tiba) terjadi peristiwa yang sangat di luar dugaan. Jarum infus copot. Padahal botol di atasnya itu berisi larutan untuk mengatur dan memacu kontraksi agar lebih sering dan lebih cepat intervalnya.
Lho, kalau lepas kan tinggal dipasang lagi?
Pasang-pasang, enak aja!
Pembuluh vena, istriku itu halus banget. Coblos tangan kanan, gagal. Coblos tempat lain masih di tangan kanan gagal. Coblos tempat lain lagi, gagal lagi, gagal lagi. Ganti beberapa coblosan di tangan kiri, masih gagal juga. Petugas pun jadi agak kalut.
Istriku? Duh Gusti, hamalathu ummuhuu wahnan ‘alaa wahnin. Ruangan ber-AC sedingin itu tak mampu menahan butiran-butiran keringat di sekujur tubuhnya. Sudah pasti ia sangat kesakitan. Sementara aku? Plonga-plongo. Oh, shit. I don’t know what I have to do (Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan).
Akhirnya petugas medis setengah nyerah. “Kita tunggu 2 jam. Kalau nggak nambah bukaannya, kita akan ganti jarum yang lebih kecil ukurannya.”
Astaghfirullah, kami pun pindah kembali ke kamar pasien. Dan memulai lagi episode penuh jeritan-jeritan memilukan itu. Ibuku yang sudah melahirkan lima kali saja jadi nervous (grogi) juga.
Aku nggak nyuruh kalian, hai para Bapak, untuk membayangkan betapa sakitnya para ibu ketika hendak melahirkan. Karena, kita para lelaki, pasti nggak akan sanggup menahannya!
Pukul 12 siang sampai 10 malam, tetap di bukaan 5! Baru kemudian bertambah ke bukaan 6, 7, 8 , 9, dan 10.
Sampai kemudian pukul 10.30 malam, kami masuk ke ruang bersalin lagi. Kugenggam erat jemari istriku. Kubacakan beberapa ayat Al-Qur`an untuknya. Sesekali kuusap keringat di keningnya dan kucium dengan lembut. Sangaaaat lembut. Jujur bin sumpah, belum pernah aku merasa secinta ini pada istriku.
Ketika sudah tiba saatnya harus mengejan, jam 11.45, kubisikkan kalimat lembut ke telinganya, “Insya Allah, ummi bisa.”
Fa inna ma’al ‘usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah-lah yang memudahkan. Dengan 2 kali mengejan, procot-procot… brol brol brol Allahu Akbar! Anakku lahir. Laki-laki. Tangisnya memecah keheningan malam. Sementara tangisku setengah ambrol.
Untuk kesekian kali kucium kening istriku. Tangisku sudah tiga per empat ambrol.
Kutatap wajah tegar ibuku yang 33 tahun lalu melahirkanku. Kuhampiri beliau, berlutut di depannya, kudekap kedua kakinya, dan akhirnya kucium jari jemari kakinya yang berkeriput. Kali ini tangisku ambrol total.
Allahumaghfirli waliwaalidayya warhamhuma kamaa rabbayani shaghiira.*/Djanto
Foto: ilustrasi
Redaksi menerima cerita-cerita pengalaman inspiratif, agar bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang