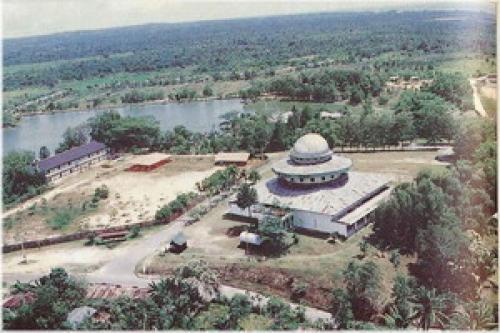HUSEIN Sangadji Baharuddin, kepala suku Moa, salah satu suku di pedalaman Sorong, Papua Barat, sudah terlihat letih. Jalannya sudah tidak tegap lagi. Padahal, tawaf yang ia lakukan baru 4 keliling. Masih ada 3 keliling lagi.
Ketika masih muda, Husein biasa berjalan kaki. “Dulu saya sering naik gunung,” ceritanya kepada penulis. Tapi itu dulu. Sekarang, Husein tak muda lagi. Ia sudah berusia 64 tahun. Kegagahannya sudah banyak berkurang.
Husein terus melangkah mengelilingi Ka’bah. Mulutnya hanya menyebut dua kata, “Allahu Akbar.” Ia tak bertanya mengapa harus mengelilingi kotak hitam tersebut. Ia hanya diperintah berjalan, maka ia berjalan.
Sebenarnya, Husein bisa saja berputar di dekat Ka’bah. Kerumunan orang-orang yang berputar searah jarum jam di sekitar Ka’bah masih agak longgar. Tapi ia diperintah oleh pimpinan rombongan untuk tawaf di lantai atas. Sebab, di dalam rombongan itu, ada jamaah yang mengenakan kursi roda. Jadi, tak bisa tawaf di dekat Ka’bah.
Husein menurut, meskipun jarak putaran yang harus dilaluinya menjadi dua kali lipat, sementara langkah Husein sudah mulai oleng.
Saat melewati Hajar Aswad, tangan Husein terangkat ke arah Ka’bah. Ia mengikuti gerakan jamaah yang lainnya. Mulutnya masih melafazkan dua kata, “Allahu akbar”. Ia juga tak bertanya mengapa harus melakukan gerakan seperi itu.
Ka’bah terlihat jelas di sebelah kiri laki-laki berperawakan kurus dan berkulit gelap tersebut. Usai berputar tujuh putaran, Husein disuruh berhenti, lalu bergeser ke bukit Safa. Husein menurut!
Baca juga: Rindu Kainama kepada Baitullah
Dari bukit Shafa, Husen kembali berjalan ke arah bukit Marwah. “Ayo, Pak, kita lari-lari,” kata penulis kepada Husein manakala memasuki wilayah lampu hijau. Lampu neon hijau yang panjangnya kira-kira sepertiga jarak antara Bukit Shafa ke Marwah memang digunakan sebagai pembatas wilayah Bathnul Wadi. Di wilayah ini jamaah dianjurkan untuk lari-lari kecil.
Husein lagi-lagi menurut. Ia berlari-lari kecil meskipun kakinya sudah pegal. Ia tak mempersoalkan mengapa harus berlari dan tidak berjalan saja. Ia juga tak mempermasalahkan mengapa harus 7 kali bolak-balik dan bukan satu kali saja.
Lalu terakhir, Husen harus merelakan rambutnya yang hitam dan kriting itu dipotong sedikit. Sang kepala suku ini lagi-lagi taat tanpa membantah.
Husein sesungguhnya bukan taat kepada pimpinan rombongan, apalagi kepada penulis. Bukan! Husein taat kepada Allah. Sebab, kata Farid Ahmad Okbah, Ketua Yayasan Al-Islam Bekasi, haji itu banyak berbicara tentang ketaatan.
“Mengapa kita rela menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan uang untuk pergi haji? Jawabnya karena kita taat kepada Allah,” jelas Farid saat berbincang-bincang dengan penulis di Dar Abu Yasir, Khalfa Tasykilat, Kamis siang (24/08/2017), menjelang keberangkatan dari Madinah ke Makkah, Arab Saudi.
Pada kesempatan lain, menjelang keberangkatan ke Jeddah, Senin (21/08/2017), Farid juga mengatakan bahwa ibadah haji sesungguhnya adalah upaya mencocokkan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu Wata’ala.
Baca juga: Kisah Hijrah untuk Ibrahim
Jika kita perhatikan memang hampir semua kehendak Allah Subhanahu Wata’ala dalam rukun, wajib, dan sunnah haji berlawanan dengan logika manusia. Betapa tidak, manusia disuruh hanya mengenakan dua lembar kain putih selama tiga hari pelaksanaan haji, itu pun tak boleh ada jahitan. Untuk apa?
Dalam keadaan seperti itu, manusia disuruh menginap di Mina, Arafah, dan Muzdalifah, padang pasir yang panas. Untuk apa?
Selanjutnya manusia disuruh melempar tiga jumrah, tawaf mengelilingi Ka’bah, berlari-lari kecil dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, menggunting rambut hingga habis, untuk apa? Semua ini berada di luar logika manusia.
Namun, dalam ibadah haji, logika ini harus diletakkan di bawah kehendak Allah Subhanahu Wata’ala. Inilah ubudiyah. Inilah penghambaan kepada Allah Subhanahu Wata’ala.
Sungguh naif jika manusia tetap menyombongkan diri sepulang mereka menunaikan haji. Labaik Allahumma labaik.* Mahladi/hidayatullah.com