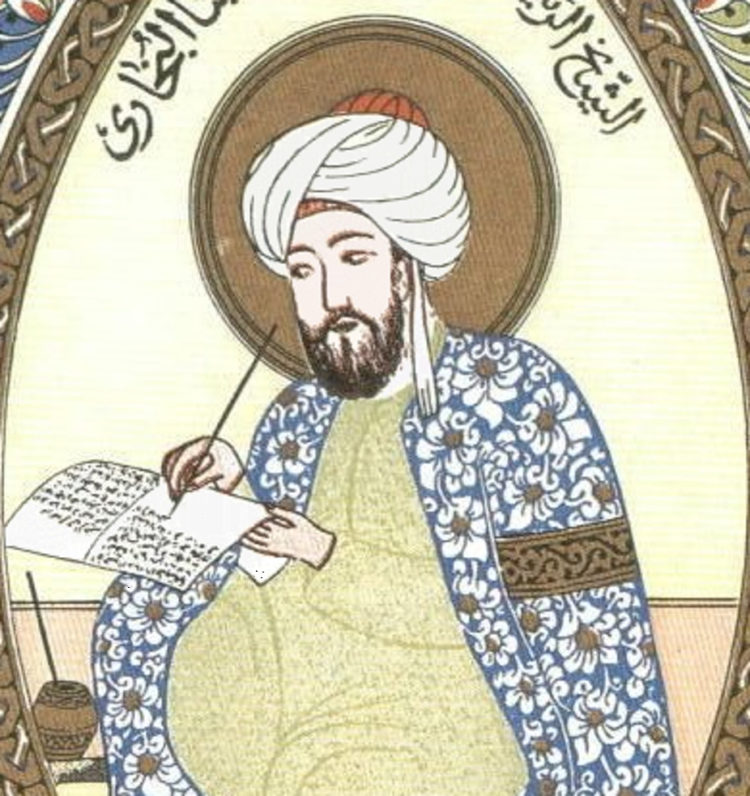Oleh: Alwi Alatas
Hidayatullah.com | ADA hubungan yang kurang harmonis, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini, di antara orang-orang keturunan Tionghoa dan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kekurangharmonisan itu tentu saja tidak bisa digeneralisir, sekaligus juga tidak bisa dinegasikan atau diabaikan. Pada simpul-simpul tertentu di dalam sejarah, hal itu kadang meledak menjadi konflik terbuka, yang ekspresinya mungkin beraroma rasisme, tetapi latar belakang utamanya sebenarnya kesenjangan ekonomi.
Orang-orang Tionghoa pada umumnya memang berbeda secara agama dan budaya dengan kebanyakan penduduk di Indonesia. Walaupun mereka sudah menetap lama di Indonesia, bahkan lintas generasi, mereka cenderung mempertahankan identitas asal mereka dari tarikan asimilasi. Dalam hal jumlah populasi mereka minoritas di Indonesia, tetapi secara ekonomi mereka ‘mayoritas’.
Perbedaan-perbedaan di atas tampaknya dipersepsikan oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai kesenjangan yang sulit dijembatani. Orang-orang Tionghoa, karenanya, kadang dilihat sebagai ancaman, dan sebaliknya warga keturunan Tionghoa cenderung melihat lingkungan Muslimnya sebagai intoleran.
Di negeri asalnya di Tiongkok, Islam memang merupakan agama yang relatif asing bagi mayoritas warganya. Namun, bukan berarti negeri itu sepenuhnya tidak bersentuhan dengan agama Islam. Jumlah penduduk Muslim di Tiongkok, sebagaimana disebut dalam sebuah artikel (Clydesdale, t.t.), adalah sekitar 20 juta, jumlah yang tidak kecil, walaupun ini hanya mewakili 1,5 % dari total populasi di negeri itu.
Baca: Pasang Surut Islam di China
Arabia dan Tiongkok sebenarnya telah terhubung sejak sebelum kemunculan Islam melalui dua jalur perdagangan, yaitu jalur sutera di utara dan jalur laut di selatan yang menghubungkan Samudera Hindia, Selat Melaka, dan Laut Cina Selatan. Sejak muncul dan berkembangnya Islam, otomatis para pedagang Muslim ikut hadir di Tiongkok (Frankel, 2016: 5-6).
Louise Levathes menulis di dalam bukunya When China Ruled the Seas bahwa pada abad ke-7 sudah ada sekitar dua ratus ribu orang Arab, Persia, India, dan Melayu yang tinggal di Kanton sebagai pedagang dan pengrajin dan pada tahun 628 pemerintah Tiongkok berusaha untuk menekan pernikahan campuran dengan mensyaratkan orang asing yang menikah dengan perempuan Tiongkok untuk tinggal seterusnya di negeri itu.
Pada tahun 651, untuk pertama kalinya pemimpin Ta-shih mengirim utusannya ke pusat kerajaan Dinasti Tang (618-907) di Xi’an (Sianfu) dengan membawa beberapa hadiah, yang diterima dengan baik oleh kaisar Tiongkok (Broomhall, 1910: 13-14). Ta-shih adalah sebutan Tiongkok pada masa itu bagi orang-orang Arab Muslim dan pemimpin Ta-shih yang dimaksud di atas adalah Khalifah Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhu.
Dinasti Tang sejak awal mengikuti perkembangan Islam di kawasan Sham dan Persia dan memiliki gambaran yang cukup akurat tentang orang-orang Arab Muslim. Mereka antara lain mencatat di era awal Dinasti Umayyah:
Ta-shih mencakup wilayah yang sebelumnya merupakan milik Persia. Orang-orangnya memiliki hidung yang besar dan jenggot yang hitam. Mereka membawa pisau dan sabuk dari perak. Mereka tidak meminum minuman keras dan tidak mengenal musik. Kaum perempuannya berkulit putih dan menutup wajahnya saat keluar rumah. Di sana ada kuil-kuil [masjid] yang besar. Setiap tujuh hari rajanya menyapa rakyatnya dari atas singasana yang tinggi di kuil itu …. Mereka shalat lima kali sehari kepada Roh Surgawi [Tuhan] … (Broomhall, 1910: 14-15; Lunde. 1985).
Pada pertengahan abad ke-8, Dinasti Tang mengalami pemberontakan serius dan meminta bantuan Abbasiyah untuk menumpas pemberontak. Khalifah al-Mansur (w. 775) kemudian mengirim ribuan tentara Muslim yang ikut membantu mengembalikan ibu kota Tiongkok ke tangan Kaisar Tang. Tentara Muslim ini kemudian diizinkan untuk menetap di wilayah Tiongkok.
Mereka menikah dengan perempuan setempat dan menjadi bagian penting dari generasi awal penduduk Muslim di negeri itu, yang nantinya dikenal dengan sebutan Hui (Frankel, 2016: 6; Lunde, 1985).
Islam di Tiongkok menjadi semakin berkembang di era Dinasti Yuan (1279-1368). Yuan merupakan bagian dari dinasti Mongol yang menaklukkan banyak wilayah, termasuk pusat kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad.
Perubahan geopolitik ini meningkatkan migrasi Muslim dari kawasan sekitar serta masuknya provinsi Yunan menjadi bagian dari Tiongkok. Yunan adalah daerah dengan populasi Muslim yang besar dan saat dianeksasi oleh Mongol memiliki gubernur yang beragama Islam, yaitu Syams al-Din Umar atau Sayyid al-Ajall (Frankel, 2016: 6; Lunde, 1985; Stuart-Fox, 2003, 57).
Ketika Dinasti Ming (1368-1644) menggantikan Dinasti Yuan, kedudukan Islam di negeri itu menjadi semakin menonjol. Sebagaimana di era Yuan, “Muslim melanjutkan bekerja sebagai saintis dan pakar Matematika di Biro Astronomi Kekaisaran dan di kantor-kantor sipil dan militer penting lainnya di seluruh kekaisaran” (Frankel, 2016: 6-7). Pada era ini terjadi peningkatan hubungan politik, ekonomi, dan keagamaan antara Tiongkok dan kepulauan Nusantara.
Baca: Menelusuri Jejak Islam China
Sejak sebelum kemunculan Islam, sudah ada orang-orang Tionghoa yang datang ke Nusantara, walaupun jumlahnya terbatas. Namun setelah abad ke-8, jumlah pedagang Tionghoa yang pergi ke kepulauan Indonesia mengalami peningkatan (Muljana, 2007: 82).
Orang-orang Tionghoa berlayar ke kepulauan Indonesia untuk berdagang maupun untuk hijrah dan menetap disebabkan perubahan sosial-politik di negeri asal mereka. Sebagian dari orang-orang Tionghoa ini ada yang sudah Muslim sejak dari tempat asal mereka. Namun, tidak sedikit pula yang masuk Islam di tempat tinggal mereka yang baru disebabkan dakwah para pendatang Muslim dari kawasan lainnya yang juga hadir di tempat ini (Kong, 2008).
Pada awal abad ke-15, Dinasti Ming beberapa kali mengirimkan armadanya ke kawasan Asia Tenggara dan beberapa tempat lainnya untuk misi diplomatik dan perdagangan. Yang memimpin misi ini adalah Cheng Ho, seorang Muslim yang berasal dari daerah Yunan, Tiongkok. Dalam perjalanannya itu ia dibantu oleh sejumlah penerjemah, di antaranya adalah Ma Huan yang juga seorang Muslim dari Tiongkok. Ma Huan kemudian menulis kisah perjalanannya dalam sebuah buku berjudul Ying-yai Sheng-lan. Dalam pelayaran-pelayaran itu mereka antara lain mengunjungi Jawa, Palembang, Samudera Pasai, Melaka, Sri Lanka, hingga Aden dan Makkah.
Saat mengunjungi Jawa, Ma Huan mengamati bahwa penduduk pulau itu bisa dibagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama adalah orang-orang Islam yang semuanya berasal dari tiap-tiap “kerajaan asing di Barat yang bermigrasi ke negeri itu sebagai pedagang”. Yang kedua adalah orang-orang Tionghoa dari daerah-daerah seperti Guangdong yang di masa lalu melarikan diri dan kemudian menetap di Jawa. Yang ketiga adalah penduduk setempat. Saat menjelaskan tentang orang-orang Tionghoa di wilayah itu, Ma Huan mengatakan bahwa “banyak di antara mereka yang mengikuti agama Islam, melakukan penebusan dosa dan berpuasa” (Ma Huan, 1970 93). Sumber kontemporer Tiongkok lainnya bahkan menyebut bahwa semua orang Tionghoa yang ada di tempat itu adalah Muslim (Lombard & Salmon, 1993, 115).
Pelayaran Cheng Ho ini beririsan waktunya dengan era kemunduran Kerajaan Majapahit dan dimulainya proses Islamisasi di Jawa secara besar-besaran. Terjalinnya hubungan baik antara Dinasti Ming dan beberapa kerajaan lokal seperti Melaka membantu meningkatkan politik dan perekonomian kerajaan-kerajaan lokal ini dan pada saat yang sama menggerogoti pengaruh regional Majapahit (Wade, 2004: 31-32). Pada penghujung abad ke-15 dan awal abad ke-16, sejarah akan menyaksikan runtuhnya Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Pulau Jawa.
Cukup pentingnya hubungan antara Tiongkok dan Nusantara membuat sebagian sejarawan mempertimbangkan bahwa Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, sebenarnya berasal dari Tiongkok, dan bukan dari Arab, Persia, atau India. Pandangan ini bermula dari M.O. Parlindungan yang menyebut di dalam bukunya Tuanku Rao tentang dua kronik Tionghoa yang menurutnya ditemukan oleh Residen Poortman pada tahun 1928, masing-masing di Klenteng Sam Po Kong di Semarang dan Klenteng Talang di Cirebon. Dua sumber yang diklaim Parlindungan ini kemudian digunakan oleh Prof. Slamet Muljana (2007: 54-75), bersama beberapa sumber lainnya, untuk menjelaskan tentang proses Islamisasi di Jawa. sambung<<<2>>> Wali Songo keturunan Tionghoa ?