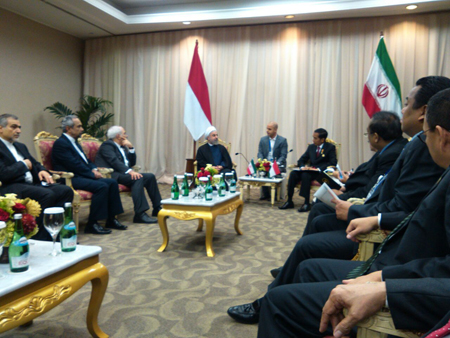Sambungan artikel KEDUA
Oleh: Muh. Nurhidayat
Hubungan Soros dengan Tanoe, pemilik MNC Group—yang mesra—tidak hanya di bidang ekonomi bisnis. Keluar-masuknya bos media tersebut ke sejumlah Parpol (dari Partai Nasdem, Partai Hanura, hingga mendirikan Partai Perindo), menunjukkan bahwa alasan masuk akalnya untuk menguasai panggung politik. Dengan kekuatan media yang menaunginya di bawah MNC, (dianggap) tidak sulit bagi Tanoe untuk mengangkat citra dirinya memenangkan Pemilu.
Begitu pula bagi Soros (kapitalis asing), media massa di bawah kekuatan MNC akan mudah mengubah citra miliarder trans-nasional itu. Masyarakat akan dibuat lupa bagaimana kiprah Soros yang pernah mengantar Indonesia bersama sejumlah negara lainnya ke lembah kelam yang bernama krisis moneter pada 1997 silam. (Zein, 2013).
Hubungan Soros dengan Tanoe menunjukkan keseriusannya untuk menguasai Indonesia. Sejak awal, pengusaha media itu (Tanoe) memang sudah dipersiapkan untuk mencengkeramkan hegemoninya di bumi nusantara. Soal terjunnya Tanoe ke dunia politik tentu saja bukan karena kebetulan. Meski harus diakui, langkah Tanoe tersebut mendapat perlawanan ‘kecil’ dari kaum nasionalis—yang diwakili para akademisi dan penggiat LSM. (Zein, 2013).
Belum lama ini, kasus sowan-nya dua pimpinan DPR-RI, Setya Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye politik Donald Trumph, secara tidak langsung membuka tabir eratnya hubungan Tanoe dengan pengusaha AS yang terkenal rasis dan anti kaum minoritas itu.
Dengan demikian menjadi jelas bahwa peningkatan kontrol atas industri media global oleh sejumlah kecil bos perusahaan multinasional seperti yang dilakukan Rupert Murdoch dan Silvio Berlusconi sebenarnya menuai kritikan. (Hargreaves dalam Keeble, 2005)
Dalam wacana etika media, sikap Berlusconi yang dicontoh para pemilik media Indonesia yang ‘terjatuh’ dalam pragmatisme politik praktis, menunjukkan bahwa mereka merupakan penganut teori etika egoisme. Teori etika egoisme menyatakan bahwa semua tindakan manusia dilakukan untuk—mendewakan—kepentingan individu atau diri sendiri (Littlejohn & Foss, 2009 : 353).
Bentuk Komunikasi Politik ala Berlusconi
Ada 3 bentuk penerapan komunikasi politik ala Berlusconi, yang ternyata ditiru di Indonesia.
Pertama, melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap partai dan capres lain. Dalam konteks Indonesia, parpol yang pengurusnya tidak memiliki jaringana media—terutama televisi—secara sporadis diberitakan aib-aib politiknya, hingga nampak benar bahwa partai yang di-bully terlihat semakin ‘buruk’ di mata konsumen media. Padahal parpol yang di-backing jaringan media juga banyak memiliki aib-aib politik.
Hal ini memperkuat asumsi teori agenda setting media—oleh McCombs & Shaw—yang menyatakan, bahwa di antara berbagai topik (isu) yang dimuat media massa, topik (isu) yang mendapat lebih banyak perhatian dari media akan menjadi lebih akrab bagi khalayaknya dan akan dianggap penting dalam suatu periode waktu tertentu, dan akan terjadi sebaliknya bagi topik (isu) yang kurang mendapat perhatian media. (Sendjaya, Pradekso, dan Rahardjo, 2007)
Memang dalam kajian komunikasi massa, pengaruh eksposur berita kepada khalayak cenderung bersifat jangka pendek. Jika tidak diberitakan secara kontinyu, maka dikhawatirkan khalayak akan melupakan isu tersebut. Sehingga berita-berita aib parpol pesaing perlu diberitakan secara terus-menerus agar khalayak tetap ingat dan bila perlu, ‘termakan’ isu berita-berita secara sporadis tersebut.
Pendapat ini didukung oleh penelitian Norris dkk. (1999) mengenai Pemilu Inggris yang menunjukkan bahwa ekspose terhadap posisi partai yang terkandung dalam siaran berita dapat secara signifikan mempengaruhi sikap (khalayak) terhadap partai dalam jangka pendek (Mc.Quail, 2011).
Kedua, melakukan pencitraan yang berlebihan terhadap partai dan capresnya sendiri. Di Italia, pencitraan yang berlebihan melalui eksposur pesan yang bombastis atas ‘kebaikan’ Berlusconi dilakukan semua media di bawah jaringan Fininvest dan Mediaset. Malah program siaran infotainment pun tidak luput dari kampanye terselubung sehingga melambungkan nama Silvio Berlusconi dan membawanya ke kursi perdana menteri pada 1994, kemudian terpilih kembali pada 2001 dan 2008 (Thussu, 2010).
Sejak jaringan media massa berdaya jangkau nasional Italia—seperti televisi—milik Berlusconi menjadi sarana komunikasi politik secara besar-besaran, opini publik—dari kalangan masyarakat awam—tentang politik seakan menjadi homogen (memandang Berlusconi sebagai calon pemimpin yang bagus), meskipun kelompok rasionalis—dari kalangan masyarakat terpelajar—tidak sejalan dengan opini tersebut. (Shin & Agnew, 2008).
Selain itu, campur tangan Berlusconi, dengan memerintahkan stasiun televisinya untuk memberikan eksposure pesan (kampanye terselubung) Forza Italia secara bombastis, menjadikan partai tersebut sebagai kekuatan baru pada Pemilu 1994. (Shin & Agnew, 2008).
Pengelola jaringan televisi membuat program siaran tidak hanya didasarkan pada keinginan penonton dan pengiklan saja, tetapi juga faktor lainnya, seperti politik. Padahal pembuatan program sesuai kepentingan (politik praktis) melahirkan masalah (pelanggaran) etika karena cenderung manipulatif, mencabut hak publik untuk mengetahui informasi yang sebenarnya, serta melahirkan self-censorship berlebihan (karena ketakutan) dari kru media dalam mengangkat tema kontroversial—yang tidak disukai pemilik media. (Peresbinossoff, 2008).* (BERSAMBUNG)
Penulis dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ichsan Gorontalo, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro