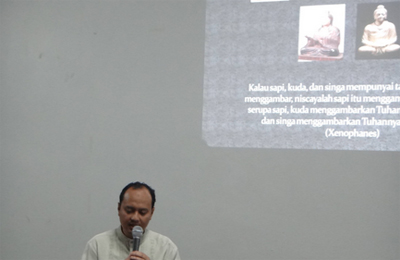“Fakta, Masalah, dan Solusi; Faktanya adalah Indonesia telah merdeka, masalahnya setelah merdeka lalu apa? Solusinya adalah seminar pembangunan”.
Rudy bersitegang dengan kawan-kawannya dalam kongres PPI seluruh Eropa, Rudy kukuh dengan gagasannya; melaksanakan Seminar Pembangunan, sementara kelompok mahasiswa lainnya menginginkan mengikuti arus politik yang tengah terjadi di Indonesia, mendukung Front Nasional. Rudy tidak saja bersitegang dengan kawan-kawannya, tetapi juga dengan Duta Besar RI untuk Jerman Barat.
Inilah adegan paling menarik bagi saya dalam film Rudy Habibie (2016) karya Hanum Bramantyo. Film ini diangkat dari kisah nyata Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie ketika kuliah di Jerman. Latar isu Front Nasional untuk pembebasan Irian Barat tahun 1959 menjadi salah satu konflik cerita. Waktu itu siapa yang menolak Front Nasional maka dianggap pemberontak.
Seminar Pembangunan adalah gagasan masa depan Indonesia. Salah satunya impiannya membangun industri manufaktur dan teknologi yang bermanfaat dan bepenaruh untuk dunia. Menurut Rudy, tidak hanya tentang industri dirgantara, tapi juga industri transportasi, perkapalan, dan sebagainya
Gagasan Habibie muda yang dipanggil Rudy menemui pasang surut di sana-sini, intrik politik yang berlangsung di Indonesia membuat visi dan mimpinya diperdebatkan, sedangkan di saat bersamaan ada tawaran pemerintah jerman untuk mewujudkannya. Di sinilah nasionalisme Habibie diuji.
“Perjalanan ini masih panjang, saya tak akan pernah menyerah, saya mencintai Indonesia, saya percaya Indonesia, dan saya akan kembali. Untuk terus berjuang, untuk ibu pertiwi.” Begitu prinsip JB Habibie muda yang ditampilkan di akhir film. Mimpinya harus dibayar dengan perjuangan yang berat.
Baca: BJ Habibie Tanggapi Santai Cercaan Mantan Menteri Malaysia
Filmnya berhenti sampai sini. Tapi kisahnya masih berlanjut.
Tahun 1974 Habibie pulang ke Indonesia dengan membawa mimpinya. Gagasannya dalam Seminar Pembangunan, berupa mimpi membangun Indonesia di masa depan segera bisa dilaksanakan.
Benar saja, tahun 1989 majalah Historia mencatat, melalui Keppres No. 59 Habibie sebagai Menristek sudah bisa mengkonsolidasii ‘industri strategis’ dengan memimpin BPIS. BPIS adalah Badan Pengelola Industri Strategis yang menaungi 10 perusahan manufaktur dan teknologi.
Di antara perusahaan itu adalah IPTN (bidang dirgantara), PT PAL Indonesia (bidang perkapalan), PT Pindad (bidang senjata dan pertahanan), PT Industri Kereta Api/INKA (bidang industri perkertaapian), dan perusahaan penting lainnya.
Beberapa perusahaan di bawah pimpinan Habibie mampu menunjukkan kapasitasnya dengan produk berkualitas. IPTN dan INKA menjadi yang paling menonjol.
IPTN berhasil mengembangkan pesawat N250 dengan menerapkan advanced turboprop fly by wire, yang merupakan teknologi tercanggih saat itu. Pesawat penumpang berkapasitas 50 orang yang dikembangkan dari rancangan asli IPTN itu ketika diluncurkan pada 1995 menjadi primadona di kelasnya sekaligus mencemaskan produsen pesawat dunia.
Seakan tak mau kalah, INKA juga berinovasi lewat pengembangan kereta api eksekutif berkecepatan tinggi: Argo Bromo JS950. Pada pengembangan pertama, INKA memanfaatkan lokomotif produksi GE Transportation System, Amerika Serikat (AS). Mampu berkecepatan 100 km/jam.
PT Pindad dan PT PAL juga setali tiga uang sebagai perusahaan yang melahirkan produk-produk canggih. PT. Pindad sukses membangun sejata SS-1 dan SS-2, senjata serbu otomatis yang kemampuannya di bawah AK-47. Sedangkan PT PAL berhasil membangun aneka kapal, dari kapal perang hingga tanker. Lagi-lagi perusahaan ini juga mengejutkan dunia.
Baca: Aksi Global untuk Peluncuran Konferensi Rakyat Menentang IMF-WB
Namun, ketika industri manufaktur dan teknologi anak bangsa ini mulai tumbuh dan sukses. Krisis moneter 1998 datang mengundang IMF. Salah satu klausul dalam syarat penawaran IMF adalah menghentikan pendanaan ke perusahaan strategis, padahal waktu itu perusahaan lagi butuh dana. Akhirnya BPIS dipaksa runtuh karena permintaan IMF yang ‘mencurigakan’.
Salah satu ‘anak intelektual’ Habibie, Jusman Syafii Djamal, menceritakan kekecewaannya seperti dikutip Republika. “Kita kadang-kadang juga menyesali kenapa ada krisis ekonomi 97-98. Mengapa juga IMF membatalkan semua program yang telah dirancang 20 tahun? Kita sudah pada ujung keberhasilan, tapi krisis melanda seolah-olah kita kayak kena tsunami,” kata dia.
Habibie sendiri tak pernah lupa akan runtuhnya perusahaan-perusahaan strategis seperti IPTN yang ia bangun akibat krisis ekonomi 1998 dan membuat perginya ilmuwan-ilmuwan top Indonesia ke luar negeri akibat pemecatan massal. Suara Habibie terasa getir saat mengenang peristiwa itu.
Suatu hari kepada wartawan dan para puluhan peneliti Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang berkumpul di kediamannya, Habibie bercerita jika ia merasa telah membunuh “anak” yang telah dilahirkan, dibesarkan, dan kemudian terpaksa harus hengkang jauh darinya.
Kegetiran Habibie Mengenang Runtuhnya Industri strategis Indonesia ini ditulis Kompas.
“Padahal, Anda tahu di situlah tempat manusia-manusia unggul di mana mereka membuat produk yang dibutuhkan banyak orang,” tutur Habibie.
“Saya serahkan 48.000 orang dan saya serahkan semua itu untuk membuat apakah kereta api, pesawat terbang, apa senjata. Total turn over 10 juta dollar AS, tapi karena reformasi diimbau oleh IMF, kita ramai-ramai membunuhnya. Di kacamata saya, itu kriminal,” ujar Habibie dengan emosional.
“Anda tahu, saya sempat protes industri strategis ditukarkan. Tapi, tidak ada yang mendengar.”

Kegetiran Habibie semakin menjadi manakala 16.000 orang yang dipecat ketika itu mendatanginya. Mereka yang tak lagi memiliki pekerjaan merasa kebingungan harus mencari nafkah dari mana. Habibie pun hanya bisa merelakan mereka untuk mencari pekerjaan di luar negeri yang juga sedang gencar memproduksi industri strategisnya.
Alhasil, para ahli Indonesia “hijrah” dan bekerja di perusahaan asing, seperti Boeing dan Airbus. Mereka juga bekerja di Thailand, Brasil, dan Turki.
Namun kedatangan IMF ke Indonesia saat krisis ekonomi 1997-1998 dengan alasan ‘memberikan suntikan dana yang disertai dengan segala persyaratannya’ memiliki resiko. Salah satu persyaratan IMF adalah ‘memaksa’ pemerintah Indonesia memprioritaskan proyek-proyek negara yang tidak padat modal, seperti proyek di sektor pertanian dan kerajinan, dibandingkan proyek-proyek padat modal, seperti industri manufaktur berteknologi tinggi.* <<(BERSAMBUNG)>> “Ini Kriminal….”