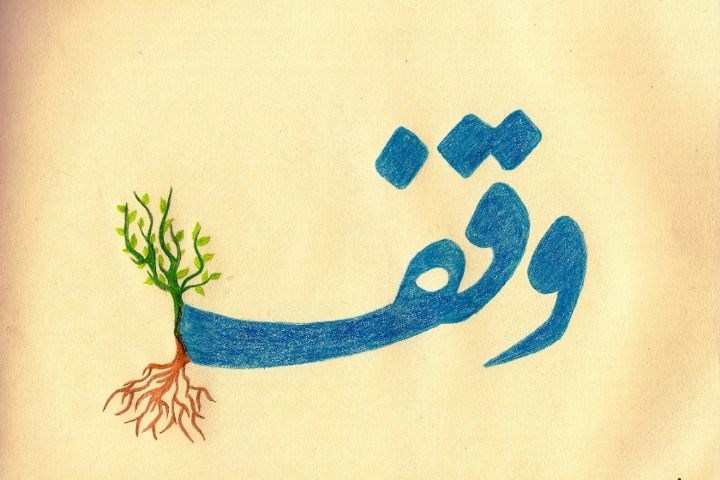Sambungan artikel KEDUA
Oleh: Adif Fahrizal
Nama Arab Rasa Nusantara
Oleh sebagian orang, merebaknya hal-hal berbau Arab -yang sedikit banyak berhubungan dengan Islamisasi, walau tidak selalu demikian- dipandang secara negatif, bahkan sinis. Putri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, Marina Muhammad misalnya menyatakan bahwa Arabisasi adalah suatu bentuk “penjajahan budaya”. Sesungguhnya tuduhan ekstrim semacam ini hanyalah suatu ungkapan emosional belaka yang sangat subyektif dan tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Apakah masuknya pengaruh asing dalam budaya suatu bangsa bisa begitu saja dipahami sebagai penjajahan budaya?
Bagaimana jika bangsa tersebut secara kreatif menggunakan pengaruh luar itu sedemikian rupa sehingga menjadi suatu hal yang otentik? Suatu hal yang meskipun datang dari luar namun justru berbeda dengan bentuk di tempat asalnya dan akhirnya menjadi milik mereka sendiri.
Ini dapat dilihat dari kasus banyaknya nama-nama Arab di Jawa yang mengalami hibridisasi dengan nama-nama Jawa (misal Ahmad Purnomo, Anwar Haryono, Nur Aini Setiawati, Sinta Nuriyah dsb).
Hibridisasi ini menunjukkan bahwa Muslim Jawa memiliki kreativitas untuk memadukan pengaruh luar dan “budaya lokal” yang kemudian menghasilkan sesuatu yang otentik alias khas Jawa. Di sisi lain nama-nama Arab murni yang beredar di kalangan Muslim Jawa sekalipun kerap terdengar asing di telinga orang Arab sendiri walau artinya baik.
Di kalangan Muslim Jawa -dan Muslim Indonesia pada umumnya- nama-nama seperti Burhanuddin (bukti agama), Zainuddin (perhiasan agama), atau Syamsul Arifin (matahari orang-orang arif) sering dipakai sebagai nama diri yang disandang seseorang sejak lahir namun bagi orang Arab nama-nama semacam itu bukanlah nama diri (asma). Di negeri-negeri Arab nama-nama tersebut adalah laqob (gelar) yang diberikan kepada seseorang yang memiliki sifat atau kelebihan tertentu yang menonjol pada dirinya.
Yang juga menarik di kalangan Muslim Jawa berlatar belakang pesantren banyak yang menggunakan nisbah nama-nama para ulama sebagai nama diri (misal Bukhori, Nawawi, Ghozali, Dimyathi, Suyuthi, dll), hal mana tidak akan kita temukan dalam masyarakat Arab.
Yang lebih unik lagi, tidak jarang kaum Muslim Jawa berlatar belakang pesantren menamai anaknya dengan judul kitab-kitab kuning seperti “Sullamut Taufiq” (kitab akidah dan fikih dasar), “Fathul Qorib” (salah satu kitab fikih mazhab Syafi’i), “Fathul Bari” (kitab syarah Shahih Bukhari), dan sebagainya. Ini pun tidak dikenal dalam masyarakat Arab sendiri.
Mereka yang menamai anak-anaknya dengan judul kitab kuning biasanya beralasan bahwa itu adalah suatu bentuk tabarrukan atau ngalap barokah dengan harapan berkah ilmu yang terkandung dalam kitab-kitab itu mengalir pada anak-anak mereka.
Jika dikaitkan dengan tradisi masyarakat Jawa, memang biasanya orang-orang Jawa yang terdidik menamai anak-anaknya dengan nama-nama yang mengandung nilai harapan yang sangat tinggi. Ini bisa dilihat dari nama-nama kaum priayi seperti Joyokusumo, Joyodiningrat, Atmokusumo, Singonegoro, dan sebagainya yang mencerminkan harapan akan kehormatan dan ketinggian martabat.
Dalam konteks ini, penggunaan nama-nama Arab yang diambil dari laqob, nisbah nama ulama, atau judul kitab kuning di kalangan santri Jawa sesungguhnya paralel dengan penggunaan nama-nama Sansekerta atau Kawi (Jawa kuno) di kalangan priayi. Kedua-duanya sama-sama menunjukkan persepsi orang Jawa tentang arti penting nama sebagai sebuah harapan. Menurut Kuipers ini adalah fenomena khas Jawa yang tidak selalu ditemukan di tempat lain.
Ia mencontohkan di Pulau Sumba dan bahkan di Barat orang tua memberi nama anaknya tanpa terlalu memikirkan apa arti nama tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola pemakaian nama Arab di tengah masyarakat Jawa sesungguhnya memiliki kekhasan yang membedakannya dengan pola pemakaian nama Arab di masyarakat Arab sendiri. Pola pemakaian ini bisa disebut sebagai ragam bahasa Arab ala Jawa atau ala Nusantara.
Pada akhirnya fakta bahwa banyak orang Jawa menamai anaknya dengan nama-nama Arab yang memiliki arti yang baik -betapapun nama itu terdengar asing di telinga orang Arab- menunjukkan bahwa Islamisasi dan Arabisasi memang berjalin berkelindan satu sama lain sehingga mustahil memisahkan keduanya.
Di sisi lain fakta bahwa orang Jawa mengadopsi, mengadaptasi, dan juga menghibridisasi nama-nama Arab menunjukkan bahwa apa yang disebut Arabisasi itu tidak berjalan satu arah. Alih-alih sekadar menjadi konsumen pasif -yang bisa ditafsirkan sebagai suatu bentuk “keterjajahan budaya”- Muslim Jawa mengolah sedemikian rupa nama-nama Arab menjadi suatu pengungkapan diri yang otentik. Arabisasi -yang berkelindan dengan Islamisasi- tidak dipandang secara paranoid dan alergik sebagai ancaman bagi identitas dan “budaya asli” Jawa melainkan sesuatu yang justru memperkaya identitas dan budaya itu sendiri.*
Penulis adalah mahasiswa S2 Sejarah Universitas Gajah Mada