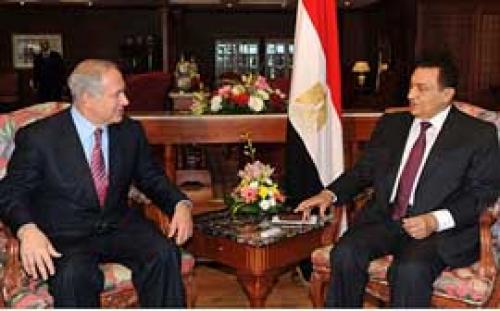Oleh: Musthafa Luthfi
PERSETUJUAN Jenewa antara Menlu AS, John Kerry dan Menlu Rusia, Sergei Lavrov pada Sabtu (14/09/2013) mengenai krisis Suriah, oleh banyak pengamat Arab sebagai nuktah tahawwul (titik perubahan) paling menonjol saat krisis tersebut sedianya telah memasuki tahap menentukan pasca penggunaan senjata kimia oleh pasukan rezim yang dibuktikan oleh tim penyidik PBB.
Dengan kesepakatan dua negara utama dalam anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB tersebut, negeri Syam yang sedianya sudah di ambang serangan AS dan sekutunya, setidaknya untuk sementara waktu bisa bernafas lega terutama rezim Assad. Sedangkan dari kubu oposisi, untuk kesekian kalinya harus “gigit jari“ lagi atas sikap “lemah“ Barat menghadapi aksi pembantaian rezim.
Sebagaimana telah dimaklumi, persetujuan yang dibidani Rusia tersebut intinya berisi kesepakatan pemusnahan senjata kimia Suriah selambatnya pada 2014 sebagai konsesi urungnya serangan Barat atas rezim Assad. Moskow berharap, persetujuan itu sebagai pembuka jalan menuju terlaksananya Konferensi Jenewa ke-2 yang terus mengalamai penundaan.
Konferensi tersebut bertujuan untuk membahas upaya penyelesaian krisis Suriah secara damai yang belum mendapat respon serius dari pihak-pihak yang bertikai. Penundaan ini juga disebabkan rasa percaya diri masing-masing pihak (rezim dan oposisi) bahwa mereka akan mampu mengatasi lawannya dengan kekuatan militer.
Kekuatan militer yang hampir berimbang terutama di darat dan pasokan senjata-senjata canggih ke pihak oposisi menurut sebagian analis strategi Arab sebagai salah satu penyebab berlarut-larutnya krisis itu. Demikian pula dengan dukungan kuat dua sekutu utama Assad, Rusia dan Iran menyebkan semakin sulit secara militer untuk menjatuhkan rezim tanpa bantuan serangan Barat seperti kasus di Libya.
Sudah kerap kali disuarakan tentang kejatuhan rezim Bashar Assad yang di ambang pintu menyusul kemajuan demi kemajuan yang dicapai pasukan oposisi yang dimotori oleh Jeisy Al-Hurr (Tentara Kebebasan) di lapangan dengan merebut wilayah yang sebelumnya berada dibawah kontrol pasukan rezim. Namun tak lama berselang muncul pula berita sebaliknya tentang perebutan kembali wilayah yang dikuasai oposisi.
Publik umum Arab akhirnya merasa terkecoh oleh pemberitaan yang setiap saat berubah dan melihat bahwa krisis tersebut bakal berlarut-larut bila tidak ada kata sepakat masyarakat internasional. Di lain pihak Iran dan Rusia menunjukkan sinyal bahwa mempertahankan rezim adalah harga mati.
Dengan tercapainya persetujuan terakhir antara AS dan Rusia dikahawatirkan perang akan semakin berlarut tanpa diketahui kapan akan berakhir dan kesudahannya seperti apa. Ibarat nasi telah menjadi bubur, negara-negara Arab pendukung oposisi salah perhitungan tentang koalisi Iran-Rusia-Suriah yang demikian solid, sementara koalisi sejumlah negara Arab-Barat pendukung oposisi kelihatan tetap lemah.
Lalu yang menjadi pertanyaan mendasar pasca persetujuan Jenewa tersebut adalah mengapa Suriah akhirnya melepaskan dengan mudah salah satu kartu kekuatannya (senjata kimia) yang selama ini sebagai balance of fear (perimbangan ketakutan) di kawasan terutama terkait perimbangan dengan senjata nuklir, kimia dan kuman Israel.
Apakah dengan persetujuan penghancuran senjata kimia Suriah tersebut rezim Assad dan sekutunya (Iran dan Rusia) berada dalam posisi lemah sehingga tidak akan mampu lagi menghadapi tekanan sehingga akan siap menerima syarat-syarat dari negara-negara pendukung oposisi? Jawabannya bisa ya dan bisa pula tidak mengingat krisis ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit diluruskan.
Jaminan Rusia
Sejumlah analis yang pro oposisi melihat bahwa keputusan rezim menghancurkan senjata kimia merupakan “kekalahan telak” Assad menghadapi oposisi ke depan karena tidak ada lagi “kartu“ pamungkas yang diharapkan. Dengan demikian, perimbangan militer di lapangan akan semakin menguntungkan oposisi ditambah dengan semangat juang oposisi yang lebih tinggi ketimbang pasukan Assad.
Bila krisis yang sudah berlangsung tiga tahun itu akhirnya sepakat diakhiri di meja perundingan, rezim Assad sudah tidak memiliki kekuatan penekan lagi sehingga terpaksa akan menerima dikte dan syarat dari negara-negara Barat dan kawasan pendukung oposisi. Itulah ringkasan opini yang berkembang di pihak pendukung oposisi Suriah setelah persetujuan pemusnahan senjata kimia negeri tersebut.
Sudut pandang di atas akan mudah diimplementasikan di lapangan apabila kesepakatan pemusnahan senjata kimia itu tanpa syarat. Rusia sebagai pemrakasa kesepakatan tetap menekankan pada syarat tertentu demikian pula dengan Presiden Assad yang tegas menolak pemusnahannya bila syarat yang diajukan tidak dipenuhi seteru dan negara-negara pendukungnya.
Presiden Rusia, Vladimir Putin mislanya mengingatkan bahwa tidak mudah memaksa suatu negara untuk memusnahkan senjatanya pada saat pihak lain bersiap-siap menyerangnya. “Keputusan ini sebagai langkah penting menuju penyelesaian damain krisis dan keputusan ini dapat dilaksanakan setelah kita mendengar AS dan negara-negara lainnya menghentikan rencana mengatasi krisis dengan kekuatan militer”.
Pernyataan Putin tersebut sebagai bentuk jaminan Rusia bahwa pemusnahan senjata kimia rezim Assad tidak dapat diterapkan apabila AS dan sekutunya di kawasan tidak menghentikan suplai senjata ke oposisi.
“Jaminan ini membuktikan bahwa kesediaan rezim memusnahkan senjata kimia bukan memperlemah posisinya, bahkan sebaliknya semakin memperkuat posisi pemerintah menghadapi konspirasi,” papar sejumlah analis Arab pro rezim Assad.
Penafsiran pernyataan Presiden Putin itu dapat juga dilihat dari pernyataan Bashar Assad yang menegaskan inisiatif ini tidak akan diterapkan tanpa diterapkannya persyaratan Suriah yakni keseriusan AS mengupayakan stabilitas di kawasan, menghentikan ancaman invasi dan pengiriman senjata ke kelompok opisisi.
Melihat pernyataan Assad tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pemusnahan senjata kimia sangat sulit dilaksanakan dengan syarat yang hampir tidak mungkin dilaksanakan pihak lain. “Pernyataan ini sebagai bukti posisi pemerintah semakin kuat dengan kepercayaan dan kemampuan untuk melanjutkan konfrontasi melawan konspirasi dunia sampai kapan pun,” ujar sejumlah pengamat lain pendukung rezim.
Beberapa pengamat lainnya yang menjadi corong rezim di sejumlah media Arab menyebutkan bahwa kesediaan rezim memusnahkan senjata kimia sebagai bentuk tangung jawab etika dan kemanusiaan untuk menghindari invasi terhadap rakyat. “Sikap pemerintah tersebut sekaligus mematahkan tuduhan bahwa pemerintah dan pasukan Suriah membantai rakyatnya,” papar mereka.
Sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga, kesediaan pemusnahan senjata kimia dikarenakan rezim telah memiliki pengganti senjata strategis lainnya yang dapat sebagai perisai menghadapi ancaman luar. Diperkirakan rudal S300, S400, S500 dan rudal Alexander buatan Rusia yang sangat canggih telah berada dalam genggaman rezim Assad yang dapat dimanfaatkan lebih efektif menghadapi ancaman luar ketimbang senjata kimia.
Satu lagi, kesepakatan sebagai buah upaya diplomasi intensif Rusia tersebut rentan untuk digagalkan baik oleh rekayasa rezim Assad sendiri maupun oleh negara-negara kawasan pendukung oposisi. Bila akhirnya gagal, kelihatannya posisi rezim Assad masih tetap kuat, sementara di pihak lain (AS dan sekutunya) nampaknya masih ragu-ragu untuk melakukan serangan langsung ke negeri Syam itu kecuali melalui peningkatan pasokan senjata canggih ke Tentara Kebebasan.
Kontradiktif
Penting juga mengetahui posisi Israel yang sebenarnya paling berkepentingan dengan pemusnahan senjata kimia tersebut. Tel Aviv telah merespon kesepakatan AS-Rusia terkait senjata kimia Suriah itu dengan dua sikap yang kontradiktif yakni di satu sisi menyambutnya dengan gembira dan di sisi lain tetap menaruh kekhawatiran tentang melemahnya peran AS di kawasan.
Sikap gembira disebabkan salah satu senjata strategis penyeimbang kekatukan antara kedua negara akan dimusnahkan sesuai kesepakatan jenewa tersebut. Selain itu, Israel melihat kesepakatan tersebut akan semakin membuka peluang bahwa perang saudara akan bertambah berlarut dan tidak jelas kesudahannya, sesuai yang diinginkan para pemimpin zionis.
Sedangkan sikap khawatir itu bersumber dari kekhawatiran negeri Yahudi tersebut tentang kemungkinan inisiatif Rusia itu dapat berhasil sehingga krisis Suriah akhirnya diselesaikan lewat perundingan Jenewa ke-2. Bila berhasil maka peran Rusia akan semakin menonjol di kawasan sehingga AS tidak terlalu bergairah untuk mengatasi masalah nuklir Iran yang menjadi kekhawatiran Israel selama ini.
Kekhawatiran tersebut merupakan bentuk fobia eksistensi yang selama ini selalu menghantui para pemimpin zionis menghadapi setiap perubahan di kawasan yang tidak menguntungkan Israel. Karena itu, PM Benjamin Netanyahu menilai urungnya serangan ke salah satu negara Arab yang berbatasan langsung dengan negerinya sebagai “gempa bumi regional yang belum pernah disaksikannya sejak Israel berdiri.“
Kekhawatiran anak emasnya itu pula yang menyebabkan, Menlu Kerry segera berkunjung ke Israel dan menegaskan dalam pernyataannya di kota pendudukan al-Quds bahwa opsi militer terhadap Suriah masih terbuka.
“Persetujuan tersebut juga akan memusnahkan seluruh senjata kimia Suriah,“ tandasnya menenangkan para pemimpin Israel sambil menyebutkan kesepakatan Jenewa tersebut belum final.
Namun kelihatannya pernyataan Kerry tersebut tidak serta merta membuat para pemimpin negeri zionis itu tenang bahkan kekhawatiran masih mewarnai komentar-komentar di sejumlah media terkemuka negeri itu. Sebagian pihak di Israel menyebutkan bahwa Kaesar Rusia telah mengambilalih peran Barat untuk menyelesaikan krisis Suriah yang bisa jadi tidak menguntungkan Israel.
Kalangan politisi dan media massa terkemuka Israel berusaha meyakinkan publik setempat bahwa kesepakatan pemusnahan senjata kimia Suriah merupakan prestasi Israel tanpa imbalan karena ibaratnya seperti “mendapat undian“ yang tidak terduga sebelumnya. Namun harian Maariv justeru melihat semakin kuatnya peran Rusia pasca kejatuhan Qadhafi di Libya berbalik dari dua sekutunya, AS dan Inggris yang dinilai semakin melemah.
Terlepas dari kekhawatiran negeri zionis itu, yang jelas krisis Suriah pasca kesepakatan Jenewa itu semakin tidak menentu, ibaratnya, rakyat negeri itu yang mayoritas Sunni masih belum menemukan secercah cahaya harapan agar bisa keluar dari pemerintahan minoritas Syiah Alawiyah yang represif. Mereka masih berada dalam bayang-bayang tetap berlarutnya krisis yang semakin menghancur-luluhkan negeri dan menimbulkan korban jiwa yang lebih dahsyat lagi.*/Sana`a, 19 Zulqa`dah 1434 H
Kolumnis hidayatullah.com, tinggal di Yaman