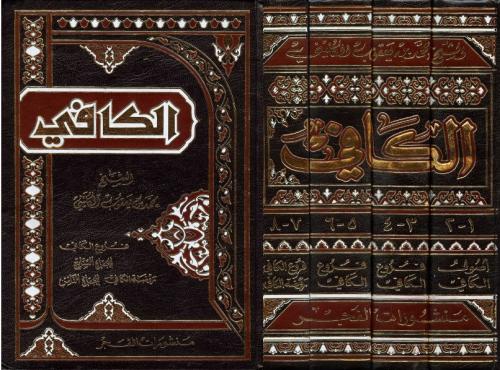Oleh: Bambang S
JANGGUTNYA sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Suara baritonnya menambah wibawa. Di Pesantren, ia dikenal sangat tangkas menjawab pertanyaan wartawan.
“Jadi apa arti nasionalisme menurut bapak?” Tanyanya suatu ketika kepada utusan pemerintah yang mendatangi pesantrennya untuk menyelenggarakan ‘Training Kebangsaan’.
“Apa Bapak meragukan ‘nasionalisme’ kami…nasionalisme santri-santri kami…?” protes Kiai yang mulai sepuh itu.
“Jika Bapak meragukan pembelaan kami terhadap negeri ini, silahkan diuji… ‘Bawa masuk’ tentara Amerika ke Indonesia, kami jamin santri kami akan berada di shaf depan untuk menghadapi mereka. Dan saya jamin, birokrat-birokrat yang sok nasionalis itu akan lari terbirit-birit meski setiap Senin hormat bendera,” ujarnya berargumen.
Setelah berdiskusi panjang, utusan itu akhirnya ‘setengah menyerah’. Di satu sisi, betapapun ia adalah delegasi yang harus pulang membawa hasil.
Akhir kata, disepakatilah sebuah kompromi. Kuliah kebangsaan tetap diadakan; diselipkan dalam sebuah sambutan acara seremonial pesantren yang kolosal. Bukan dalam bentuk training melainkan pidato dengan durasi sekitar satu jam. Dan untuk mewujudkannya, sang utusan memberikan dana atas nama ‘training kebangsaan’ tersebut.
Karena yang memberi kuliah adalah seorang menteri, kawan saya harus meminjam mobil Camry ke pemerintah kabupaten waktu itu. Tapi itu cerita beberapa tahun lalu. Dan kini, upaya mereduksi ‘arti cinta tanah air’ kembali mencuat.
Seorang wali kota yang terkenal santun dan berpihak kepada wong cilik, juga tiba-tiba mengumbar ancaman akan menutup sebuah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT). Semua atas sebab tak menjalankan upacara bendera. Beberapa pesantren di luar jawa, juga mulai mendapat tekanan serupa meski tak diwartakan di surat kabar.
‘Hormat bendera’ kini menjadi indikator penting loyalitas seseorang kepada bangsanya. Kita kembali dibawa ke alam Orde Baru (Orba).
Menarik, sebab ‘tebar ancaman’ ternyata hanya tertuju pada beberapa sekolah tertentu. Betapa banyak institusi pendidikan di negeri ini yang tak menggelar upacara bendera dan tak pernah disoal?
Hal ini mengingatkan kita Januari lalu di mana sebuah lembaga bernama ‘Setara Institute’ mengklaim telah melakukan riset atas lembaga- lembaga pendidikan Islam seperti Taman Kanak-kanak Islam terpadu (TKIT) dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dituding sebagai sarana pemupuk benih radikalisme Islam.
Menurut Setara Institute, TKIT dan SDIT telah mengajarkan benih radikalisme Islam karena sering melombakan nasyid jihad Palestina.
“Lagu-lagu jihad itu mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila, “ katanya. Kenapa tidak pakai lagu-lagu perjuangan Indonesia?” kata Ismail Hasani, sang peneliti yang tak jelas jasanya kepada bangsa ini. “Jadi kita harus waspada..!” katanya penuh curiga.
Statement yang muncul dalam paket acara “Deradikalisasi” di hotel Atlet 11 Januari 2011 ini tak memerlukan penjelasan panjang tentang siapa dan mau kemana arah diskusi itu.
Decision Maker
Padahal banyak pelajaran penting soal ujian pertahanan di negeri ini. Saat organisasi separatis Republik Maluku Selatan (RMS) beraksi di Maluku, oknum yang adalah orang penting di badan intelejen sowan (berkunjung) kepada sesepuh kelompok jihadis. Ini tentu bukan cerita koran, tapi cerita behind the scene yang bersumber dari pelaku. Sang intel meminta bantuan agar aktifis ‘jihadis’ membantu Negara untuk menghadapi kelompok separatis itu.
“Segala sesuatunya akan kita siapkan Pak…” bujuk sang intel.
Sesepuh itu menjawab, “Maaf, kami tidak biasa beramal atas dasar order. Kami hanya beramal lillahi ta’ala.”
Para aktifis jihadis ternyata sudah ada di lapangan karena Allah semata. Oknum intelejen yang dulu sering nongol di media itu menanggapi, “Baik, jika Bapak tidak bersedia kami akan meminta aktifis yang lain.”
Jadi bahwa mental pembelaan Negara itu dimiliki ‘kelompok santri’ bukanlah rahasia. Birokrat sangat mengerti akan hal itu.
Sejarah menunjukkan negeri ini dibangun oleh tetesan darah santri dan ulama. Sebuah komunitas perwira nan ikhlas. Kelompok yang tak berharap pamrih kecuali ridha ilahi. Sebuah komunitas yang menggariskan hidupnya dalam dua kalimat: ‘Hidup mulia atau Mati Syahid’.
Sayang banyak orang memanfaatkan ‘keikhlasan’ santri selama ini. Bukankah doktrin jihad terbukti paling unggul melawan Belanda?
Dalam khazanah kita, ada Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Pengeran Antasari, dan lain-lain. Term ‘jihad’ sebagai spirit perlawan mereka terekam apik dalam buku-buku ‘Babad Sejarah’ negeri ini. Saat kemudian Belanda hengkang, para pejuang sejati kembali ke surau-surau.
Sebaliknya, para tentara yang masa itu adalah output didikan Belanda dan Jepang justru tampil memimpin negeri bak pahlawan kesiangan. Santri, ternyata hanyalah sebuah komoditas.
Saat aktifis jihadis berjibaku menghadapi RMS, justru petugas keamanan bersembunyi di kolong-kolong seperti burung pipit sambil berkata, “Mas, tembak-menembaknya sebelah sana saja biar tidak kena saya”. Ini cerita mujahidin kepada saya.
Saat aktifis jihadis gugur tertembus peluru RMS, para birokrat kita asik berselingkuh dengan bangsa-bangsa penindas. Mereka sibuk menjual aset-aset Negara yang oleh Stiglitz (mantan Ketua Tim Ekonomi Bank Dunia) dijelaskan sebagai ‘penjajahan sistemik.’ Stiglitz akhirnya ‘tidak tahan’ dan menulis testimoninya dalam “Globalization And Its Discontents”. Ia ternyata masih punya nurani.
Bukankah bangsa ini sudah mulai melupakan perampokan atas nama ‘privatisasi’? Apa kabar Semen Gresik Gate, Krakatau Steel Gate, Telkom Gate, dan Indosat Gate?
Hampir bisa dipastikan (sebagaimana dituturkan Stiglitz) bahwa dalam setiap ‘privatisasi’ ada 10 % masuk ke kantong decision maker? Dan yang pasti, para mekelar hitam itu adalah cumlaude dalam melafalkan Pancasila dan khusyu’ dalam upacara bendera.
Penjajahan memang hanya berganti model. Kita semua sepakat bahwa sesungguhnya kita belum pernah merdeka. Bukankah pembukaan UUD Negara ini mencantumkah bahwa Indonesia baru sampai ‘di pintu gerbang kemerdekaan’? Yang harus kita ingat, bahwa penjajah tidak akan langgeng tanpa dukungan begundal lokal.
Belanda bisa bertahan menjajah selama 350 tahun, karena ulah demang dan bupati. Mereka para-para begundal yang hanya memikirkan perut dan kelompoknya.
Agaknya, kita belum beranjak jauh dari situasi itu. Tambang minyak dan emas kini berganti pemilik dengan ‘bangsa kulit putih’ sebagai tuan.
Aset potensial dijual murah ke bangsa-bangsa asing. Kita tak memiliki kemandirian politik dan ekonomi.
Kita menjadi buruh di negeri sendiri. Dan siapa lagi para bandit itu kalau bukan yang rajin berupacara bendera?; memparadekan ke-khusu’an nasionalisme tapi hatinya penuh dengan kemunafikan?
Ironis. Kini, saat Birokrasi gagal mendapat kepercayaan masyarakat di sekolah dasar; yang membuat sekolah-sekolah negeri tak mendapatkan siswa, komunitas santri kembali terpanggil membangun bangsanya. Sebagian sekolah yang semula hampir ambruk disulap menjadi sekolah-sekolah unggulan dan favorit. Umumnya kemudian menjadi TKIT atau SDIT dengan pola fullday school. Lokal yang dikelola, bahkan kini tak sanggup menampung luapan siswa.
Karena keikhlasannya, banyak dari mereka yang digaji di bawah UMR. Sungguh, sebuah penghayatan kebangsaan yang dalam istilah sufi bukan lagi berlevel syariat tapi sudah hakekat.
Pada saat yang sama, para birokrat itu punya keasyikan memainkan anggaran sambil berfikir ‘adakah tipe mobil baru yang belum aku beli?’.
Dan kini, para ‘pahlawan tanpa tanda jahasa’ sedang disoal
kecintaannya kepada bangsanya karena muridnya tak hafal Pancasila?
Ya, tapi para guru itu memang ‘berdosa’ karena mengajarkan nasyid Palestina. Tapi agaknya, itulah cara mereka menjauhkan anak didik dari mental para maling. Dan itulah ‘ilmu hekekat’. Para koruptor ternyata lebih berharga bagi negeri ini.
Merdekaaa!!!
Allahu Akbar …
Penulis adalah peminat masalah sosial keagamaan