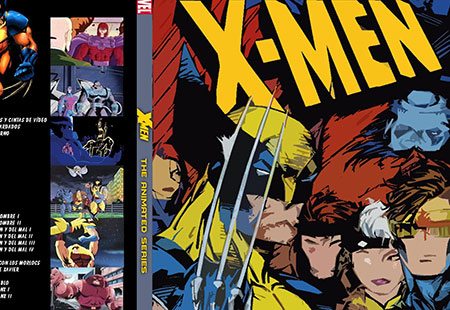Majelis Ulama Indonesia (MUI) lahir di era pemerintah Orde Baru, dimaksudkan sebagai lembaga fatwa serta mediator hubungan ulama dan pemerintah
Oleh: H. Ainul Yaqin
Hidayatullah.com | KETIKA ada salah seorang anggota komisi fatwa MUI diamankan oleh Densus 88 karena diduga terlibat jaringan teroris, tiba-tiba saja muncul aksi menuntut pembubaran MUI. Padahal keterlibatan yang bersangkutan adalah atas nama pribadi.
MUI juga telah merespon dengan menonaktifkan yang bersangkutan dari keanggotaan komisi fatwa sesuai dengan mekanisme organisasi. MUI menghormati proses proses hukum, dengan prinsip praduga tak bersalah akan menetapkan sikap berikutnya jika telah ada kepastian hukum.
Namun itulah uniknya MUI, yang berbeda dengan instansi atau lembaga lain pada umumnya. Jika di lembaga lain ada oknum bermasalah, tidak lantas lembaganya yang dibully. TNI misalnya ketika terbukti ada oknum anggotanya yang memasok senjata ke OPM yang akhirnya dipecat dan dipenjara, tidak ada yang menghujat TNI, apa lagi menuntut pembubarannya.
MUI memang unik sejak kelahirannya. Maka pada saat banyak yang menginginkan pembubarannya, tak sedikit yang membelanya. Tak kurang Menkopolhukan, Mahfud MD menyampaikan pembelan. Kata PaK Mahfudz MD, kekuatan hukum MUI sangat kokoh, sehingga wacana pembubaran MUI tidak realistis. Hal senada, sfat Khusus Presiden, Aminuddin Ma’ruf menyampaikan, keberadaan MUI sangat dibutuhkan. Organisasi MUI menjadi benteng dalam menjaga NKRI (mui.org/19/11).
MUI lahir di era pemerintah Orde Baru, dimaksudkan sebagai lembaga fatwa serta mediator hubungan ulama dan pemerintah. Lembaga sejenis MUI yang memerankan sebagai mediator hubungan ulama dan pemerintah, telah ada di masa orde lama.
Tahun 1956, para ulama di Priangan Timur membentuk BMAU (Badan Musyawarah Alim Ulama), dengan tujuan memulihkan stabilitas di Priangan Timur pasca ketegangan karena polarisasi pemberontakan DI/TII. Dengan tujuan yang sama, tanggal 12 Juli 1958 didirikan Majelis Ulama se Jawa Barat yang diketuai KH. M. Sudja’i.
Untuk tujuan penghubung ulama dengan pemerintah pula, pada kabinet Kerja II tahun 1962 selain ada kementerian agama, dibentuk Menteri Penghubung Alim Ulama yang dijabat oleh KH Fattah Yasin. Sedangkan Menteri Agamanya dijabat KH. Saifuddin Zuhri. Menteri Penghubung Alim Ulama tetap eksis pada Kabinet kerja III, dan IV, serta Kabinet Dwikora I, II, dan III.
Sukses peran majelis para ulama di masa Orde Lama, mendorong pemerintah Orde Baru untuk menginisiasi lembaga serupa. Maka Pusat Dakwah Islam, lembaga bentukan Menteri Agama menggagas penyelenggaraan konferensi ulama yang diselenggarakan tanggal 30 September – 4 Oktober 1970. KH. Ibrahim Hosen salah satu pembicara, menyampaikan makalah yang salah satu poinnya, pentingnya pembentukan Majelis Ulama yang bisa menaungi adanya praktik ijtihad kolektif, merujuk praktik dari Majma’ al-Buhûts al-Islâmiyyah di Mesir.
Buya Hamka yang juga menjadi penyaji tidak setuju dengan ide tersebut. Hamka khawatir adanya lembaga fatwa kolektif bisa diisi orang-orang sekular yang akan duduk di dalamnya. Sebagai ganti Hamka mengusulkan agar Presiden Soeharto mengangkat seorang ulama yang mumpuni sebagai mufti.
Senada dengan Hamka, kalangan tokoh Islam menanggapi apriori ide ini. Pembentukan Majelis Ulama oleh kalangan Islam dinilai sebagai upaya pengebirian para ulama dan dikhawatirkan akan menjadi alat untuk membatasi gerak umat Islam.
Sinyalemen seperti ini beralasan, karena perkembangan politik waktu itu memperlihatkan semakin menguatnya kekuatan kelompok sekular di dalam pemerintahan, di sisi lain peran kekuatan Islam di pemerintahan semakin mengecilnya. Kasus rancangan UU Perkawinan yang kontrovesial, menjadi contoh fenomena yang sempat menyulut keresahan kalangan Islam.
Konferensi tanggal 30 September – 4 Oktober 1970 berakhir tanpa menghasilkan apa-apa. Namun pada perkembangannya kemudian, Buya Hamka yang di awalnya menolak pembentukan majelis ulama, akhirnya menerima pembentukannya.
Bahkan Buya Hamka bersedia menjadi ketua umumnya saat MUI dideklarasikan pada Munas Alim Ulama 21 – 27 Juli 1975. Hal ini karena ada lobi dari Kementerian Agama. Hamka bersedia, karena kaum muslimin harus bekerja sama dengan pemerintah menghadapi komunis. Beliau diyakinkan, bahwa pendirian MUI akan meningkatkan hubungan umat Islam dengan pemerintah.
Untuk memberikan penguatan pada independensi MUI, pada perjalanannya dirumuskan kriteria orientasi perkhidmatan MUI, yang menjadi bagian dari pedoman organisasinya. Salah satu dari orientasi itu adalah hurriyah, yakni bahwa MUI merupakan wadah perkhidmatan independent yang bebas dan merdeka serta tidak tegantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
Sehingga kendatipun kelahiran MUI melibatkan inisiasi dari pemerintah Orde Baru, tidak lantas mudah didekte begitu saja. Terbukti dalam kasus fatwa perayaan natal bersama, MUI tidak mau mengikuti kemauan pemerintah untuk mencabutnya waktu itu. Ini salah satu dari keunikannya.
Secara kelembagaan, MUI adalah organisasi kemasyarakatan. Setelah UU No. UU No. 17 th 2013 tentang Ormas disahkan, badan hukum MUI pun dikeluarkan dengan akte notaris No 034, tertanggal 15 April 2014 dan terdaftar di Kemenkum dan HAM No. AHU-00085.60.10.2014.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan pasal 11 ayat (2) UU No. 17 th 2013, ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan basis keanggotaan. Kemudian dalam pasal 11 ayat (3) dinyatakan, ormas yang tidak berbasis anggota dan hanya pengurus saja, badan hukumnya adalah yayasan. Sedangkan MUI tidaklah demikian. MUI berbadan hukum perkumpulan, namun menjadi anomali karena tidak punya stelses keanggotaan kecuali hanya pengurus saja.
Hal ini juga menjadi keunikan MUI dari sisi kelembagaannya. Keunikan lain dari MUI adalah keberadaannya yang merupakan ormas dengan badan hukum perkumpulan, tetapi secara eksplisit disebutkan dalam banyak peraturan perundang-undangan.
Bisa disebutkan di sini tidak kurang dari enam undang-undang antara lain: UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah Negara, UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, UU No.33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain itu nama MUI juga tersebut dalam Peraturan Gubernur Jatim No. 55 tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jatim. Kemudian tercantum pula dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/ 32 /PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syari’ah, Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syari’ah, Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syari’ah, dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah.
UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas misalnya, pada pasal 109 ayat (2) menyebutkan, bahwa Dewan Pengawas Syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dalam UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 14 ayat (3) dinyatakan bahwa anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang berasal dari unsur masyarakat salah satunya adalah MUI.
Lalu ada pula yang mempertanyakan fatwa MUI. Secara umum, fatwa adalah penjelasan atau jawaban dari ulama yang berhubungan dengan masalah keagamaan yang bersifat tidak mengikat.
Hal ini berbeda dengan hukum positif yang mengikat terhadap warga negara, ataupun keputusan hakim yang mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara. Namun demikian, beberapa fatwa MUI menjadi unik karena diadopsi oleh perudang-udangan sehingga menjadi mengikat.
Beberapa contoh, antara lain dalam UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah Negara, pada penjelasan pasal 25 dinyatakan, bahwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syari’ah adalah MUI. Kemudian UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, pada pasal 26 ayat (2) juga dinyatakan, bahwa prinsip syari’ah dalam lembaga keuangan syari’ah adalah mengikuti fatwa MUI. Berikutnya, dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK N0. Kep-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, dalam ketentuan umum dinyatakan, prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Dalam kaitannya dengan produk halal pun fatwa MUI yang menjadi rujukan. Ketentuan ini antara lain diatur dalam UU No. 33 tahun 2014. Pada pasal 1 ketentuan umum angka 10 dinyatakan, bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 pasal 1 ketentuan no. 6.
Inilah keunikan-keunikan MUI. Jika sekarang ada yang bersuara meminta MUI di bubarkan, itu juga keunikannya. Demikian pula jika ada yang bertanya, “MUI Itu makhluk apa?”, ini pun bagian dari keunikannya itu. Tetapi yang jelas, masih jauh lebih banyak umat yang berharap pada eksistensi MUI untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya secara istiqamah sampai di masa-masa mendatang, sekalipun tidak bersuara.*
Ketua MUI Prov. Jatim