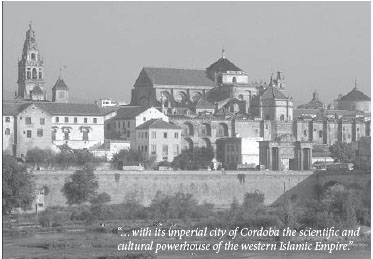“Umat Islam – kadang juga Islamnya – dalam kamus pemikiran Barat dan kerangka pemikiran sekular acapkali dituduh sebagai fanatik, tidak mau menerima “orang lain”, bahkan mengkafirkan orang lain. Tuduhan-tuduhan ini sudah menyebar dan sedang menyebar di pena para penulis sekular yang ekstrem di negara-negara Islam…” (Dr. Muhammad ‘Imārah)
Oleh: Qosim Nursheha Dzulhadi
APA yang disebutkan oleh Dr. Muhammad ‘Imārah, pemikir Islam asal Mesir, di atas adalah benar belaka. Termasuk di Indonesia. Banyak kaum sekular di Indonesia menuduh umat Islam dengan tuduhan tak berdasar: fanatik, intoleran, mudah mengkafirkan, dan lain sebagainya.Maka, melalui buku-buku mereka mencoba untuk tampil bak “mujtahid”: melahirkan hukum baru, meskipun salah kaprah. Misalnya, penulis buku Argumen Pluralisme Agama yang diantara kesimpulannya adalah: agama yang satu tak membatalkan agama yang lain, karena setiap agama lahir dalam konteks historis dan tantangannya sendiri. Selain itu, dia juga menyimpulkan bahwa umat non-Muslim juga di akhirat selamat. (Lihat, Abd. Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an (Depokt: KataKita, 2009), 240, 249).
Selain penulis Argumen Pluralisme Agama, ada juga penulis Polemik Kitab Suci. Diantara pandangannya adalah: istilah “polemik” di sini berarti teks-teks kitab suci itu menggambarkan agama lain secara negatif, yang mencakup di dalamnya kritik terhadap komunitas agama lain, secara eksplisit maupun implisit. (Mun’im Sirry, Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik Al-Qur’an terhadap Agama Lain (Jakarta: Gramedia, 2013), xix).
Nah, agaknya buku-buku semacam ini sangat mungkin menjadi “mukaddimah” bagi diskusi-diskusi lanjutan tentang kritik terhadap ajaran Islam, yang menurut mereka dipandang ekslusif, ekstrem, dan menyalahkan ajaran agama lain. Termasuk diskusi tentang upaya penggantian istilah ‘kāfir’ dengan ‘non-muslim’, dan kata ‘ahl ad-dzimmah’ dengan ‘warga negara’ (muwāthinūn). Bayangkan, hal yang sudah mapan dalam ajaran Islam, ingin diganti dengan istilah lain hanya karena dianggap, mungkin, sebagai ‘kekerasan teologis’.
Melihat hal di atas, sudah sepatutnya tokoh umat, para ulama, dan individu Muslim merespon ini dengan serius. Meskipun kita tahu bahwa inilah konsekuensi menjadi pemeluk agama yang benar dan diakui oleh Allah di sisi-Nya (Qs. 3: 19, 85). Sehingga beramai-ramai musuh Islam “menyerangnya”: ingin mengontrolknya, ingin memperburuk citranya, bahkan ingin menghabisinya. Dan itu mereka lakukan “siang-malam”, setiap ada kesempatan (Qs. 2: 217). Karena mereka ‘tidak akan pernah ridha’, kecuali umat Islam masuk dan mengantu millah (ide, pemikiran, konsep, ideologi, bahkan ajaran agama) mereka (Qs. 2: 120). Dan musuh Islam ini “berkolaborasi” dengan kaum munāfiqūn yang memang selama ini menampakkan diri sebagai Muslim, padahal menyembunyikan kebencian mendalam terhadap Islam.
Hal dia atas juga patut menjadi pertanyaan: ada agenda apa di balik semua ini? Padahal masalah ‘penistaan’ terhadap Qs. 5: 51 masih hangat dalam ingatan umat ini. Kasus masalah ‘azan’ dan ‘tusuk konde’ belum lagi sirna. Belum lagi masalah LGBT yang kian hari kian mengerikan. Ditambah lagi dengan RUU-PKS yang sangat mengancam ‘ketahanan keluarga Muslim’ – entah kalau agama lain merasa terancam dengan rancangan ini. Datang pula masalah kriminalisasi terhadap ulama-ulama Islam. Itu semua belum usai, tiba-tiba emosi umat Islam kembali “diaduk-aduk” dan “diacak-acak” dengan usulan penggantian istilah ‘kāfir’ dengan non-muslim. Allahu Akbar!
Apakah dengan mengganti istilah ‘kāfir’ dengan ‘non-muslim’ dibutuhkan oleh umat Islam di Indonesia? Apakah selama ini kaum Nasrani tidak dianggap sebagai ‘warga negara’? Dan, apakah dengan mengganti istilah ‘kāfir’ otomatis kaum Nasrani, misalnya, jadi beriman? Tentu tidak, kan?
Yahudi dan Nasrani Tetap ‘Kāfir’!
Nah, hal-hal di atas kemudian membawa ingatan penulis kepada beberapa orang, diantaranya: Fahmī Huwaidī, penulis liberal Mesir, yang menulis buku ‘Muwāthinūn Lā Dzimmiyyūn’ (Warga Negara, Bukan Kāfir Dzimmī) (Kairo: Dār as-Syurūq, cet. II, 1990). Tujuan Fahmī Huwaidī sama dengan para pengusul penggantian terminologi Al-Qur’an, ‘kāfir’, dengan istilah yang campur-aduk dan amburadul: non-muslim (‘bukan muslim, tidak muslim’). Padahal, selama ini istilah ‘kāfir’ tidak pernah menimbulkan riak yang menggangu jalannya aliran toleransi antar umat beragama.
Karena istilah ‘kufr’ adalah lawan dari ‘iman’. Maka, misalnya, orang yang mengimani Trinitas pasti ‘kāfir’ kepada Tawhīd. Sebaliknya, orang yang mengimani Tawhīd pasti kafir dan menolak Trinitas. Orang yang mengimani bahwa ‘Uzair’ (Ezra) ada hamba Allah pasti ‘kāfir’ dan menolak keyakinan bahwa Ezra adalah anak Tuhan. Padahal yang benar adalah dia hamba Allah. Kemudian, orang yang mengimani bahwa ‘Isa adalah hamba Allah dan rasul-Nya pasti mengingkari, menolak, dan ‘kāfir’ kepada keyakinan bahwa ‘Isa adalah anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Padahal yang benar adalah dia hamba Allah dan rasul-Nya. Dan, orang yang mengingkari bahwa Al-Qur’an itu wahyu ilahi dan Muhammad Saw. adalah seorang nabi dan rasul pasti dia ‘kāfir’ terhadap Islam sebagai agama samawi.(Dr. Muhammad ‘Imārah,al-Islām wa al-Ākhar: Man Ya‘tarifu Biman? Wa Man Yunkiru Man?(Kairo: Maktabah as-Syurūq ad-Dawliyyah), 5.
Ingatlah, ketika para pendeta Gereja St. Catherine di Bukti Tursina – mereka adalah dari Roma Ortodoks – pada tahun 2000 menolak Paus Vatikan dan pendeta agung Katolik (Paulus II) untuk berdoa di dalam Gereja itu. Karena dalam pandangan mereka, Paulus II bukan “orang beriman”. Ini berdasarkan standar dan ajaran iman mereka.
Akhirnya, pada September 2000 keluarlah Surat Keputusan dari Vatikan yang menegaskan, “Gereja-gereja selain Katolik “bukanlah gereja dalam artinya yang benar..dan keselamatan di hari akhirat nanti hanya untuk gereja Katolik saja.” (Muhammad as-Sammāk, “al-Vātīkān wa al-Īmān al-Mukhtalif” (Harian Al-Ahram, 20/9/2000. Dikutip dari Dr. Muhammad ‘Imārah, al-Islām wa al-Ākhar, 7).
Kemudian, muncul dalam benak penulis sosok Syekh Yusuf al-Qaradhawī, yang dikenal sebagai sosok alim, pemikir hebat, dan tokoh Islam dunia yang banyak melakukan “ijtihad” dalam ranah interaksi sosial antara umat Islam dan orang-orang kāfir. Diantaranya adalah upaya menyebarkan penggunaan istilah ghair al-muslimīn (non-muslim) sebagai ganti dari istilah ‘kāfir’ dan muwāthinūn (warga negara) pengganti dari istilah ahl ad-dzimmah (kāfirDzimmī). Tapi, Syekh Yusuf al-Qaradhawī memiliki alasan yang sangat mungkin berterima di tengah-tengah umat Islam.
Dalam karyanya yang bertajuk Khithābunā al-Islāmī fī ‘Ashr al-‘Awlamah (Wacana Islam di Era Globalisasi) beliau memang mengusulkan agar kata kuffār diganti dengan ghair al-muslimīin. Ini merupakan bagian dari dakwah bi’l-hikmah, kata beliau. Apalagi di era globalisasi seperti. Jadi, jangan sampai kita menyebut mereka ‘kāfir’, meskipun kita meyakini kekufuran mereka. Apalagi yang berbeda dengan kita adalah kaum Ahl Kitab.
Kemudian Syekh al-Qaradhawī menyebutkan dua sebab mengapa harus menyebut mereka non-muslim, yaitu:
Pertama,karena kata kuffār memiliki banyak makna. Diantara maknanya adalah: mengingkari Allah, rasul-rasul-Nya, dan akhirat. Ini adalah yang dilakukan oleh kaum materialis yang tidak mengimani hal-hal yang metafisik: tidak mengimani Tuhan, tidak meyakini kenabian (nubuwwah), dan tak percaya akhirat. Sedangkan kata kufur ketika kita membicarakan Ahli Kitab maksudnya adalah: mereka kafir kepada risalah Muhammad dan agamanya. Dan ini benar. Sebagaimana mereka juga meyakini bahwa kita ini ‘kāfir’ kepada agama mereka, yang mereka peluk itu. Dan ini pun benar.
Kedua,Al-Qur’an mengajarkan kita agar tidak menyebut manusia – meskipun mereka kāfir – dengan nama ‘kāfir’. Sebutan untuk manusia – yang tidak beriman, bukan mukmin – dalam Al-Qur’an, disebut dengan yā ayyuhan-nās, yā ibna ādam, ya ‘ibādī, atauahl al-kitāb.
Dan Al-Qur’an menyebut ‘kāfir’ hanya dalam dua ayat: (1) sebutan untuk mereka di hari Kiamat (Qs. at-Tahrīm: 7) dan (2) al-Kāfirūn: 1-6. Dalam surah al-Kāfirūn ini Allah menyeru kaum musyrik-pagan, yang “menego” Rasul yang mulia agar beliau menyembah tuhan-tuhan mereka selama setahun. Kemudian, bergantian, mereka menyembah Tuhan sang nabi selama setahun pula. Maka, surah ini ingin memotong usaha mereka dengan gaya bahasa yang tegas, dengan sebutan yang keras sehingga tak ada celah lagi. Maka Allah memerintahkan Rasulullah dengan menggunakan kata yang kuat ini (kāfirūn). Bahkan, di dalamnya disertai dengan pengulangan (tikrār) dan penekanan (tawkīd). Meski demikian, surah ini ditutup dengan “membuka” pintu toleransi dengan orang lain, yaitu: lakum dīnukum waliyadīn.
Maka, Syekh Yusuf al-Qaradhawī lebih mengutamakan istilah ghair al-muslimīn daripadakāfir, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam karyanya yang lain, ‘Ghair al-Muslimīn fī al-Mujtama‘al-Islāmī’ (Non-Muslim di Tengah-tengah Masyarakat Islam). (Lihat, Syekh Yusuf al-Qaradhawī,Khithābunā al-Islāmī fī ‘Ashr al-‘Awlamah (Kairo: Dār as-Syurūq, cet. I, 1424 H/2004 M), 44-45).
Namun, pandangan Syekh al-Qaradhawī sejatinya perlu digarisbawahi. Yaitu, beliau tetap menegaskan bahwa kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) adalah ‘kāfir’. Yang beliau usulkan adalah hanya khithāb (ujaran, seruan, sebutan). Ini tepat dalam masalah muamalah (interaksi) sosial dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, di ruang publik sebutan ‘kāfir’ untuk kaum di luar Islam memang tidak pernah terjadi. Karena ini masalah privasi.
Namun, dalam masalah teologis mereka memang tetap disebut sebagai orang ‘kāfir’, karena tak mengimani kerasulan Rasulullah Saw. dan menolak kebenaran agama Islam. sebagaimana kaum Nasrani, misalnya, tetapi menyebut orang di luar agama mereka (terutama umat Islam) sebagai “domba tersesat”. Ini adalah hak mereka. Dan ini benar dalam pandangan agama mereka. Dan tentang kekufuran Yahudi dan Nasrani, dengan tegas Syekh al-Qaradhawī menyatakan bahwa seluruh aliran dan madzhab dalam Islam sepakat tentang ‘kekufuran’ kedua penganut agama ini. Alasan lugasnya: karena manusia hanya terbagi kepada dua golongan: Muslim dan Kāfir. Siapa saja yang bukan Muslim berarti ‘kāfir’. Namun, orang-oraang ‘kāfir’ bertingkat-tingkat: ada Ahli Kitab, ada musyrik, ada kaum jāhidūn-dahriyyūn(penolak kebenaran, kaum naturalis), ada kāfir damai (musālimūn), ada juga kāfir yang memerangi umat Islam (muhāribūn). (Lihat, Syekh Yusuf al-Qaradhawī, Mawqif al-Islām al-‘Aqadī min Kufr al-Yahūd wa an-Nashārā (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. I, 1420 H/1999 M), 6, 7).
Dan kami pun, umat Islam Indonesia, mengakui dan meyakini bahwa siapa saja yang tak mengimani kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad Saw. adalah ‘kāfir’. Ini adalah aqidah kami, keyakinan kami. Karena beriman kepada nabi-nabi Allah, termasuk Nabi Muhammad Saw. merupakan ‘Rukun Iman’. Maka, Allah dengan keras menyatakan bahwa orang-orang yang kāfir kepada Allah dan para rasul-Nya dan ingin memecah-mecah (membeda-bedakan) antara Allah dan rasul-rasul-Nya dan berkata bahwa ‘kami mengimani sebagian saja dan kufur kepada sebagian yang lain’ mereka itulah orang-orang ‘kāfir’ yang sejati (Qs. 4: 150-151).
Sebagai pentutup, mari kita renungkan dan hayati kata-kata Buya Hamka ketika menjelaskan surah al-Kāfirūn berikut ini,
“Surah ini memberikan pedoman yang tegas bagi kita, pengikut Nabi Muhammad, bahwa aqidah tidaklah dapat diperdamaikan. Tauhid dan syirik tak dapat dipertemukan. Kalau yang hak hendak dipersatukan dengan yang batil, maka yang batil akan mendapat untung. Oleh sebab itu, maka aqidah Tauhid tidaklah mengenal apa yang dinamai Cyncritisme, yang berarti menyesuai-nyesuaikan. Misalnya, diantara animisme dengan Tauhid, penyembah berhala dengan shalat, menyembelih binatang guna hantu atau jin dengan membaca Bismillah.” (Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Gema Insani Press, 1435 H/2015 M): 9/680).
Maka, wibawa ulama yang waratsatu’l-anbiyā’ saat ini amat perlu dihadirkan. Yaitu para ulama yang konsisten menjaga kemurnian ajaran Al-Qur’an, ajaran Nabi Muhammad, dan kesempatakan (ijmā‘) para ulama. Ulama-ulama seperti Syekh Muhammad al-Ghazali, Buya Hamka, dan yang lainnya. Ulama-ulama seperti mereka inilah yang akan menjadi “benteng” aqidah umat. Karena masalah aqidah adalah masalah keyakinan yang pangkalnya di dunia dan ujungnya di akhirat. Maka, jika kita main-main dan anggap remeh urusan aqidah yang untung adalah musuh Islam. Fa‘tabirū yā uli’l-abshār.[]
Aktivis Muslim dan penulis buku ‘Membongkar Kedok Liberalisme di Indonesia’