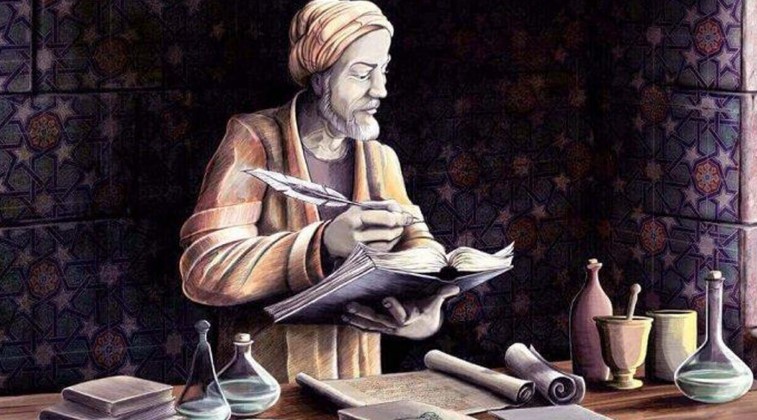Teori receptie yang digagas orientalis Snouck Hurgronje memberikan kebebasan umat Islam menjalankan semua ibadah, tapi kegiatan politik dibatasi
Oleh : Syahrir Roudhi Hadi
Hidayatullah.com | DALAM tata hukum nasional, hukum agama dapat menjadi unsur utama dalam pertimbangan pembuatan undang-undang. Berdasarkan kepada sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga Pasal 29 UUD 1945 bahwa penerapan hukum positif berdasarkan dengan nilai atau ajaran agama dijamin hak-haknya oleh negara.
Sila Pertama secara langsung menjelaskan kondisi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Indonesia senantiasa membangun perkembangan hukum nasional, di dalam perjalanannya sebagaimana pernyataan Mahfud MD bahwa perkembangan hukum senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan politik, dampaknya karakter dan ciri khas produk hukum selalu merujuk kepada kekuatan atau konfigurasi politik yang menghasilkannya (Harun, 2009).
Memasuki periode reformasi arah dan kebijakan hukum dan politik hukum nasional harus sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999, yaitu “Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan selaras dengan mengakui sekaligus menghormati hukum agama dan juga hukum adat serta melakukan pembaharuan terhadap undang-undang warisan Belanda dan hukum nasional yang terkesan mengandung diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan cita-cita reformasi melalui program legislasi.” (Panji Adam, 2020)
Kesimpulan dari GBHN Tahun 1999 sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa pembangunan hukum nasional berlandaskan kepada hukum adat, hukum agama dan hukum barat yang terbebas dari hal-hal diskriminatif dan selaras dengan tuntutan reformasi. Dalam hal ini hukum Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum nasional, bahkan memiliki peluang menjadi hukum nasional itu sendiri. Keberadaan hukum Islam di Indonesia sudah ada semenjak era kerajaan-kerajaan Islam di nusantara hingga saat ini.
Perkembangan Hukum Islam di Indonesia memiliki dinamika perjalanan yang panjang dan berliku. Salah satu metode dalam memahami dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah dengan mengkaji dan memahami terkait teori-teori yang disampaikan oleh orientalis dan pakar hukum Indonesia berdasarkan pada fakta yang terjadi. Tujuannya adalah agar memahami dinamika perkembangan dan teori implementasi hukum Islam di Indonesia.
Panji Adam dalam bukunya “Hukum Islam : Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia” mengungkapkan ada tujuh teori terkait implementasi hukum Islam di Indonesia, adapun teorinya yaitu :
Pertama, Teori Kredo
Teori Kredo atau disebut juga dengan teori syahadat adalah teori yang mengharuskan bagi setiap pemeluk agama Islam yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, menjalankan hukum Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari, sekaligus sebagai konsekuensi logis dari ikrar dua kalimat syahadat. Menurut Juhaya S. Praja teori kredo sejalan dengan teori teritorialitas dari imam Abu Hanifah dan teori non-teritorialitas dari Imam Syafi’i.
Teori teritorialitas imam Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang Muslim terikat dengan hukum Islam selama dia hidup dalam wilayah diberlakukannya hukum Islam. Sedangkan, teori non-teritorialitas Imam Syafi’i menjelaskan bahwa setiap Muslim senantiasa terikat dengan hukum Islam baik ketika berada dalam negara yang diberlakukannya hukum Islam maupun tidak.
Kedua, Teori Receptie in Complexu
Teori Receptie in Complexu merupakan kelanjutan dari teori kredo. Di mana seorang Lodewijk Willem Christian Van Den Berg mengamati adanya pembauran antara hukum Islam dan hukum adat, seperti di Aceh, Jawa, Sulawesi Selatan, Minangkabau, Riau dan Padang. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ungkapan adat yang berbunyi “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah” dan “Syara’ mengata, adat memakai” artinya adalah “kebiasaan berdasarkan syariat, dan syariat berdasarkan Al-Qur’an” dan “Apapun yang dikatakan syariat, maka adat memakainya”.
Menurut teori ini hukum agama bisa berlaku bagi setiap pemeluknya masing-masing, karena hukum adat mengikuti agama yang dianut.
Pemerintah kolonial kemudian mengadopsi teori receptie in complexu yang dimuat dalam pasal 77 Regeeringsreglement tahun 1855. Pada pasal 75 ayat (3) berbunyi “oleh hakim Indonesia hendaknya diberlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia. Pada masa berlakunya teori ini muncul kebijakan terkait pembentukan Pengadilan Agama (Priesterraaad) dan Pengadilan Negeri (Landraad) yang tertulis dalam staatsblad. 1882 No.. 152. Sebelum diputuskannya pembentukan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan orang Islam para hakim menggunakan buku yang berisi himpunan hukum Islam sebagai pegangan, seperti Mogharrer Code pada tahun 1774, Compendium van Clootwijk pada tahun 1795 dan Compendium Freijer pada tahun 1761”.
Ketiga, Teori Receptie
Dalam perjalanannya muncul sebuah teori receptie yang bertolak belakang dengan teori receptie in complexu di mana hukum Islam menjadi sah apabila telah di resepsi ke dalam hukum adat. Teori ini digagas oleh orientalis yang masyhur dalam menyelewengkan sejarah nasional, terkhusus adalah sejarah yang berkaitan dengan perjuangan umat Islam, yaitu Snouck Hurgronje dan Cornelis Van Vollenhoven.
Teori ini muncul akibat kekhawatiran Hurgronje apabila umat Islam di Indonesia semakin kuat memeluk ajaran Islam sehingga menjadi susah untuk dipengaruhi. Teori ini memberikan kebebasan umat Islam dalam menjalankan kegiatan ibadah, dalam kegiatan kemasyarakatan atau aspek muamalah dalam Islam pemerintah Hindia Belanda juga harus menghormati keberadaannya, dalam aspek politik umat Islam tidak diberikan ruang sedikit pun terlebih apabila dicurigai akan berpotensi menyebarkan seruan pan-Islamisme.
Dengan usaha yang sistematis, Pemerintah Hindia Belanda mengaminkan teori receptie yang digagas oleh Snouck Hurgronje dan Cornelis Van Vollanhoven ditandai dengan munculnya pasal 134 ayat (2) yang esensinya adalah Hukum Islam akan memiliki dampak dan manfaat bagi kepentingan pemeluknya, apabila hukum Islam telah diresepsi kedalam hukum adat. (BERSAMBUNG)