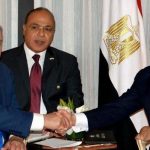Hidayatullah.com—Meski tema kajian tidak sama dengan yang direncanakan sebelumnya, namun sama sekali tidak mengurangi kualitas pembahasan di forum INSAF (INSISTS Saturday Forum) yang deselenggarakan oleh INSISTS, Jakarta (16/02/2019 – 10.00-12.00). Dr. Ahmad Zainun Najah –selaku pembicara—mengangkat tajuk: “Fiqih dan Perubahan Sosial Politik”.
Dalam pendahuluannya, pakar fikih yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Madinah itu menerangkang alasan dirubahnya tema kajian –meski tidak sepenuhnya menyimpang dari tema fikih—agar pembahasannya itu terkait langsung dengan realitas. Sebab, pembahasan fikih ikhtilaf (perbedaan pendapat) sudah biasa. Alangkah baiknya jika, kajian fikih diarahkan ke tema-tema yang aktual.
Ada beberapa poin penting yang dipaparkan oleh dai yang juga merupakan tokoh Majelis Intelektual dan Ulama Muda (MIUMI) itu. Pertama, pengertian fikih. Kedua, fikih dan etika sosial. Ketiga, fikih dan perkembangan zaman. Keempat, fikih dan kearifan lokal. Kelima, fikih dan hubungan sesama. Keenam, fikih lahir dan batin. Ketujuh, fikih dan politik. Kedelapan, penutup.
Ketika menjelaskan makna fikih, beliau memberi penekanan bahwa antara ilmu dan fikih maknanya berbeda. Bila ilmu adalah pemahaman mengenai sesuatu secara umum; sementara fikih adalah pemahaman secara mendalam.
Bagaikan air yang tenang menunjukkan kedalamannya, maka seorang fakih (ulama yang menguasai fikih) semestinya menunjukkan ketengan dan kesejukan dalam setiap fatwa atau hukum yang merupakan hasil ijtihadnya. Atau dengan istilah lain, bagai padi yang berisi. Semakin berisi semakin merunduk yang menunjukkan ketawadhuan.
“Fikih itu, lebih di dahulukan sebelum menyampaikannya. Terutama juga terkait pemimpi. Sebelum menjadi pemimpin semestinya harus memilik pemahaman yang dalam mengenai agama,” kata Zain.
Di sela-sela penjelasannya, ia berharap ke depan akan lahir pemimpin-pemimpin dari INSISTS yang menjadi pemimpin berdasarkan basis keilmuan dan kefikihan yang kuat sehingga kepemimpinanannya bisa diandalkan.
Tidak kalah menarik dari itu, pria yang menyelesaikan S-2 dan S-3 di Al-Azhar Kairo ini berujar bahwa fikih itu berdiri dengan adab dan etika. Menyitir perkataan Imam Syafi’i, seorang tidak cukup hanyak menjadi fakih namun sekaligus sufi (yang bermakna memiliki kepedulian dalam hal tazkiyatun-nafs [penyucian jiwa] dan etika).
Sebagai contoh, aurat laki-laki sebenarnya dari pusar hingga paha. Yang menjadi permasalahan, apakah sah jika orang shalat sebatas aurat itu saja; misalnya sembahyang dengan celana kolor tanpa baju? Secara fikih mungkin sah, namun secara adab dan etika sangat kurang etis.
Setelah menyampaikan perkataan Imam Syafii tadi, Zain menggaris bawahi poin menarik bahwa fikih dan sufi (dalam pengertian positif) harus beriring. Sebab, jika pendekatan hanya fikih saja maka fikih akan terasa kering.
Fikih juga harus memperhatikan perkembangan zaman. Dalam terminologi fikih ada istilah “Fiqhu al-Waqi’” (fikih realitas). Meskipun ada sebagian yang mempermasalahkannya, namun umat Islam tidak akan pernah bisa menghindar dari realitas. Kata beliau, kita tidak bisa lari dari problem aktual yang sedang dihadapi, tapi perlu dipecahkan solusinya dengan fikih realitas tadi.
Pembahasan seperti hukum mengonsumsi benda najis yang sudah berwarna, inseminasi (bayi tabung), operasi selaput darah, Go Pay, Dropship dan lain sebagainya adalah permasalahan aktual yang perlu dipecahkan dengan fikih realitas.
Selain itu yang tak kalah penting juga dalam kajian ini adalah hubungan fikih dengan kearifan lokal (adat). Ada sebuah kaidah fiqhiyah yang dikemukan “al-‘Aadaah al-Muhakkamah” kearifan lokal bisa menjadi hukum (ketika tidak ada dalam Al-Qur`an, Sunnah dan bahasa) sebagaimana yang beliau kutib dari kitab “al-Asybah wan al-Nadhair” karya Imam Suyuthi.
Kata Imam Suyuthi, “Setiap sesuatu yang tidak ada standar atau ukurannya dalam al-Quran , as-Sunnah dan bahasa, maka dikembalikan kepada kearifal lokal (tradisi).” Jadi, sebenarnya antara kearifan lokal dan fikih bisa berjalin kelindan, tak mesti dipertentangkan. Para tokoh Islam pendiri bangsa ini, dengan undang-undang dasar dan pancasila telah mempraktikkannya dengan sangat baik.
Pada kesempatan yang begitu penuh keakraban itu, Zain juga menyampaikan pentingnya “Fiqih Muwazanah” (fikih keseimbangan). Terinspirasi dari hadits, “Jika air volumenya sebanyak dua qulla, maka tidak najis.”
Hadits ini bisa dipakai untuk mendamaikan antara fikih dan hubungan sesama muslim. Kata beliau tidak ada orang sepenuhnya sempurna atau salah. Maka, dalam menilai sesuatu harus berimbang dan adil.
“Fikih,” kata Ustadz Zain, “juga harus lahir batin.” Maksudnya, perlu dikombinasikan antara tataran hukum yang sifatnya lahiriah dan ranah akhlak yang sifatnya batiniah. Sebagai contoh, secara fikih orang yang sudah mengerjakan shalat sesuai syarat rukun sudah sah, namun bagaimana jika dilakukan dengan tidak ikhlas? Contoh lain adalah haji yang dilakukan dengan dana korupsi. Karena itu, fikih tidak bisa dipisahkan dengan akhlak dan adab.
Islam dan Politik
Pada pembahasan terakhir beliau membahas seputar fikih dan politik. Dari al-Qur`an dan hadits serta karya-karya ulama Islam terdahulu, menunjukkan bahwa fiikih Islam juga membincang ranah politik. Kisah-kisah seperti Musa dan Fir’aun, Yusuf di Mesir, Sulaiman dan Ratu Bilqis misalnya adalah hal-hal inspiratif terkait politik. Makanya, umat Islam tidak boleh mengabaikan masalah penting ini terlebih di tahun-tahun politik seperti saat ini.
Seusai pemaparan ada beberapa pertanyaan yang diajukan peserta misalnya sistem negara Islam yang paling ideal, khawarij prosuderal, hukum memasuki tarekat, terjun di dunia politik yang tak lepas dari hal syubhat dan lain sebagainya. Semuanya dijawab dengan mantab oleh beliau yang menunjukkan kepakarannya dalam bidang fikih.
Dalam penutup ia memberikan pesan berharga, “Berpolitik harus berilmu!” Artinya, orang yang terjun di dunia politik harus berilmu. Terkait pemimpin yang layak bisa dipilih misalnya, saran dari MUI bisa dipertimbangkan, yaitu pemimpin yang memenuhi empat kriteria Nabi atau minimal mendekati: jujur, terpercaya, cerdas dan pandai menyampaikan gagasannya ke publik. Maka berilmulah terlebih dahulu sebelum memimpin.*/MB Setiawan (Jakarta)