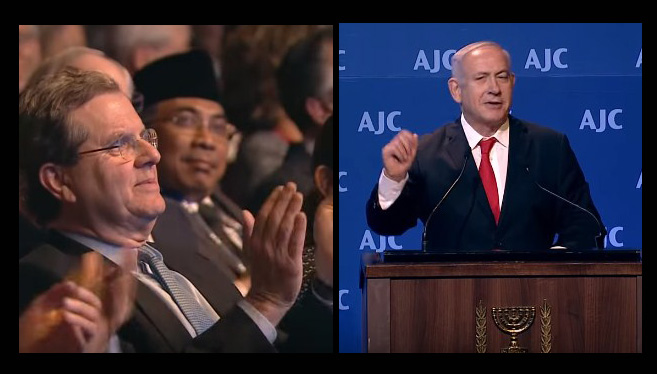Oleh: Reza Ageung
HIJABISASI, itulah julukan yang diteriakkan oleh kaum feminis untuk menggugat maraknya Peraturan Daerah (Perda) syariah belakangan ini.Memang, sejak diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, ramai pemerintahan daerah menyusun perda yang sesuai dengan kehendak daerahnya. Di antara Perda-perda tersebut adalah perda yang dinilai berbasis syariah, walaupun sebetulnya tidak pernah tertulis bahwa perda tersebut adalah syariat Islam, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota bahkan desa.
Kasus terbaru, protes feminis yang terakhir adalah terhadap rencana diberlakukannya perda larangan duduk mengangkang untuk perempuan yang dibonceng di sepeda motor di kota Lokhseumawe, Aceh. Sebagaimana ramai diwartakan media, walaupun Perda ini nantinya hanya berlaku di kota itu saja, tanggapan miring dari kaum feminis telah menggaung secara nasional.
Protes ini semakin melengkapi penentangan mereka terhadap Perda-perda syariah lainnya. Komnas Perempuan pada tahun 2010 menyusun laporan bertajuk “Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia.”
Dalam laporan itu Komnas Perempuan mencatat dalam rentang 1999 hingga 2009 adanya 154 Perda di seluruh Indonesia yang disebut “menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, baik di tingkat tujuan maupun sebagai dampak.” Dikatakan pula, 63 dari 154 Perda itu secara langsung diskriminatif terhadap perempuan melalui pembatasan hak kemerdekaan berekspresi.
Yang membuat kita mengerutkan dahi, apa yang disebut “diskriminatif” dan “membatasi hak kemerdekaan berekspresi” ternyata tidak lain aturan yang semestinya sudah lazim dalam masyarakat Muslim, tanpa harus ada perda sekalipun. Sebut saja Perda tentang menutup aurat bagi perempuan, Perda larangan khalwat dan prostitusi, juga aturan tentang pembatasan perempuan untuk keluar malam. Apa yang aneh dari aturan ini?
Memungkas laporan di atas, dalam penutup makalah bertajuk “Perempuan dan Ruang Publik” yang ditulis oleh Nong Darol Mahmada untuk Komunitas Salihara tertulis, “Dan Perda syariat yang menghijabisasi perempuan di ruang publik semestinya tak perlu ada. Ruang publik betul-betul menjadi tempat untuk perempuan berkiprah lebih besar lagi tanpa harus dikontrol dengan peraturan remeh temeh seperti cara berpakaian dan jam malam untuk perempuan,” tulisnya.
Perempuan dalam Visi Feminis
Feminisme kotemporer berangkat dari asumsi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam produktifitas akibat kekuatan modal, tradisi dan agama. Dari sini, perlawanan feminis ditujukan pada globalisasi di satu sisi dan apa yang disebut sebagai penafsiran agama yang patriarkis di sisi lain. Untuk itu, perlu ada penafsiran ulang atas al-Quran, tafsir yang mengandung semangat pembebasan perempuan. Dalam resensinya untuk buku “Qur’an menurut Perempuan” karangan feminis masyhur Amina Wadud, di Jurnal Perempuan edisi 48 tahun 2006 menulis, “Jika tujuan masyarakat Islam adalah memenuhi tujuan al-Qur’an yang berkaitan dengan hak, tanggung jawab, potensi dan kapasitas dari semua anggotanya yang sungung-sungguh taat, maka mereka yang benar-benar mengimani al-Qur’an tentu akan berharap agar perempuan mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan produktif.”
Lebih lanjut, pada hal. 168 dalam buku itu ditulis, “kesetaraan moral dan keagamaan antara laki-laki dan perempuan di harapan Tuhan merupakan ungkapan tertinggi dari nilai kesetaraan.” Sedangkan Nong Darol Mahmada mengutip tokoh feminis, Fatima Mernissi dalam bukunya “Women in Islam” (1996) menjelaskan bahwa ketika Nabi shallallahu ‘alaihi Wassalam masih hidup, tercipta konsep ruang public yang bebas dan demokratis di mana perempuan berpartisipasi secara aktif. Perempuan Islam tetap menjalankan tugas reproduksinya tanpa meninggalkan kehidupan publiknya. Ini telihat dari keterlibatan dan keaktifan istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi Wassalam dan para shahabat perempuan beliau yang bisa kita baca dalam sejarah.
Menurutnya, hal ini terjadi karena sejak awal tata ruang yang diciptakan Nabi sudah mengondisikan perempuan untuk aktif dalam ruang publik. Mernissi lalu menyebutkan contoh kiprah beberapa shahabiyah dalam masa itu, seperti Siti Asisyah dan lain-lain. Intinya, feminis mengingkan perempuan berpartisipasi di ruang publik, tanpa ada perbedaan dengan laki-laki, walaupun mereka mengakui bahwa tugas-tugas biologis tertentu tidak mungkin disamakan.
Semua Salah Syariah?
Dengan visi seperti itu, mereka membuat tolak ukur untuk memandang Perda-perda syariah. Kaum feminis membangun asumsi bahwa Perda-perda syariah akan menghalangi terwujudnya visi tersebut. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Women Research Institute pada tahun 2005 bertajuk “Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah”, disebutkan ada 9 ketagori teks perda yang berdampak pada perempuan
(baca : menghalangi visi feminis). Dua di antaranya menyinggung Perda-perda syariah, yaitu kategori “Jilbab dan Pemisahan Ruang Publik Berdasarkan Gender,” dan “Perempuan dan Kesusilaan.” Kategori pertama merujuk ke aturan keharusan memakai pakaian yang menutup aurat dalam Perda no 4 tahun 2002 di Tasikmalaya dan UU no 44 tahun 1999 di Banda Aceh. Sedangkan kategori kedua merujuk ke aturan yang melarang pelacuran dalam Perda no. 1 tahun 2000 di Tasikmalaya dan Perda no. 10 tahun 2001 di Sukabumi. Barangkali yang terlewat dari penelitian ini adalah perda tentang larangan berkhalwat di Qanun no 14 tahun 2003 (Aceh).
Pada penutup bab yang membahas Perda-perda itu dalam penelitian tersebut ditulis, “penerapan (Perda-perda) ini pun mengakibatkan pembatasan ruang publik perempuan dan laki-laki, yang potensial mengakibatkan akses yang tidak setara bagi kedua gender terhadap ruang-ruang tersebut.” Meski begitu, nampak bahwa feminis bukan hendak menyalahkan Islam itu sendiri, melainkan orang-orang yang dianggap memiliki otoritas agama (ulama, fuqaha dan mufassir) yang menafsirkan teks al-Qur’an dan menyusun fikih-fikih yang kemudian disebut syariah tanpa memperhatikan perempuan. Bagi mereka, Islam itu justru membebaskan perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan memperjuangkan kesetaraan gender, sebagaimana dijelaskan dalam pemikiran Amina Wadud dan Mernissi di atas.
Menggugat Asumsi Feminis
Asumsi feminis tersebut nyatanya cacat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Islam membolehkan perempuan sejak masa Nabi shallallahu ‘alaihi Wassalam untuk berpartisipasi dalam ruang publik, terutama membangun masyarakat, berdakwah dan untuk kepentingan ilmu asalkan dengan batas-batas tertentu. Namun, ini tidak menafikan adanya aturan khusus yang berorientasi kepada kehormatan perempuan, yaitu aturan dalam sektor berpakaian dan perilaku.
Menutup aurat sudah ditetapkan sebagai aturan baku dalam al-Qur’an (al-A’raf : 21, al-Ahzab : 59, al-Ahzab : 33, An-Nuur : 21). Sedangkan pembatasan jam malam untuk perempuan dan larangan khalwat dapat dipahami dalam konteks mencegah perbuatan zina (al-Isra : 32), apalagi terdapat hukuman yang keras bagi pezina (an-Nuur : 2).
Terdapatnya aturan-aturan tersebut yang bersumber dari Tuhan Semesta Alam tidak lain untuk tujuan-tujuan tertentu demi kemaslahatan manusia dan masyarakat. Dalam perspektif ushul fiqh, tujuan-tujuan itu disebut sebagai maqashid as-syariah (tujuan-tujuan Syariah). Imam Abu Hamid al-Ghazali membagi maqashid syariah menjadi tiga jenis, yaitu Dharuriyat (primer), Hajiyat (sekunder) dan Tahsiniyat (tersier).
Sedangkan dhaduriyat terbagi menjadi lima tujuan (al-kulliyat al-khamsah), yaitu menjaga agama (hifdz ad-diin), menjaga jiwa (hifdz an-nafs), menjaga akal (hifdz al-aql), menjaga keturunan (hifdz an-nasl) dan menjaga harta (hifdz al-maal). Penulis lain menambahkan poin menjaga kehormatan. Adapun Ibnu Taimiyah mengambil perspektif yang lebih luas, “Sebagian ulama membatasi maslahat pada penjagaan agama, jiwa, harta, kehormatan, akal dan badan. Padahal seharusnya bukan demikian. Maslahat yang sebenarnya ada pada pencapaian manfaat dan pencegahan mudarat. Kelima Maqashid Syariah yang mereka sebutkan baru merupakan satu bagian saja.”
Nah, peraturan-peraturan terkait pakaian dan perilaku perempuan dalam syariat Islam dapat dipahami sebagai realisasi tujuan syariah menjaga jiwa dan kehormatan. Oleh karenanya jilbab juga berfungsi “agar mudah dikenali” (al-Ahzab : 59). Dengan aturan-aturan ini perempuan terhindar dan terlindungi dri niatan jahat laki-laki. Bukankah kaum feminis ingin melawan “dominasi laki-laki?”
Betapa tidak, makhluk yang notabene lemah ini sangat rentan menjadi mangsa dari kekuatan laki-laki yang diperbudak hawa nafsu. Naiknya kasus perkosaaan di India ke permukaan akhir-akhir ini dapat menjadi contoh jelas ketika pakaian, perilaku dan interaksi laki-laki dan peremuan tidak diatur. Sampai-sampai di salah satu propinsi di India keluar larangan menggunakan t-shirt dan celana jeans untuk perempuan, dan tentu mereka tidak akan menganggapnya sebagai “perda syariah,” melainkan aturan untuk melindungi perempuan.
Di Indonesia, Komnas Perempuan sendiri mencatat ada 20.503 kasus kekerasan seksual di ruang publik. Menurut riset nationmaster.com, angka pemerkosaan Indonesia ada di urutan 109, sedangkan 7 dari 10 negara dengan urutan tertinggi adalah negara-negara Eropa yang notabene kaum perempuannya menikmati kebebasan di ruang publik tanpa “terkekang” aturan-aturan soal pakaian, perilaku dan jam malam.
Maka, jika berkomitmen untuk melindungi perempuan, seharusnya kaum feminis juga menaruh perhatian pada perlindungan terhadap kehormatan dan jiwa perempuan. Bahkan kedua hal itu merupakan kebutuhan asasi yang harus dipenuhi sebelum yang lainnya. Logika sederhananya, bagaimana mungkin perempuan bisa menikmati partisipasi di ruang public jika pada saat yang sama nyawa dan kehormatannya terancam?
Asumsi bahwa jika kaum perempuan memakai jilbab, tidak berkhalwat dan tidak keluar malam akan menghambat produktifitas perempuan juga harus dipertanyakan. Faktanya dalam keseharian, banyak perempuan yang menutup aurat dan terjaga pergaulannya ternyata masih bisa berkiprah dalam masyarakat.
Oleh karenanya, penolakan mereka terhadap syariat lebih karena perbedaan miqyasul amal (standar dan tolak ukur perbuatan). Feminis menjadikan kebebasan (freedom) sebagai miqyasul amal, sedangkan seorang Muslim dan Muslimah mestilah menjadikan pertimbangan halal-haram sebagai miqyasnya.*
Penulis adalah pemerhati masalah sosial keagamaan