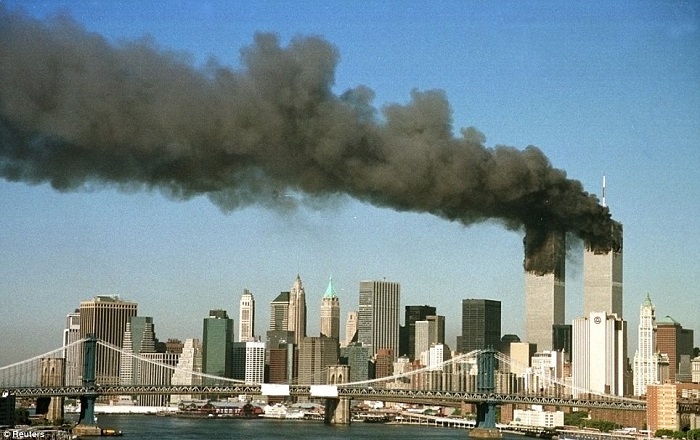Oleh ZA. Maulani *)
Dalam kurun waktu setengah abad setelah merdeka, sejarah Indonesia berjalan di bawah dua rezim: Orde Lama dan Orde Baru. Meskipun namanya berbeda tetapi dalam praktik kehidupan bernegara memperlihatkan isi yang sama. Yakni, praktik negara kekuasaan (maachtstaat), pemerintahan yang otoritarian dan sentralistik, serta korupsi yang merajalela. Semua ini membawa kepada kehancuran ekonomi dan krisis di berbagai bidang kehidupan nasional secara menyeluruh.
Reformasi yang dimulai pada 1998 telah membuka peluang bagi supremasi sipil untuk mengonsolidasikan kepemimpinan dan kewibawaan serta mengefektifkan kontrol politik atas militer dan polisi. Tapi nyatanya sipil tak berhasil memanfaatkan peluang itu dengan baik. Politisi sipil tak cukup memiliki kepercayaan pada diri sendiri.
Ketika pada tanggal 12 April 2004 wakil panglima TNI jenderal Fachrul Razie menyatakan, ‘’TNI sudah berubah, TNI tidak lagi mengemban tanggung jawab di bidang keamanan (dalam negeri) yang kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab polisi,’’ para politisi sipil di MPR justru melakukan hal sebaliknya. Mereka memperpanjang kehadiran fraksi TNI-Polri di MPR sampai dengan tahun 2009.
Di luar MPR, partai-partai politik sipil berlomba-lomba mengundang militer aktif maupun mantan jenderal untuk bergabung dengan mereka. Sehingga membuat panglima TNI Jenderal Endriartono Soetarto mengeluarkan pernyataan keras, “Jangan ada yang mencoba-coba menyeret militer (kembali) berpolitik.”
Dalam dua pemerintahan era reformasi, peluang emas untuk menerapkan kontrol politik sipil yang efektif terhadap tentara justru dilepaskan secara sengaja. Dua orang menteri pertahanan yang sama sekali tidak akrab, tidak paham, dan tidak menguasai masalah-masalah pertahanan dan militer, malah ditempatkan pada posisi penentu kontrol tersebut.
Lemahnya manajemen nasional ini jelas merefleksikan pemerintah yang belum juga berhasil membawa negeri ini keluar dari kemelut krisis multi-dimensional. Malah, terkesan bergulir kian parah.
Kesan tersebut terefleksi melalui survei dan polling yang hasilnya menunjukkan keinginan masyarakat yang kian besar untuk mencari pemimpin yang ‘kuat’. Pemimpin seperti ini dipersepsikan sebagai tokoh jenderal militer, manajer gaya militer yang efisien, tegas, dan tak kenal tawar-menawar, terutama dalam penegakan hukum.
Polling yang dilakukan The National Leadership Center bekerjasama dengan Thomas Nelson Suffrage (perusahaan polling terbesar ketiga di dunia) yang dilaksanakan antara tanggal 28 Maret sampai 1 April 2004 menjelang pemilu 5 April 2004 lalu telah membuktikan hal ini. Lebih dari 1.016 responden di 18 provinsi dengan error margin 3,1 persen menghendaki jenderal militer sebagai kepala pemerintahan yang akan datang. Jumlah ini mencapai 62 persen, atau lebih dari separuh, dari total responden. Sedangkan yang menghendaki Megawati Soekarno Putri —yang sipil— hanya 22 persen.
Keluar dari Krisis
Mengapa negeri ini tak segera bisa keluar dari krisis? Penyebab terpentingnya adalah adanya sikap tidak saling percaya antar-anak bangsa. Ini sekaligus mencerminkan adanya krisis kepemimpinan yang akut.
Fungsi terpenting kepemimpinan adalah melakukan mobilisasi untuk menyatukan bangsa dalam satu ikatan kebangsaan yang kohesif. Sebuah bangsa yang bersatu, meskipun ada berbagai perbedaan latar-belakang etnisitas, kepentingan social, ekonomi, budaya, paham, aliran keagamaan, ideologi politik, dan sebagainya.
Masalah akut krisis kepemimpinan ini tercermin dari banyaknya responden di setiap survei yang mendambakan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang memiliki integritas dalam track record-nya, jujur, mampu bersikap adil, kompeten menyelesaikan program politiknya, dan memiliki keberanian politik mengatasi permasalahan yang kontroversial dan dilematik. Pemimpin yang mampu membawa bangsa ini hijrah dari keterpurukan.
Untuk keluar dari krisis multidimensional yang menghimpit bangsa, diperlukan langkah-langkah yang jelas, tegas, realistik, disesuaikan dengan tahapan prioritas. Untuk jangka lima tahun pertama dibutuhkan tindakan mendesak antara lain: menegakkan stabilitas keamanan dalam rangka membangun supremasi hukum sehingga masyarakat merasa tenteram dalam menjalankan kehidupan mereka; mengatasi permasalahan yang nyata dan segera; mengatasi masalah pengangguran sebagai masalah pokok keterpurukan masyarakat; meningkatkan produktivitas dan kemampuan daya saing di pasar domestik dan dunia; membasmi korupsi secara tegas, tegar dan ajeg; meningkatkan kualitas keluaran pendidikan khususnya pada bidang ilmu, teknologi, dan industri.
Lapis Menengah yang Kuat Pada tataran jangka sedang atau sepuluh tahun ke depan, pemerintah yang akan datang harus sukses memberdayakan dan meningkatakan status kesejahteraan sosial-ekonomi rakyat pada umumnya melalui keberpihakan kepada usaha kecil dan menengah; memulihkan kekuatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi nasional; serta melanjutkan kebijakan membangun dasar-dasar yang sehat dan kuat bagi industrialisasi dalam rangka membangun Indonesia sebagai sebuah trading nation.
Kebijakan membangun lapisan kelas menengah yang kuat dan mandiri harus merupakan usaha pelengkap pembangunan politik-ekonomi sebagai sumber pembentukan kader kepemimpinan nasional yang andal dan komitmen kepada rakyat. Kelas menengah tidak dapat ditampilkan dari dalam masyarakat miskin, teralienasi, dan dicengkeram oleh frustasi.
Masyarakat tradisional akan melahirkan kepemimpinan yang bercorak tradisional. Sebaliknya, masyarakat madani akan melahirkan kepemimpinan yang demokratik, dapat dipercaya, dan kompeten.
Dalam jangka panjang kita harus mampu membangun masyarakat kita dengan perbandingan struktur sosial sebagai berikut: 10 persen penduduk berpendapatan rendah, 70 persen berpendapatan menengah, dan 20 persen berpendapatan tinggi.
Namun, agar permasalahan sebagaimana yang ditengarai di atas tak lagi berulang, dari sekarang kita harus mulai melaksanakan strategi pengembangan budaya dalam rangka perombakan kultur. Dengan begitu, masyarakat kita bisa menjadi lebih cerdas dan cakap mengelola kehidupan mereka dengan meninggalkan nilai-nilai sosial yang merugikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang lebih baik, lebih berorientasi kepada pencapaian, lebih berdaya-saing. Yaitu nilai-nilai yang lebih kompatibel untuk menjadikan bangsa ini lepas dari keterpasungannya sebagai “bangsa lembek”, dan menjadikannya “bangsa yang keras dan tegar” mengatasi tantangan-tantangannya di masa depan. Reformasi yang dijalankan harus meletakkan dasar yang kokoh untuk maksud tersebut. *
* Penulis, mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Tulisan ini diambil dari majalah Hidayatullah edisi Agustu 2004.