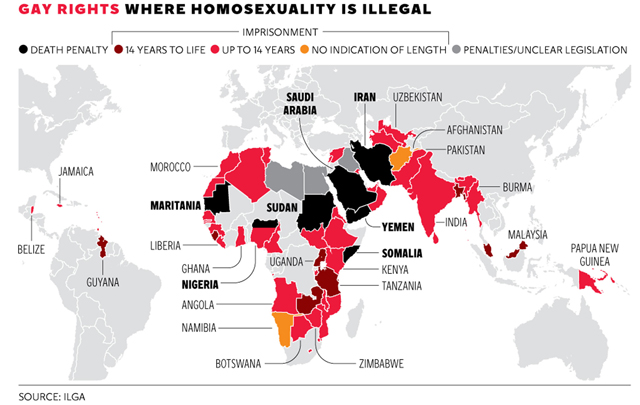Oleh: Rofi Munawwar
Hidayatullah.com | DI PENGHUJUNG bulan Juni lalu, Setara Institute merilis survei soal model beragama pada 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Hasilnya perguruan-perguran negeri ini terpapar paham Islam radikalisme.
10 PTN itu adalah UI, ITB, UGM, UNY, UIN Jakarta dan bandung, IPB, UNBRAW, UNIRAM, dan UNAIR. Direktur Riset Setara Instite, Halili mengatakan ini dikarenakan corak kegiatan keislaman dikooptasi oleh gologan Islam tertentu yang tertutup atau eksklusif.
Dalam penelitiannya, Setara Institute menggunakan metode kuantitatif. Untuk mengukurnya, peniliti menanyakan persetujuan atas beberapa pernyataan kepada responden.
Contohnya soal: jalan keselamatan dunia dan setelah mati hanya terdapat dalam ajaran agamaku, ajaran agamaku sudah sempurna, dan saya tidak memerlukan pedoman tambahan di luar agama, atau hanya ajaran agamaku yang dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Semakin tinggi nilai yang diperoleh pertanyaan di atas, maka semakin tinggi fundamentalisme beragama responden.
Riset tersebut bukanlah yang terbaru. Sudah sering istilah radikal dan radikalisme ini dikaitkan dengan umat Islam. Standar-standar pun berusaha mengerdilkan peran Islam dalam kehidupan masyarakat. Arahnya ingin membangun cara pandang bahwa, “Semakin kuat Islam dalam kehidupan Anda, semakin kuat anda berpontensi radikal.”.
Dari istilah ini lah diarahkan asumsi sebagai pemicu terorisme, ekstrimisme, intoleran dan perongrong NKRI. Maka lahirlah wacana strategi deradikalisasi oleh pemerintah.
Hingga kini, istilah radikal sendiri pun secara definitif masih kabur. Dahulu di era perjuangan kemerdekaan kata radikal diartikan sangat baik, kelompok-kelompok progesif dan anti penjajahan selalu dielu-elukan dengan kata radikal.
Kini istilah radikal selalu diamsusikan sebagai musuh bangsa. Ancaman bagi NKRI, UUD 1945 dan Pancasila. Tidak bisa kita pungkiri stigma ini selalu dialamatkan kepada Islam, -lebih khusus syariat Islam. Orang-orang yang alergi syariat Islam selalu memakai opini ini.
Padahal jika kita merujuk makna radikal dalam arti ingin memisahkan diri dari NKRI, UUD 1945 dan Pancasila. Tidak bisa kita lupa catatan sejarah pada 18 Agustus 1945. Sebuah ancaman ‘Radikal’ –yang bermakna ingin memisahkan diri dari Indonesia- datang dengan mengatasnamakan orang timur.
Singkatnya, waktu itu Indonesia yang baru berumur sehari terancam bubar. Lantaran Mohammad Hatta setelah menemani Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada pagi 17 Agustus 1945, sore harinya Hatta kedatangan seorang opsir Angkatan Laut Jepang yang mengirim pesan keberatan atas dasar Negara dari Piagam Jakarta.
“Opsir itu, yang aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan sungguh, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik, yang (tinggal di wilayah yang) dikuasai Kaigun, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-undang Dasar, yang berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” ujar hatta, sebagaimana ditulis dalam autobiografinya, Mohammad Hatta: Memoir (1979).
Baca: Polisi Awasi Masjid dan Kampus, Peneliti: Itu Misi “Membonsai” Perkembangan Islam
Isi Piagam Jakarta yang dipermasalahkan adalah sila pertama. “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Padahal kalimat ini adalah bagian dari kesepakatan yang disusun oleh Panitia Sembilan, bentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang ditandatangani 22 Juni 1945.
Dalam buku Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam (2011) Hamka Haq menulis bahwa sila itu merupakan hasil kompromi antara ideologi Islam dan ideologi kebangsaan yang mencuat selama rapat BPUPKI berlangsung.
Karena dalam buku R.M.A.B Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidik Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan, Ki Bagus Hadikusumo bahkan lebih tegas lagi meminta kata-kata ”bagi pemeluk-pemeluknya” ditiadakan, sehingga berbunyi: “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam.” Artinya, dalam pandangan Ki Bagus, syariat Islam harus berlaku secara umum di Indonesia.
Hatta menambahkan, walaupun orang Kristen Timur mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka dan hanya ditujukan kepada rakyat yang beragama Islam. Tetapi bagi Hatta, “tercantumnya ketetapan seperti itu dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar, berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika ”diskriminasi” itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia…”
Piagam Jakarta sendiri telah disepakati dari perjuangan memeras otak dan tenaga berhari-hari oleh tokoh-tokoh terkemuka bangsa. Mohammad Natsir mengatakan, penghapusan tujuh kata tersebut sebagai ultimatum kelompok Kristen, yang tidak saja ditujukan kepada umat Islam, tetapi juga kepada bangsa Indonesia yang baru 24 jam diproklamirkan.
Natsir menegaskan, peristiwa tanggal 18 Agustus 1945 adalah peristiwa sejarah yang tak bisa dilupakan. ”Menyambut proklamasi tanggal 17 Agustus kita bertahmid. Menyambut hari besoknya, tanggal 18 Agustus, kita istighfar. Insya Allah umat Islam tidak akan lupa,” kata Natsir.
Kini 74 tahun setelah peristiwa 18 Agustus 1945 sudah berlalu. Umat Islam kini menghadapi situasi yang pelik. Dalam narasi-narasi publik, seperti diskusi politik di televisi dan diskursus pembahasan di lini media massa, syariat Islam terus tersudut. Syariat Islam selalu dituduh sebagai bentuk perlawanan terhadap UUD 1945, dianggap merongrong NKRI bahkan tuduhan ingin menggadaikan pancasila. Dengan kampanye “NKRI, UUD 1945 dan Pancasila adalah Harga Mati”.
Padahal proses lahirnya Negara, UUD 1945 dan pancasila sangat dekat dan erat dengan semangat Syariat Islam. Walaupun sila pertama dalam piagam Jakarta lepas. Tapi nafasnya masih terasa seperti dalam kalimat “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,…” di pembukaan UUD 1945 dan sila pertama dalam pancasila yang kental dengan semangat mentauhidkan Allah.
Pada akhirnya, sebenarnya ada jawaban pamungkas untuk menghadapi stigma radikalisme terhadap Islam. Ialah rekonstruksi sejarah dan kesadaran sejarah kita harus diperkuat.*
Penulis peminat masalah sejarah