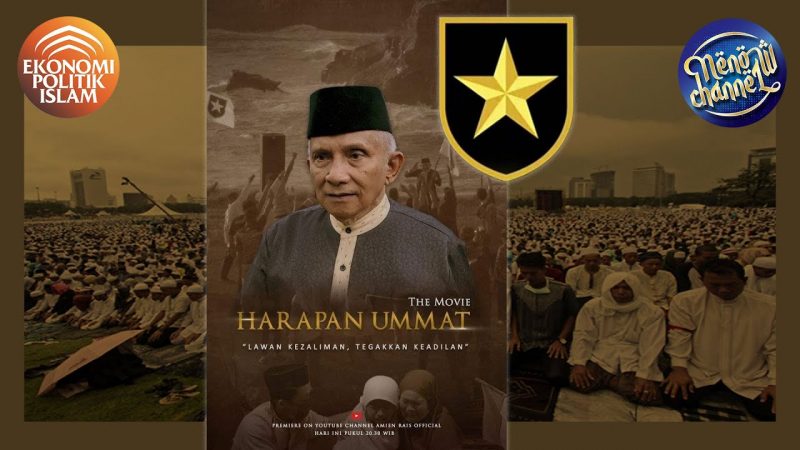Oleh: Kholid A.Harras
Hidayatullah.com| JURU bicara penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengakui, penggunaan diksi new normal dalam penanganan pandemi virus corona selama ini tidak tepat. Menurutnya, saat mendengar istilah new normal masyarakat hanya terfokus pada kata ’normal’-nya saja, bukan pada kata ‘new’-nya. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman terhadap istilah tersebut. Oleh karenanya, pihaknya akan mengganti istilah new normal dengan “adaptasi kebiasaan baru”.
Sejak awal, istilah new normal memang menjadi polemik. Ada yang setuju, tetapi banyak yang menentangnya. Kritik terhadap istilah ini pun datang dari banyak pihak. Pakar epidemiologi misalnya, mengkritik keras, khususnya saat istilah tersebut jadi pembenar melakukan relaksasi aktivitas publik di luar rumah di tengah eskalasi penyebaran Covid-19 yang terus melesat. Penggunaan diksi tersebut bukan hanya tidak tepat tetapi juga menyesatkan.
Secara semantik-kognitif, penggunaan istilah new normal memang pontensial memicu kesalahpahaman persepsi pada masyarakat. Hal ini antara lain karena kosakata ‘normal’ diserap ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda: normaal, dan berfungsi sebagai kata sifat. Arti kata ini dalam KBBI1) Menurut aturan atau pola yang umum; sesuai dan tidak menyimpang aturan, norma atau kaidah; sesuai keadaan yang biasa; tanpa cacat; tidak ada kelainan; dan 2) Bebas dari gangguan jiwa.
Berdasarkan uraian di tersebut, maka dalam kantong memori semantik-kognitif sebagian besar masyarakat Indonesia, kata ‘normal’ dipahami sebagai “suatu kondisi ideal, tidak menyelisihi norma atau sebagaimana seharusnya”. Selain itu, istilah ini dipersepsi sesuatu yang baik atau positif.
Sebagai istilah, new normal menimbulkan persoalan manakala istilah ini diberi muatan makna yang sama sekali baru. Seperti dikemukakan Achmad Yurianto (20/5/2020), new normal adalah tatacara hidup sehat sesuai protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi virus corona. Caranya yakni senantasa menggunakan masker saat berada di ruang publik, menjaga jarak fisik, serta menghindari kerumunan.
Istilah baru tersebut tentu saja bertabrakan dengan konsep ‘normal’ sebagaimana dipahami saat ini oleh khalayak. Masyarakat pun dibuat bingung, karena kondisi yang sejatinya mahiwal, harus dipahami sebagai hal yang normal. Situasi yang sesungguhnya dapat mengancam nyawa, harus disikapi sebagai kondisi yang biasa-biasa saja.
Boleh jadi menyadari potensi bisa menimbulkan terjadinya kesalahanpahaman persepsi terhadap frasa new normal, sejak awal Pemda Jawa Barat cukup berhati-hati dalam menyerap istilah tersebut. Mereka tidak ikutan latah menyerap frasa new normal lewat cara adopsi sehingga menjadi ‘kenormalan baru’ seperti drekomendasikan Badan Bahasa.
Mereka memilih mengkreasikan istilah new normal ini sehingga menjadi AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru), karena begitulah sesungguhnya yang ingin dicapai dari istilah tersebut. Jadi kata ‘normal’ tidak harus diterjemahkan menjadi ‘normal’ lagi.
Sependek pengetahuan penulis, ijtihad bahasa Pemda Jabar ini agaknya lebih memudahkan masyarakat Jawa Barat dalam memahami pengertian dan konsep new normal. Untuk ijtihad perkara ini, apresiasi layak diberikan kepada Kang Emil sebagai gubernur Jabar.
Karena istilah AKB atau Adaptasi Kebiasaan Baru akhirnya dijadikan sebagai istilah resmi oleh pemerintah pusat untuk menggantikan istilah new normal yang sejatinya memang tidak normal tersebut. Harus diakui, salah satu dampak penyebaran virus corona ke berbagai belahan dunia, telah mengakibatkan melimpahnya peristilahan baru.
Setiap hari masyarakat seolah dipaksa berkenalan dengan berbagai istilah baru dalam bidang covid-19. Misalnya ada istilah droplet , specimen , suspect, social distancing, physical distancing, lockdown, rapid test, swab test, hand sanitizer, thermo gun, disinfektan/disinfeksi. Sependek pengetahuan penulis, berbagai istilah tersebut masih belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia.
Agar berbagai istilah yang berasal dari bahasa asing bisa dipahami masyarakat tentunya proses penyerapannya harus dengan mempertimbangakan faktor. Antara lain, harus cocok konotasinya, lebih singkat dibandingkan terjemahan Indonesianya, serta lebih mudah dipahami maksudnya.
Modus penyerapannya juga bisa menggunakan bererapa pola: adopsi, adaptasi, penerjemahan, atau kreasi. Hal ini perlu dilakukan agar fungsi-fungsi bahasa seperti alat berinteraksi antarmanusia, alat untuk berfikir, serta sarana dalam menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat dapat tercapai.
Ihwal pentingnya memilih kosakata yang tepat dalam proses komunikasi, penting kita memperhatikan pernyataan Heinrich Theodor Böll, pemenang Hadiah Nobel Sastra dari Jerman pada 1972: Di balik setiap kata, tersimpan makna ‘muatan dunia’ (whole world), yang harus dibayangkan para penggunanya.
Setiap kata juga memiliki beban kenangannya tersendiri yang sangat besar. Tidak hanya bagi setiap orang tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Saya khawatir, banyak orang yang menggunakan kata-kata tanpa merasakan beban yang terkandung di dalamnya.
Sungguh, sesiapa yang bermain dengan kata-kata sejatinya ia sedang bermain dengan sebuah dunia”.*
Pengajar pada FPBS Univeritas Pendidikan Indonesia