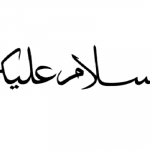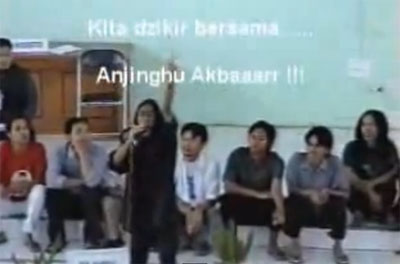~ “The ideal of benign neglect is a myth”’~
(Will Kymlicka, Political Theorist of Multiculturalism)
Oleh: Muhammad Iswardani Chaniago*
ISU kemajemukan, diversitas, pluralisme atau multikulturalisme nyaris selalu hangat. Memang demikian. Sebab, kemajemukan adalah tantangan kontemporer.
Itu mungkin yang telah menyebabkan liberalis ternama, John Rawls (1921-2002), terdorong menulis karyanya yang terkenal, Political Liberalism. “The political culture of a democratic society is always marked by a diversity…what are the grounds of toleration so understood and given the fact of reasonable pluralism as the inevitable outcome of free institution?” tanya Rawls, saat ia menjelaskan hal yang mendorongnya menulis Political Liberalism .
Oleh sebab itu tak aneh juga jika banyak literatur politik memasukkan isu keberagaman (pluralisme dan multikulturalisme) ke dalam tema contemporary political theory. Walaupun ada yang tidak setuju, sebab memandang multikulturalisme bukan sebagai teori, tapi filsafat politik.
Namun faktanya, dulu Barat tidak banyak menghadapi isu ini. Isu yang hangat saat itu di Barat adalah soal heretics. Konsep yang membagi individu dan kelompok ke dalam tipologi sesat dan tidak sesat. Heretics merupakan isu tua keagamaan yang telah dimulai di abad ke 4 hingga awal reformasi gereja di abad 16. Kemudian muncul gagasan religious toleration sebagai responnya, dengan sejumlah penggagas macam Martin Luther (1483-1546), Michel Servetus (1509-1553), Castellio (1515-1563) dan John Locke (1632-1704). Jadi memang isu multikulturalisme belum terlalu eksis saat itu. Atau mungkin belum terlalu terlintas di benak para pelopor toleransi Eropa. Wajar jika Susan Mendus pernah mengeritik Locke lantaran teori toleransinya terlalu religious.
Justru di dunia Islam isu multikulturalisme ini sudah pernah mendapat sentuhan. Setidaknya ulama klasik tidak terlalu kuper dengan interaksi kaum minoritas. Tulisan mereka tersebar dalam berbagai karya-karya fikih atau tafsir. Salah satu karya fikih bertema khusus yang ditemukan dalam literatur klasik adalah Ahkam Ahl al-Dzimmah karya, Ibn Qoyyim al-Jauziyah. Ulama kenamaan dari mazhab Hanbali.
Terkait dunia Islam penulis melihat setidaknya ada dua problem terkait isu multikulturalisme yang berkembang. Pertama, isu diskriminasi fiqhiyah yang dituduhkan pada fikih Islam. Konsep jizyah, larangan nonmuslim menjadi pemimpin dan lainnya kerap menjadi sasaran empuk kritik. Menurut para pengkritik, regulasi fikih yang demikiaan sudah tidak relevan dengan semangat persamaan. Menurut para pengkritik, regulasi fikih yang demikiaan sudah tidak relevan dengan semangat persamaan.
“Dalam kitab fikih klasik mereka (non Muslim) tidak mendapatkan perhatian…Di sinilah, amat terkesan bahwa fikih klasik telah menelantarkaan dan mendiskriminasikan non Muslim,” demikian gugatan sejumlah inteletual liberalis seperti tercermin dalam buku Fikih Lintas Agama terbitan Paramadina (Fikih Lintas Agama, hal 146) Negara haruslah netral dan bersikap benign neglect terhadap setiap tipologi minoritas yang hidup. Benarkah?
Sejatinya argumen benign neglect yang dikemukan para pengkritik pernah dikritik Kymlicka dalam bukunya Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Right dan dianggap sebagai sebuah mitos daripada realitas. Dalam pandangan Kymlicka argumen benign neglect tak pernah nyata dan merupakan problem serius yang dikandung argumen ini.
Kymlicka menunjukkan bagaimana sejumlah negara ternyata berpihak kepada performa budaya tertentu dan gagal menjadi netral. Pemberian hari libur pada satu agama tertentu dan tidak pada agama lain; memilih bahasa tertentu; simbol negara, lagu kebangsaan yang mewakili budaya tertentu; memberikan ruang posisi politis untuk institusi agama tertentu adalah buktinya. Sehingga Kymlicka sampai pada kesimpulan, “there is no way to have a complete ‘separation of state and ethnicity’. In various way, the ideal of ‘benign neglect’ is a myth.”
Dalam fikih Islam alternatifnya bisa pemberian bebas wajib militer (jihad) bagi ahl al-dzimmah. Kompensasi ini merupakan hal yang telah eksis dalam fikih Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Karim Zaidan, dalam Ahkam al-Dimmiyyin wa al-Musta’minin, bahwa bila Ahl al-dzimmah ikut berpartisipasi dalam aktivitas bela negara, maka kewajiban jizyah menjadi gugur (Abdul Karim Zaidan, Ahkam al-Dzimmiyyin wa al-Musta’minin, hal 155). Hal yang sama juga dikatakan oleh al-Qaradhawi dalam Fiqh al-Jihad. Kesimpulan demikian diambil karena jizyah dipandang sebagai kompensasi dari bantuan yang mereka (ahl al-d}immah) berikan kepada negara. Bila mereka tidak memberikan bantuan itu, maka mereka dikenakan jizyah. Demikian pula sebaliknya. Dasar ini kerap dipakai dalam fikih Mazhab Hanafi, seperti yang disebutkan Abdul Karim Zaidan (Abdul Karim Zaidan, Ahkam al-Dzimmiyyin wa al-Musta’minin, hal 143 dan 145).
Sedangkan al-Qaradhawi@ berpandangan kewajiban jizyah muncul sebagai pengganti berupa harta dari kewajiban jihad fisik. Karena laki-laki ahl al-dzimmah pada hakikatnya adalah ahl al-qital (mampu berperang membela negara). Ketika mereka membayar jizyah, hilanglah kewajiban tersebut. Itulah mengapa -menurut al-Qaradhawi-perempuan, laki-laki tua, dan anak-anak ahl al-dzimmah tidak diwajibkan ber-jizyah. Sebab mereka tidak termasuk ahl al-qitaal (al-Qaradhawi, Fiqh al-Jihad, hal 846).
Kompensasi lain yang bersifat khusus juga bisa diberikan dalam betuk pendirian mahkamah hukum tersendiri dalam hukum privat pada tubuh komunitas non-Muslim. Minoritas non-Muslim dapat menggunakan institusi ini guna menjalankan praktik keagamaan privat mereka tanpa harus tunduk pada hukum Islam. Mereka dibebaskan menjalankan akidah dan hukum privat mereka sebagai pengajawantahan keterikatan terhadap agama dan nilai budaya mereka. Al-Qaradhawi termasuk ulama yang menggagas hal itu dan mendukung perlakukan khusus terhadap non-Muslim ahl al-dzimmah.
Fakta kecenderungan setiap pemerintahan terhadap kultur (dan agama) tertentu, ini membuat Kymlicka menyadari realitas bahwa pertanyaan yang paling penting bukanlah menghindari kecenderungan yang nyaris terdapat di setiap negara. Tapi, menjamin bahwa praktik kecenderungan tersebut dilakukan dengan adil (fairly) (Kymlicka, Multicultural Citizenship, hal 115). Jika demikian, tuduhan terhadap fikih Islam dalam konteks hubungan Muslim-non Muslim (jizyah, larangan memilih pemimpin nonmMuslim dan lainnya) tidak relevan bila dikaitkan dengan tuduhan diskriminasi. Karena tuduhan tersebut tidak memahami realitas kultural-politis di banyak negara.
Kedua, multikulturalisme khususnya dalam diskursus Muslim dan Islam Indonesia sering diartikan sebagai benign neglect pula. Semuanya minta dinetralkan. Bukannya hanya pada ranah sosial-religi tapi juga politik hukum. Intinya Pancasila harus diartikan netral agama dan tak boleh didominasi agama tertentu. Argumen ini bermasalah secara sosial dan ketatanegaraan. Secara sosial setiap agama berbeda, dengan latar belakang sejarah yang beragam pula. Misalnya, Kristen dan Islam. Pada kasus ini sejarah keduanya dengan segala implikasi teologis di belakang tidak bisa disamakan.
Trauma sejarah demikian tidak dimiliki Islam. Negara dan kekuasaan bukan momok yang menakutkan bagi peradaban Islam. Negara dengan agama bisa berdamai. Meskipun, bukan hanya sekali kasus semacam heretics terjadi di lingkungan peradaban Islam, tapi solusinya tidak pernah menghasilkan sekularisasi. Apalagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam lebih tegas dibandingkan dalam tubuh Kristen.
Kasus Ali Abd al-Raziq yang divonis bersalah oleh institusi al-Azhar karena bukunya Islam wa Usul al-Hukm yang beraroma sekularisme adalah bukti sahih tegasnya sikap Islam dalam menyikapi isu kekuasaan. Dan hingga sekarang tidak ada gugatan yang menghasilkan gelombang dahsyat dari tubuh Islam sendiri atas sikap Islam terhadap sekularisme. Hal yang berbeda dengan Kristen.
Sehingga jika sikap Kristen kontemporer adalah melepaskan negara dari pelukan agama, maka sikap itu tidak bisa dipaksakan kepada Islam yang mengambil posisi sebaliknya. Konsekuensinya, keengganan Kristen memasuki ranah politik hukum lebih merupakan sikap teologis dan aspirasi Kristen sendiri yang belum tentu diamini agama lain.
Kedua, benign neglect tidak cocok dengan logika ketatanegaraan kita. Dalam pandangan Hamdan Zoelva, mantan ketua Mahkmah Konstitusi, sumber norma konstitusi Indonesia jauh lebih kompleks daripada sejumlah negara lain yang hanya memuat norma dasar organ negara. UUD 1945 juga memuat sejumlah norma dasar kebijakan dalam ekonomi, politik dan budaya. (Hamdan Zoelva, Mengawal Konstitusionalisme, hal 24) Tentu di dalamnya termasuk agama. Menjauhkan agama dalam politik hukum sama saja berlaku diskriminatif terhadap agama. Ini bisa berdampak pada pengistimewaan hukum adat dan Barat dalam memengaruhi politik hukum yang justru bententangan dengan konstitusi itu sendiri. Lalu apakah dalam konteks sekularisasi dan nonsekularisasi berarti konstitusi negara tidak netral terhadap agama yang ada? Atau dengan kata lain cenderung berpihak pada Islam ketimbang yang lain?. Seperti yang dikatakan Kymlicka, “The Ideal of benign neglect is a myth.”
Mahasiswa S2 konsentrasi Agama dan Politik, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta