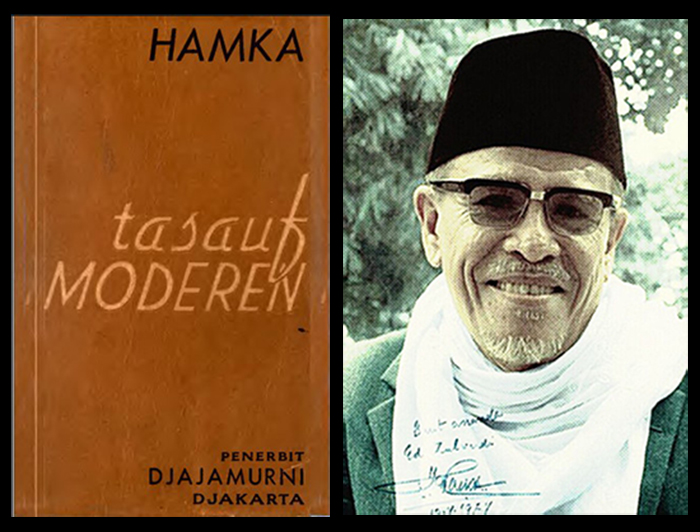Moderasi beragama sangat kental dengan misi orientalis yang berupaya membuat Islam yang dinilai radikal seolah menjadi jinak, tetapi lambat laun pemikiran itu justru dapat merusak.
Oleh: Apriyanti Kartika Agustin
Hidayatullah.com | ISU moderasi beragama terus mencuat. Generasi muda sebagai aset berharga, terus menjadi sasaran yang dimasuki lewat jalur pendidikan. Hal ini tentu harus diwaspadai. Pasalnya, moderasi beragama sangat kental dengan misi orientalis yang berupaya membuat Islam yang dinilai radikal seolah menjadi jinak, tetapi lambat laun pemikiran itu justru dapat merusak.
Bagaimana tidak, moderasi agama yang dikampanyekan menjadi sarana perekat bangsa, pada praktiknya justru hanya sibuk mengurusi satu agama saja; yaitu Islam.
Misalnya tahun 2020 lalu, menteri agama menghilangkan konten yang dinilainya radikal dan eksklusif. Tetapi hal itu hanya dilakukan pada buku mata pelajaran Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, Al-Qur’an dan Hadis, dan Bahasa Arab. Telah nampak kerancuan dari program tersebut.
Tak tanggung-tanggung, moderasi beragama kini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kemenag telah menjabarkan moderasi beragama dalam Rencana Strategis (renstra) pembangunan di bidang keagamaan lima tahun mendatang.
Kabarnya Kemenag tidak sendiri menjalankan misinya itu. Bersama Setara Institute dan USAID, lembaga bantuan milik pemerintah Amerika yang biasa membiayai program liberalisasi Islam di Indonesia, ketiganya telah menandatangani kesepakatan untuk mencegah adanya radikalisme.
Siapkan Fasilitator, Kemenag Inginkan Implementasi ‘Moderasi Beragama’ di Sekolah dan Perguruan Tinggi Umum
Di Balik Topeng Moderasi
Jika ditarik benang merah antara misi kesepakatan ketiganya dengan program yang dibuat, sangat menunjukkan ajaran Islamlah yang dianggap radikal. Padahal makna radikal yang mereka maksud, sama sekali tidak terbukti ada dalam tubuh Islam.
Prof. Ahmad Zahro, guru besar Fikih UIN Sunan Ampel Surabaya mengungkapkan bahwa ia menolak istilah radikal ala rezim yang konotasinya negatif, karena radikal artinya akar atau pondasi. “Jadi ajaran Islam itu semuanya radikal (mengakar pada akidah dan dalil-dalil syar’i) dalam pengertian positif” paparnya.
Benar saja, pada satu kesempatan di bulan Mei 2018 lalu, pemerintah Indonesia mengadakan acara Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama se-Dunia dengan tema Islam Wasathiyah di Istana Bogor.
Di sana dijelaskan bahwa moderat yang dimaksud pada program moderasi beragama yang sudah mengglobal ini, bukanlah moderat yang dipahami kaum Muslim. Melainkan program rancangan Barat yang diarahkan untuk menerima nilai-nilai Barat dan tidak menentang Barat dalam segala aspek.
Dengan ini, akhirnya siapa pun yang menolak misi moderasi beragama, akan dicap radikal. Syahdan, ini berarti umat Islam akan terus menjadi objek sasaran misi Barat.
Wasathiyyah bukan Moderasi
Awalnya, semua memahami istilah moderasi beragama sebagai sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama. Sikap tersebut diakui sebagai perwujudan Surat Al-Baqarah ayat 143 yang menyebutkan kadzâlika ja’alnâkum ummatan washatan… (dan demikianlah Kami jadikan kalian sebagai umat yang “wasath”…).
Padahal moderasi beragama sebagai perwujudan Islam Wasathiyyah hanyalah akal-akalan musuh Islam agar terkesan bisa dibenarkan. Mereka menjadikan ayat Al-Qur’an sebagai alat, dan membelokkan dari makna sebenarnya.
Sikap mengambil jalan tengah dalam konteks beragama, justru menyamarkan kebenaran itu sendiri. Sikap ekstrem yang dialamatkan kepada Islam, sebetulnya hanya label agar umat Islam lupa terhadap batas-batas toleransi dan langsung menerima jalan alternatif atas kebenaran yang standarnya dibuat manusia, untuk diterapkan pada lingkup beragama.
Berbeda dengan makna wasath menurut Fakhrudin Al-Razi. Beliau menyebutkan ada beberapa makna yang satu sama lain saling berdekatan dan saling melengkapi. Di antaranya: 1) Adil, 2) Pilihan, 3) Paling baik, dan 4) Orang-orang yang dalan beragama di tengah-tengah antara ifrath (berlebih-lebihan hingga mengada-ngadakan yang baru) dan tafrith (mengurang-ngurangi ajaran agama).
Dari pemaparan tersebut, makna wasath tidak sesuai untuk dijadikan alat propaganda bagi pemikiran yang merusak. Sebab wasath sama sekali tidak berkonotasi untuk menerima nilai-nilai Barat yang kemudian membuat umat Islam kehilangan jati dirinya; mengurang-ngurangi ajaran agama, yang akhirnya justru moderasi beragama ini yang keluar dari makna wasath dalam Islam.
Menurutnya, wasathiyah identik dengan mengambil jalan tengah yang lurus dalam urusan ibadah dan duniawi. Jalan antara wahyu (nagl) dan rasional (aql), antara dunia material dan immaterial.
Wasathiyah adalah kualitas jalan tengah yang adil di mana semua kebajikan terakumulasi. Lawan dari wasathiyyah adalah ghuluww (berlebihan atau ekstrim) dalam menjalankan syariah (amaliyah), yang melampaui atau melanggar parameter yang diizinkan atau ditentukan sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Hadits.
Gus Hamid tentang Moderasi Beragama dan Islam Washatiyah
Islam dan Moderasi
Bermacam kriteria yang disematkan dalam kata moderasi beragama, sangat tidak mendasar. Dalam banyak kasus, modernitas mengangungkan ‘rasionalitas’ sebagai tolak ukur kebenaran. Mengutip Ahmad rizky M. Umar dalam bukunya Nalar Kritis Muslim Abad XXI, “Hasil olah pikir, cipta dan karya manusia menjadi sangat mulia dalam kerangka kerja modernisme.” Pandangan seperti ini jelas sangat berbahaya saat moderasi disandingkan dengan kata agama.
Moderasi beragama yang seolah menjadi jalan tunggal, solusi bagi ancaman radikalisme yang maknanya saja samar, perlu dituntaskan karena kontradiksi yang dihasilkannya. Sebab alih-alih mengimbangi kehidupan persatuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, moderasi beragama justru menghancurkan nilai-nilai yang sudah tertata rapi.
Padahal makna moderat, Prof. Hamid mengangkat pengertian Muqtedar Khan, cendekiawan Muslim asal Kanada. Menurutnya, moderat itu berpikiran terbuka, kritis, menghormati semua orang, bermoral, beramar ma’ruf nahi mungkar (QS. 5: 48, 3:110), tidak ada intimidasi dan kekerasan.
Lalu untuk mengelola situasi keagamaan yang beragam, Islam tak butuh moderasi. Sebab berabad lamanya Islam telah miliki solusi yang terbukti efektif untuk bisa hidup berdampingan dengan penganut agama yang berbeda.
Kita hanya butuh memahami batas-batas tolerasi, menjalankan kewajiban antarsesama manusia, dan memastikan hak masing-masing terjaga. Tidak ada kekerasan, tidak pula saling meleburkan, karena kira punya pegangan; lakum dînukum waliyadîn (bagimu agamamu, bagiku agamaku, dalam Surat al-Kafirun:6).
Justru tidak masuk akal jika ide dasar moderasi untuk mencari persamaan dan menghapus perbedaan. Sebab jika pembawa misi moderasi beragama sejak awal menyadari bahwa keragaman adalah niscaya, maka perbedaan sudah barang tentu menyertainya.
Dengan ini, mencari titik persamaan tak lain hanyalah perjuangan yang sia-sia. Memang sejak awal, rencana moderasi beragama sudah bisa dipatahkan dengan sendirinya.
Hanya saja para pembawa misi tak pernah berhenti mencari cara. Artinya kita perlu terus waspada agar tidak salah dalam berpikir dan bertindak.
Pengarus utamaan moderasi Islam yang mereka disebut “Islam Moderat” nampaknya lebih banyak merujuk kepada prinsip-prinsip liberal bukan wasathiyah. Bagi Barat Syariah itu tidak moderat, karena dalam perspektif Barat hanya percaya demokrasi, toleransi, pendekatan politik tanpa kekerasan, perlakuan yang sama terhadap wanita dalam hukum dianggap moderat.
Muslim moderat menurut pandangan Barat adalah mereka yang memiliki ciri-ciri; tidak anti-semith (tidak anti-Yahudi), kritis terhadap Islam sendiri, menganggap Nabi Muhammad tidak mulia, pro kesetaraan gender, menentang jihad, menentang kekuasaan Islam, pro pemerintahan sekuler, pro-Israel, pro-kesamaan agama-agama, anti-pakaian Muslim, anti-jilbab, anti-syariah dan anti-terorisme. Jika memenuhi hal ini, berate moderat menurut Barat.
Kesimpulannya, moderat dalam pikiran Barat itu identik dengan liberal. Sehingga tidak sama dengan wasathiyah.*
“Disadari atau tidak, sebenarnya moderasi Islam adalah wajah lain dari liberalisasi Islam agar kaum Muslimin tidak terikat syariat Islam secara kaffah sehingga cara berpikirnya lebih sesuai dengan pandangan Barat kolonial, ketimbang pandangan Islam,” demikian penjelasan Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi. (Tabloid Media Umat Edisi 270).*
Alumnus PKU UNIDA Gontor Angkatan XIV