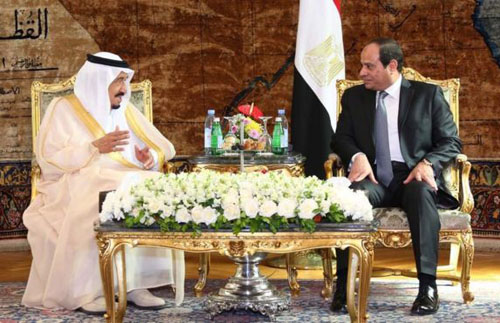Hidayatullah.com–Sabtu, 20 Maret 2004. Genap setahun Amerika Serikat melaksanakan keputusannya menyerang Irak secara sepihak. Setahun lalu Presiden AS George Walker Bush dengan lantang mengatakan, keputusannya ini akan membawa angin baru yang lebih segar di Timur Tengah. Yaitu, demokratisasi dan perdamaian.
Seperti yang telah dilakukan di Afganistan, AS pun akan membawa era demokratisasi di Iraq. Selanjutnya, Bush berharap AS akan segera dikenang sebagai “liberator” atau negeri pembebas. Untuk memperingati hari “bersejarah” itu, Presiden Bush mengadakan pidato khusus. Lebih dari itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Colin Powell mengadakan kunjungan luar biasa ke Iraq untuk memperingati acara tersebut.
Sayang, janji tinggal janji. Setahun setelah itu tak satu pun janji AS yang menjadi kenyataan. Iraq, di masa kini, justru jauh lebih tidak aman. Hampir setiap hari pasukan koalisi pimpinan AS mendapat ratusan kali serangan. Ledakan bom hampir setiap hari terjadi.
Hingga kemarin harian Washington Post mengatakan, jumlah korban tewas mencapai 574 tentara AS dan 100 tentara lain. Sedangkan tentara Iraq yang tewas diperkirakan mencapai 6.400 personel. Namun, jumlah itu masih belum seberapa dibanding dengan jumlah rakyat sipil Iraq yang tewas. Diperkirakan, setahun ini Iraq kehilangan 8.581 hingga 10.430 warga.
Citra AS sebagai negara demokratis dengan kehidupan pers yang bebas pun tumbang. Kamis (18/4) malam CNN melaporkan tentara AS menembak dua wartawan televisi Al-Arabiya. Pantauan Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), pada nulan April, menunjukkan, setidaknya 12 wartawan dari seluruh dunia tewas ketika meliput di Iraq. Jumlah itu masih ditambah dua orang yang dinyatakan hilang.
Kondisi itu tidak hanya memicu pesimisme, namun juga hilangnya kepercayaan kepada Presiden AS Bush dan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair. Terutama setelah masalah senjata pemusnah massal yang dijadikan alasan utama serangan ke Iraq terbukti tidak ditemukan. Bahkan hingga saat ini!
Maka tidak mengherankan jika Ketua Tim Inspeksi Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Hans Blix pun berkomentar keras. “Faktanya, Perang Iraq yang dilakukan AS setelah terjadi tragedi 11 September (2001) belum berhasil mengakhiri masalah terorisme dunia,” kata Hans Blix suatu ketika.
“Dunia tidak lebih aman, bahkan setelah Saddam Hussein terguling dari kekuasaannya. Dan semakin jelas, sejak 10 bulan lalu kita semua tahu tidak pernah ada yang namanya senjata pemusnah massal,” tegas Blix. Jauh sebelum AS secara unilateral memutuskan invasi ke Iraq, Hans Blix telah berulang kali melaporkan kenyataan bahwa Iraq tidak lagi memiliki senjata pemusnah massal seperti dituduhkan AS.
“Iraq, kenyataannya telah menumbuhkan lebih banyak terorisme dan kebencian kepada Dunia Barat. Perlucutan senjata lewat perang dan dengan alasan demokratisasi merupakan hal yang sulit dicapai,” tegas Blix.
Kalimat Blix terucap tak lama setelah terjadi ledakan bom di Madrid, Spanyol, yang menewaskan 200 orang dan melukai sekitar 1.500 warga lain. Di bawah kepemimpinan PM Jose Maria Aznar, Spanyol termasuk salah satu sekutu terkuat AS, setelah Inggris.
Pesimisme itu bahkan telah merembet ke Dewan Urusan Hubungan Luar Negeri AS, yaitu salah satu Satuan Tugas yang dibentuk oleh mantan Menteri Pertahanan dan Energi AS James R Schlesinger dan mantan Duta Besar AS di PBB Thomas Pickering.
Dalam laporan berjudul “Iraq: One Year After”, mereka menyimpulkan, tentara koalisi tidak mampu menjamin keamanan lingkungan di wilayah kritis Irak. “Kurangnya jaminan keamanan ini telah memicu kekhawatiran besar di kalangan rakyat Irak,” kata laporan tersebut.
Pendapat itu diperkuat Kenneth Pollack, Direktur Penelitian dari Brookings Institution’s Saban Center yang juga mantan anggota Dewan Keamanan Nasional AS di era Presiden Bill Clinton hingga Bush. “Iraq yang meletakkan harapan terlalu tinggi kepada AS akhirnya harus kecewa,” ujarnya.
Salah satu polling versi ABC News pekan ini menyebutkan, 42 persen rakyat Iraq dan 33 persen warga Arab-Iraq merasa terbebaskan. Namun, 41 persen Iraq dan 48 persen Arab-Iraq merasa dipermalukan. Sedangkan, 51 persen menentang tegas keberadaan tentara AS di Iraq.
*** SELURUH gambaran itu lalu membawa pada satu pertanyaan. Mampukah Irak melaksanakan transformasi kekuasaan dari AS kepada pemerintah sipil, 30 Juni nanti?
Patrick Basham dari Pusat Perwakilan pemerintahan di Institut Ceto, Washington, juga mengaku pesimis. “Mampukah Irak berpindah dari diktator ke demokrasi dengan mulus?” katanya seperti dikutip BBC News. Menurut dia, Gedung Putih akan menuai kekecewaan yang cukup besar. Terutama dalam mencapai cita-cita menerapkan demokrasi yang liberal di Iraq.
Barry Buzan, Profesor Pusat Pengkajian Internasional di London School of Economics dan Direktur Peace Institute di Copenhagen, Denmark, memperjelas masalah itu. Katanya, Irak terdiri dari berbagai unsur, yaitu Syiah, Suni, dan Kurdi yang saling bersaing. “Bagaimana demokrasi itu bisa tumbuh selama mereka sendiri masih bersaing?” ujarnya. Ya, bagaimana? (AP/kcm)