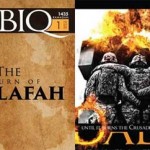Hidayatullah.com–Para pakar di Perserikatan Bangsa-Bangsa menuding pejabat senior militer dan intelijen Mali dengan sengaja menghalangi pelaksanaan kesepakatan damai 2015, yang aslinya dirancang untuk mengurangi kekerasan bersenjata di negara Afrika yang porak-poranda akibat perang berkepanjangan itu.
Hal tersebut terungkap dalam sebuah laporan ahli yang diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB pada 7 Agustus, yang salinannya diperoleh kantor berita AFP.
Mali sekarang ini sedang dalam perselisihan politik antara Presiden Ibrahim Boubacar Keita dan gerakan oposisi yang menuntut pengunduran dirinya, yang menuding presiden tidak sanggup mengatasi konflik bersenjata di negaranya.
Namun, hal yang paling membuat marah rakyat di negara miskin itu adalah kebrutalan 8 tahun konflik bersenjata yang bermula di bagian utara, yang entah kapan akan berakhir.
Pemberontak dari etnis Tuareg menguasai sebagian besar wilayah utara pada tahun 2012, menyulut perang yang sejak itu diambil alih oleh kelompok Muslim bersenjata dan meluas ke bagian tengah. Akibatnya, ribuan orang warga sipil dan tentara kehilangan nyawa.
Namun, menurut laporan PBB, para pejabat senior keamanan di negara itu justru yang mengancam dan menunda-nunda kesepakatan perdamaian penting, yang menurut banyak kalangan merupakan satu dari segelintir cara untuk mengeluarkan Mali dari lingkaran setan konflik berkepanjangan.
Diupayakan di ibu kota Aljazair, Aljiers, pada tahun 2015, kesepakatan antara pemerintah Mali dan beberapa kelompok bersenjata menyepakati kemungkinan para pemberontak untuk bergabung lagi dengan tentara nasional Mali. Kesepakatan itu juga menyetujui sejumlah hal lainnya.
Namun, implementasinya senantiasa ditunda, meskipun ada tekanan internasional agar segera dilaksanakan sepenuhnya.
Laporan PBB itu menyebut soal “ketidakpercayaan, beban dan kebingungan” yang disebabkan oleh tidak sejalannya antara ucapan dan tindakan pemerintah.
Para pakar PBB menyebut nama mantan kepala staf Angkatan Darat, Keba Sangare, sebagai salah satu orang yang membuat kesepakatan itu tidak diimplementasikan. Terutama karena ketidakbecusannya dalam mengatur penugasan tentara.
Kesepakatan Aljazair 2015 memberikan kesempatan pasukan Mali untuk kembali menguasai kota-kota di bagian utara. Dengan catatan pasukan itu terdiri dari batalion campuran tentara reguler, bekas pemberontak dan anggota milisi pro-pemerintah.
Akan tetapi dalam prosesnya sampai tahun lalu, sebagian bekas anggota pemberontak tidak kunjung dimasukkan dalam unit pasukan “gado-gado” tersebut, dan sebagian lain justru salah ditugaskan ke bagian selatan Mali sehingga terjadi keruwetan dan penundaan berbulan-bulan.
Tidak hanya itu, militer Mali tidak memberikan sekelompok prajurit kendaraan transportasi yang mereka butuhkan ketika ditugaskan di bagian utara pada September tahun lalu, sehingga menimbulkan risiko besar bagi prajurit-prajurit itu.
Dua puluh orang dari mereka diculik ketika menumpang bus umum dan lainnya masih dinyatakan hilang. Empat prajurit ditahan oleh tentara negara tetangga Burkina Faso, tetapi dilepaskan tahun ini.
“Penculikan dan penahanan … mengungkap awal dari kesalahan-kesalahan rencana pemerintah dan taktik penundaan,” kata laporan pakar PBB itu seperti dikutip AFP Jumat (14/8/2020).
Sangare dipecat setelah gagal menghentikan pembantaian di Ogossagou, sebuah desa etnis Fulani di bagian tengah Mali, pada 14 Februari.
Padahal desa itu sudah menjadi target pada Maret 2019, ketika 160 orang dibunuh dalam serangan yang dicurigai bermotif kebencian etnis.
Tentara Mali dikerahkan ke desa itu setelah pembantaian pertama. Namun, mereka meninggalkan daerah tersebut beberapa jam sebelum serangan bulan Februari itu terjadi.
Pasukan pengganti baru tiba di lokasi setelah sekitar 35 warga desa dibantai.
Laporan PBB itu mengatakan Sangare, yang kala itu komandan tentara di wilayah bagian tengah Mali,sebenarnya sudah berulang kali menerima banyak laporan tentang ancaman terhadap desa-desa di wilayah kerjanya.
Dia juga disebut membuat jaminan palsu kepada atasannya bahwa pasukannya tidak akan meninggalkan lokasi sebelum pasukan pengganti datang.
Bukan hanya petinggi militer yang sengaja mengacaukan upaya perdamaian di Mali. Pejabat intelijen negara tersebut juga menjadi biang kerok.
Pakar-pakar PBB mengatakan dinas intelijen Mali ikut andil dalam memperlemah kesepakatan damai 2015.
Dalam laporan mereka disebutkan bahwa intelijen Mali membayar sejumlah individu yang kebanyakan tergabung dalam kelompok aliansi bersenjata Tuareg, yang ikut menandatangani kesepakatan damai, untuk mendirikan kelompok sempalan.
Intelijen Mali sengaja menimbulkan perpecahan internal di kalangan kelompok-kelompok utama penandatangan kesepakatan damai Aljiers 2015, aliansi kelompok bersenjata yang dikenal dengan nama Platform, menurut laporan pakar PBB itu.
Presiden Keita, yang pertama kali naik ke puncak kekuasaan pada 2013, mendapat tekanan agar segera menyudahi konflik berdarah di negaranya.
Hari Selasa, ribuan orang turun ke jalan-jalan di ibu kota Bamako untuk menuntut pengunduran dirinya.*