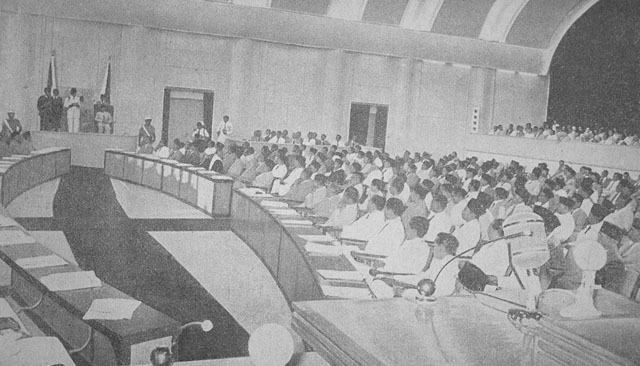Pada tanggal 3 Mei 2005, Salahuddin Wahid, ketua Majelis Pengurus Pusat ICMI, menulis sebuah artikel di Harian Republika berjudul “Pernikahan: Hukum Agama Vs Hukum Negara”. Artikel itu menanggapi tulisan saya tanggal 14 April 2005 di harian yang sama yang berjudul “Pernikahan Lintas Agama.”
Dalam tulisan tersebut, saya memang menanggapi tulisan Salahuddin Wahid berjudul “Perkawinan, Agama dan Negara” muncul di Republika (1/4). Ketika tulisan itu muncul, saya bersama-sama dengan teman-teman INSISTS sedang melakukan workshop di beberapa kota di Jawa. Karena yang menulis Salahuddin Wahid, yang saya kenal lama, maka saya merasa tidak perlu membacanya sampai detail. Selama ini, Salahuddin yang sering disapa Gus Solah, rajin mengkritik ide-ide sekularisme, termasuk ide-ide sekuler kakaknya sendiri, Abdurrahman Wahid. Dulu, saya sering bertemu dan berdiskusi dengan beliau, dan secara paralel melakukan kritik-kritik terhadap gagasan sekularisme.
Saya baru merasa ada yang aneh, ketika dalam perjalanan ke Yogyakarta, saya singgah di kantor hidayatullah.com di Surabaya, dan membuka-buka email. Ternyata, ada seseorang yang men-forward tulisan Gus Solah itu ke email saya. Setelah saya cermati, saya cukup terkejut. Karena waktunya sempit, saya hanya menfokuskan pada satu hal, yaitu masalah pernikahan lintas agama, khususnya antara muslimah dengan laki-laki kafir (non-Muslim).
Pada artikel 1 April 2005, Gus Solah menulis: “Isu itu (pernikahan antar agama. Pen.) telah lama menjadi bahan perdebatan dalam sejarah Islam. Pada prinsipnya pandangan para ulama terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, melarang secara mutlak pernikahan antara Muslim dan non-Muslim baik yang tergolong musyrik maupun ahlul kitab. Larangan itu juga berlaku bagi perempuan maupun lelaki. Kedua, membolehkan secara bersyarat. Sejumlah ulama membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-Muslim dari kelompok ahlul kitab. Tetapi perempuan Muslim tidak boleh menikah dengan lelaki non-Muslim walaupun tergolong ahlul kitab. Pendapat ketiga, membolehkan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim yang berlaku untuk perempuan dan lelaki Muslim.
Sejauh pengamatan saya, di Indonesia mayoritas termasuk kedalam kelompok kedua.”
Gus Solah tidak menyebutkan sumber tulisannya, dan saya menduga kuat, ia tidak melakukan riset sendiri tentang masalah ini. Belakangan, saya menemukan, ternyata Ketua ICMI ini menjiplak kategorisasi yang dibuat Musdah Mulia dalam bukunya “Muslimah Reformis” (2005, hal. 57).
Yang saya persoalkan dalam artikel 14 April lalu adalah kategorisasi ketiga, yaitu bahwa di kalangan ulama ada yang membolehkan perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Gus Solah tidak menunjukkan, siapa ulama yang membolehkan hal itu. Ia juga tidak menilai, sejauh mana validitas dan kekuatan argumentasinya. Sebagai cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari dan sempat menjadi ketua NU, harusnya Gus Solah merujuk kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jika dia cermat, maka dia akan tahu, bahwa memang tidak pernah ada perbedaan di antara ulama dalam masalah ini. Yang sejak lama menjadi ajang perdebatan adalah boleh atau tidaknya laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab (Yahudi dan Kristen).
Gus Solah sendiri mengaku berpendapat bahwa muslimah haram menikah dengan laki-laki non-Muslim. Dia menulis: “Secara pribadi saya mengikuti pendapat bahwa menurut syariat Islam, Muslimah tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim. Tetapi saya tidak setuju jika hukum negara secara eksplisit mengizinkan pernikahan semacam itu atau secara eksplisit melarangnya. Itu adalah wilayah hukum Islam yang mengandung perbedaan pendapat di antara umat Islam dan negara tidak perlu terlibat di dalamnya.”
Itulah anehnya pendapat tokoh cendekiawan Muslim ini. Gus Solah tetap ngotot bahwa dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, tanpa menunjukkan, siapa ulama yang membolehkan pernikahan semacam itu. Kalau soal beda pendapat, dalam semua masalah juga ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Hingga kini, banyak umat Islam yang mendukung pelacuran, perjudian, korupsi, dan sebagainya. Seorang cendekiawan Muslim, apalagi yang memimpin para cendekiawan Muslim, seyogyanya tidak boleh berpendapat seperti itu. Hanya karena melihat ada perbedaan pendapat, lalu perbedaan itu diterima sebagai fakta, tanpa menguji keabsahan perbedaan pendapat itu.
Islam sangat menghargai perbedaan. Tetapi, perlu dijelaskan, perbedaan itu terjadi dalam hal apa? Apakah perbedaan itu di lapangan al-shawab wal khatha’ atau di lapangan al-haq wal bathil? Apakah perbedaan dalam masalah dzanni atau dalam soal qath’iy.
Cendekiawan Muslim harusnya mengklirifikasi masalah ini, sebelum melontarkan pendapatnya ke masyarakat. Perbedaan ijtihad di kalangan mujtahidin dalam soal-soal furuiyyah adalah rahmat. Tetapi, pendapat Aminah Wadud yang membolehkan wanita menjadi imam dan khathib salat Jumat di Gereja – dengan jamaah yang bercampur aduk antara laki-laki dan wanita dan sebagian wanita salat dengan tidak memakai jilbab – tidak termasuk hal yang rahmat. Meskipun Wadud adalah seorang profesor, tetapi pendapatnya ini keluar dari metodologi fiqih Islam.
Cendekiawan Muslim, baik ICMI atau bukan, tentu bisa menilai bahwa pendapat Kiai Roy yang membolehkan salat dalam bahasa Indonesia bukanlah rahmat. Pendapat Kemal Ataturk yang mengubah azan dalam bahasa Turki pun tidak patut diterima. Ketika ribut-ribut goyang ngebor Inul, ada juga kyai yang mendukung pertunjukan tarian erotis arsi dangdut asal Pasuruan dan meminta agar pertunjukan itu jalan terus. Apakah gara-gara pendapat sang kyai itu juga menjadi rahmat, sehingga negara tidak boleh campur tangan? Ketika ribut-ribut masalah undian olah raga Porkas dan SDSB, ada juga ulama yang berpendapat bahwa Porkas danb SDSB bukanlah judi. Apakah hanya karena ada pendapat ‘minoritas’ ulama yang mendukung Porkas dan SDSB, lalu negara tidak boleh melarang SDSB?
Apakah karena ada Prof Wadud yang membolehkan wanita salat tanpa menutup aurat lalu hal itu menjadi halal? Imam Al-Syathibi dalam Kitab terkenalnya, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah (ed. Muhd. Abd al-Qadir al-Fadili, 4:84), mencatat, bahwa “perbedaan dalam satu masalah, tidak menjadi hujah untuk memperbolehkannya”. (al-khilaf fi al-masail laysa hujaj al-ibahah).
Selain tetap ngotot bahwa dalam masalah perkawinan muslimah dengan laki-laki kafir terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, dalam artikel 3 Mei itu, Gus Solah, juga menegaskan, bahwa negara tidak patut melarang perkawinan Muslimah dengan pria non-Muslim dan harus menghormati pendapat minoritas umat Islam yang memperbolehkan pernikahan semacam itu, dengan cara memberikan kesempatan untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Catatan Sipil supaya pernikahan mereka sah menurut negara.
Kata Gus Solah: “Tetapi negara harus menghormati pendapat minoritas umat Islam yang memperbolehkan pernikahan semacam itu, dengan cara memberikan kesempatan untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Catatan Sipil supaya pernikahan mereka sah menurut negara. Untuk bisa melakukan itu tampaknya kita harus menunggu lahirnya UU Catatan Sipil yang mengatur keharusan untuk mencatat atau mendaftar semua pernikahan di Indonesia.”
Inilah ide berbahaya dari Ketua ICMI ini. Hanya gara-gara ada pendapat minoritas umat Islam yang membolehkan praktik perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki kafir, maka negara dimintanya untuk mengesahkan perkawinan semacam itu. Sementara itu, dia sendiri mengaku tidak setuju dengan pendapat tersebut, dan menyatakan, bahwa perkawinan itu adalah haram.
Bukankah ini cara berpikir yang paradoks? Bukankah itu sama saja, dia meminta agar negara juga mengesahkan hal yang haram: seperti perkawinan homoseksual, perjudian, korupsi, dan sebagainya. Jika dia berpikir konsisten, bahwa perkawinan antara muslimah dan laki-laki kafir adalah salah, maka harusnya dia juga mendukung pelarangannya oleh negara. Bukan malah meminta negara mengesahkannya.
Sang Ketua ICMI mestinya menguji dulu, apakah pendapat yang membolehkan wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir itu, merupakan ide yang layak dipertimbangkan atau tidak dalam kajian bidang hukum Islam. Sebagai contoh, berikut ini argumentasi Musdah Mulia yang menyatakan, bahwa larangan perkawinan antara Muslimah dengan laki-laki non-Muslim sebagaimana disebutkan dalam QS Mumtahanah ayat 10 sudah tidak berlaku lagi.
Di tulis dalam buku Musdah Mulia itu: “Jika kita memahami konteks waktu turunnya ayat itu, larangan ini sangat wajar mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi dan pengikutnya. Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum Mukmin dan kaum kafir. Larangan melanggengkan hubungan dimaksudkan agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh dan mana kawan. Karena itu, ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, maka larangan dimaksud tercabut dengan dengan sendirinya.” (hal. 63).
Argumentasi “kontekstual” itu sangatlah lemah dan keliru. Dengan logika semacam itu, maka ketika damai, seorang Muslimah halal menikah dengan laki-laki kafir. Lalu, ketika perang, nikahnya jadi haram. Dan jika damai lagi, maka nikahnya halal lagi. Dengan logika itu, maka ketika meletus konflik islam-Kristen di Maluku, perkawinan Yuni Shara dengan Henry Siahaan haram. Lalu, setelah damai, perkawinan itu jadi halal lagi. Apakah pendapat seperti ini – meskipun dikeluarkan seorang profesor– bertanggung jawab dan valid? Jelas tidak.
Sepanjang sejarah Islam, banyak kondisi dimana kaum Muslim tidak berperang dengan kaum kafir. Bahkan, selama 1200 tahun lebih, kaum Yahudi hidup damai di dalam wilayah Islam. Tetapi, selama itu pula para ulama tidak pernah berpikir, bahwa muslimah halal menikah dengan laki-laki Yahudi. Para Imam mazhab juga merumuskan pendapatnya di zaman damai. Mereka tidak berpendapat seperti Musdah Mulia ini.
Sebagai Muslim, kita mestinya bersyukur jika negara juga melarang hal-hal yang haram dalam Islam, seperti negara melarang pembunuhan, korupsi, mencuri, pornografi, perzinahan, perkawinan homoseksual, perusakan lingkungan, dan sebagainya. Karena kita yakin bahwa perkawinan antara muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah haram dan munkar, maka sebagai konsekuensi dari iman kita, kita harus mendukung, jika negara juga melarang perkawinan semacam itu. Sebab, adalah aneh dan ajaib, jika kita berpendapat ‘kumpul kebo’ adalah haram, lalu kita justru mendukung negara kita mengesahkan praktik ‘kumpul kebo’. Na’udzubillahi min dzalika.
Semoga para cendekiawan Muslim kita tidak bersikap sembrono dalam masalah ajaran Islam. Jika tidak mengerti masalah hukum Islam, sebaiknya kita kembali kepada para ulama kita yang salih dan alim. Tugas cendekiawan adalah menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Cendekiawan Muslim sejatinya adalah ulama. Di pundak merekalah amanah risalah dibebankan, sebab mereka adalah “pewaris para Nabi”.
Jika para cendekiawan ini bersikap sembrono – apalagi dalam hukum agama – maka merekalah yang akan pertama kali diminta pertanggungjawaban di Hari Akhirat. Di dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, Imam al-Ghazali mengutip ucapan Muadz bin Jabal r.a., “Hati-hatilah terhadap tergelincirnya orang alim karena ia besar nilainya di mata makhluk, lalu mereka mengikutinya atas ketergelinciran itu.”
Sayyidina Umar r.a. juga menyatakan, “Tiga hal yang dengannya robohlah zaman. Salah satunya ialah tergelincirnya orang alim.” Semoga hal ini menjadi i’tibar bagi kita semua. Wallahu a’lam. (Jakarta, 6 Mei 2005).