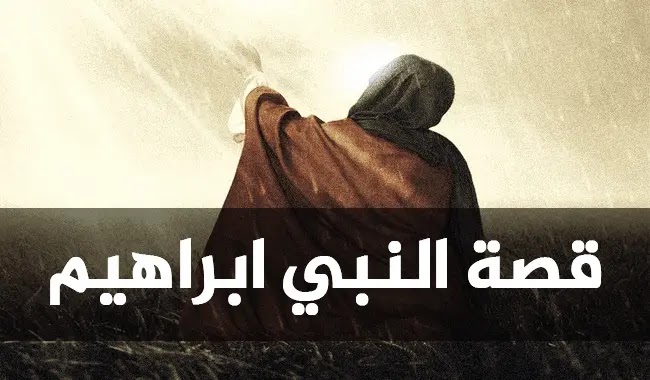Oleh: Mohammad Fauzil Adhim
Hidayatullah.com | Justru seharusnya, anak-anak memasuki masa remaja tanpa krisis identitas. Tidak perlu mengalami badai dan guncangan sebagaimana diyakini oleh sebagian psikolog.
Penelitian psikologi sendiri sebagaimana –misalnya– ditunjukkan oleh Offer D and Schonert-Reichl KA (1992) dalam laporan bertajuk Debunking the Myths of Adolescence: Findings from Recent Research menegaskan bahwa hanya 20% remaja yang mengalami krisis identitas. Mayoritas memasuki masa remaja dan melewatinya tanpa mengalami krisis.
Hasil riset yang dimuat dalam Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (Desember 1992) ini menegaskan kembali pendapat maupun hasil-hasil penelitian terdahulu bahwa krisis identitas sebagai fase yang harus dilalui oleh para remaja merupakan mitos belaka. Tetapi akibat meyakini mitos ini, begitu banyak pendidik yang melonggarkan nilai-nilai (loosening values). Padahal tidak adanya keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai itulah justru penyebab krisis. Semakin kuat pegangan seorang remaja kepada nilai keimanan sehingga membangkitkan idealisme dalam dirinya, maka semakin jauh dari krisis identitas.
Masalah krisis identitas yang seolah wajib dialami para remaja ini semakin tidak menemukan tempatnya apabila kita menyandarkan diri pada tuntunan Islam. Tidak kita temukan nash yang tegas menyatakan remaja sebagai masa keguncangan dan kekacauan identitas diri. Tidak pula kita temukan contohnya pada generasi Sahabat, tabi’in, tabi’ut-tabi’in, hingga generasi sesudahnya.
Sebaliknya, mereka justru menjadi para pemuda generasi terbaik. Usia masih sangat muda, tetapi telah matang kepribadiannya, sehat mentalnya, dan memiliki kemampuan berpikir yang mendalam dengan berpijak pada tuntunan agama yang sempurna.
Mitos krisis identitas pada remaja bermula dari buku tulisan Granville Stanley Hall berjudul Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Physiology, Anthropology, Sex, Crime, Religion, and Education (1904). Psikolog Zionis sekaligus pendiri APA (American Psychological Association) ini menyatakan bahwa keguncangan dan badai (storm and stress) merupakan ciri khas yang pasti dialami oleh setiap remaja. Mereka sedang mengalami krisis identitas. Inilah masa ketika remaja meragukan agamanya. Meninggalkan agama (murtad) merupakan hal yang normatif alias sangat wajar terjadi.
Hall menyarankan agar remaja tidak disibukkan dengan tanggung jawab pekerjaan. Remaja sebaiknya diarahkan agar hanya sibuk belajar di bangku sekolah. Anehnya, saran Hall ini justru bertentangan dengan hasil risetnya sendiri.
Hasil riset Hall menunjukkan bahwa remaja yang mengalami krisis kurang dari 20%. Hanya saja, Hall menguasai publikasi sehingga asumsi-asumsinya diterima sebagai teori psikologi yang dianggap 100% benar.
Apa yang terjadi jika kita mempercayai asumsi Hall? Menganggap wajar tingkah laku buruk remaja dan tidak mencegahnya karena merupakan hal yang lumrah. Mereka masih mencari jatidiri sehingga kenakalan dan tingkah laku yang melanggar norma ditoleransi bahkan dianggap sebagai hal yang seharusnya terjadi untuk mencapai kematangan diri. Seolah tanpa adanya berbagai tingkah laku tersebut mereka tidak akan berkembang menjadi remaja yang unggul, mandiri, dan memiliki sikap yang kokoh.
Begitu besarnya pengaruh Hall sampai-sampai di dunia Arab pun muncul istilah muraahiq. Akar kata ra-ha-qa, jelas Abdul Aziz an-Naghaimsyi, bermakna bodoh, dungu, tergesa-gesa, dan melakukan kejahatan.
Istilah yang berkonotasi buruk tersebut pada gilirannya menggantikan istilah syabab (pemuda) yang dipergunakan dalam hadits Nabi SAW. Padahal kata syabab lebih bermakna positif. Di dalamnya terkandung pengertian tawaqqud (menyala-nyala) untuk menunjukkan semangat yang berkobar-kobar dalam memperjuangkan idealisme dan meraih apa yang menjadi cita-citanya.
Bermula dari pergeseran istilah syabab menjadi muraahiq, banyak perubahan sikap terjadi dalam menghadapi masa yang sangat strategis ini. Para guru maupun orangtua yang seharusnya sigap jika menjumpai keanehan cara berpikir maupun keyakinan anak, menjadi kendor karena menganggap sebagai tahap perkembangan yang wajar. Gejolak anak, dan bukannya semangat yang meluap untuk bersungguh-sungguh (hirsh), ditanggapi sebagai kewajaran yang sudah seharusnya terjadi.
Kita menjadi lalai menyiapkan anak untuk segera meraih masa dewasa, siap bertanggung jawab di usianya yang belia. Padahal semestinya, jikapun kita masih terus membantu mereka, anak-anak itu sudah memiliki kesadaran tentang tanggung jawab dan mampu mengelola dirinya.
‘Aqil Baligh Itu Proses’
Salah tugas penting yang perlu direnungkan adalah mempersiapkan anak-anak kita mampu menjadi mukallaf begitu mereka mendapati tanda-tandanya. Salah satu yang seharusnya melekat pada setiap mukallaf adalah akalnya telah sampai (‘aqil balligh). Yakni mereka memiliki kecakapan berpikir yang matang berdasarkan acuan shahih dalam agama ini.
Kecakapan untuk menakar menimbang itu beriring dengan kematangan mental. Sesungguhnya akal bukan hanya berkait dengan rasio. Jauh lebih dari itu. Dan ini seharusnya terjadi beriringan dengan datangnya kemasakan seksual yang ditandai dengan haid untuk pertama kali bagi perempuan dan ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki.
Salah satu tanda tercapainya ‘aqil baligh adalah adanya sifat rasyid yang dicirikan oleh kemampuan membelanjakan harta (tasharruf) dengan baik dan bertanggung jawab. Ini semua memerlukan proses pendidikan dan pendampingan. Tidak datang dengan tiba-tiba.
Anak akan belajar meraih kematangan berpikir melalui proses latihan dan terus-menerus mengilmui disertai latihan. Sekadar berpengetahuan banyak tidak menjadikan anak mampu berpikir secara terarah dan tertata.
Sebelum datangnya kemasakan seksual, seharusnya anak kita telah menjadi mumayyiz di usia 6 atau 7 tahun. Inilah masa ketika anak-anak mulai kita kenalkan dan ajari bebanan ibadah. Tetapi sebagaimana ‘aqil baligh, kemampuan untuk membedakan baik dan buruk serta benar dan salah dengan akalnya atau dikenal dengan istilah tamyiz perlu ditumbuhkan dan dibangun dengan sungguh-sungguh oleh orangtua maupun pendidik. Usia ini merupakan masa ketika anak memiliki potensi kuat untuk memiliki kemampuan tamyiz, tetapi ini semua perlu kita persiapkan.
Cukupkah itu? Tidak. Arah hidup mereka perlu kita bangun. Anak-anak harus memiliki idealisme, yakni seperangkat keyakinan yang membangkitkan keinginan untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak hanya memiliki banyak pengetahuan, maka krisis identitas di masa remaja masih mungkin akan terjadi.
Nah, sudahkah anak-anak kita siap mencapai ‘aqil baligh?*
Penulis buku ‘Mencari ketenangan di tengah kesibukan’ dan pengajar Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu’.