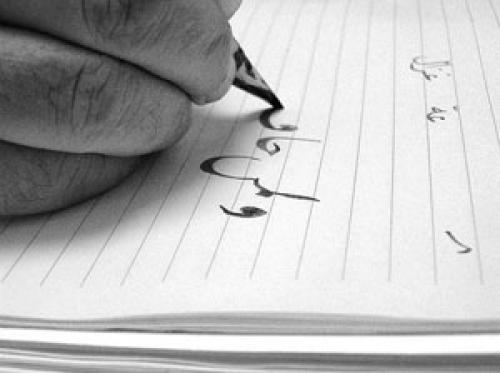Hidayatullah.com–Pada 8 April 2010, enam hari sebelum peristiwa Tanjung Priok berdarah pada 14 April 2010, Hidayatullah.com memuat tulisan saya dengan judul Dicari Sosok Ayah untuk Umat. Tesis tulisan tersebut adalah perlunya sebuah kekuatan “ayah” yang berfungsi melindungi, membimbing, memperkuat, dan mengarahkan gerak umat. Sebab realitasnya, umat memang tidak memiliki “ayah” sehingga mereka jatuh ke dalam keyatiman, gampang terurai (tidak solid), dan hanya menjadi lahan eksploitasi musuh-musuh.
Apa yang saya tulis tersebut, rupanya menemukan konfirmasinya pada peristiwa Tanjung Priok berdarah yang pecah beberapa hari kemudian. Tragedi tersebut, meskipun dalam lingkup kecil, jelas mencerminkan kosongnya kekuatan “ayah” pada masyarakat di sana.
Jika saja kekuatan “ayah” eksis di sana, tragedi tersebut akan dapat dikendalikan dengan mudah. Kalau pun tragedi tersebut harus pecah, jika ada kekuatan “ayah” yang memimpin, masyarakat akan menuai keuntungan politis jangka panjang. Misalnya, dengan darah yang telah ditumpahkan, semestinya terbayar dengan koreksi kebijakan dari para penggusur atau setidaknya posisi politis masyarakat di Tanjung Priok di hadapan penggusur meningkat. Kedua hal tersebut gagal diraih oleh masyarakat akibat kosongnya kekuatan “ayah” atau kepemimpinan masyarakat. Justru yang mengecewakan kemudian, di ujung konflik muncul pihak yang mengklaim diri sebagai ahli waris Mbah Priok.
Kemunculan pihak yang mengaku ahli waris tersebut jelas merugikan kepentingan politis masyarakat. Hemat saya, karena situs wali Allah tersebut telah berkembang menjadi milik publik, maka tidak ada lagi sebuah keluarga yang mengklaim paling berhak atasnya. Mbah Priok telah menjadi milik masyarakat. Munculnya perlawanan yang luas dari masyarakat tatkala situs tersebut hendak digusur, merefleksikan bahwa masyarakat merasa memiliki akan makam tersebut. Hal ini sama kasus makam Rasulullah, apakah hanya keturunannya saja yang berhak atasnya. Tentu tidak.
Bagi pemerintah yang terlibat konflik dengan masyarakat di sana, kemunculan pihak yang mengklaim diri sebagai ahli waris Mbah Priok itu tentu menguntungkan. Setidaknya untuk sementara kemarahan masyarakat di sana dapat diredam dengan dalih bahwa kini persoalan sedang dirundingkan antara pemerintah dengan pihak ahli waris. Masalahnya adalah, apakah pihak yang mengklaim ahli waris Mbah Priok tersebut tengah memperjuangkan aspirasi masyarakat atau aspirasinya sendiri. Sebab kemunculannya di ujung peristiwa tersebut seolah-olah mendadak dan menyodok di depan. Kalau saja sejak awal hingga pecahnya tragedi, keberadaan dan kepemimpinannya telah terlihat, tentu kita tidak akan mempertanyakan legitimasi politisnya.
Ternyata apa yang kita risaukan kemudian benar-benar terbukti. Jika sebelumnya pertentangan yang terjadi adalah antara masyarakat dengan Satpol PP sebagai kaki tangan pihak penggusur, kini dengan cerdik digeser menjadi pertentangan antara pihak ahli waris dengan PT. Pelindo. Sedangkan pihak penggusur (pemerintah), tiba-tiba mengambil lakon sebagai mediator. Tetapi dengan bodohnya pihak yang mengklaim ahli waris Mbah Priok tersebut menuruti tipu muslihat penggusur. Hasilnya ada sembilan poin yang tidak satu pun yang menguntungkan posisi politis masyarakat secara luas atau mengubah pola kebijakan pemerintah terhadap setiap areal yang memiliki hubungan ekonomis dan emosional yang kuat dengan masyarakat. Berikut sembilan poin kesepakatan di antara Pemprov DKI, PT Pelindo II, dan pihak ahli waris sebagaimana yang diberitakan media.
Pertama, Makam tetap di posisinya, tidak dibongkar ataupun dipindah.
Kedua, Pendapa Majelis Gapura dipindahkan posisinya agar Terminal Peti Kemas Koja berfungsi sesuai aturan dan standar internasional. Posisinya dibicarakan antara PT Pelindo dan ahli waris.
Ketiga, Sisa tanah akan dibicarakan antara ahli waris dan PT Pelindo.
Keempat, Kasus lapangan akan ditindaklanjuti secara hukum, siapa yang melanggar akan ditindak. Satpol PP sebagai organik Pemda merupakan tanggung jawab Pemda.
Kelima, Perlunya pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.
Keenam, PT Pelindo setuju untuk membuat MoU hitam di atas putih mengenai pembicaraan lebih lanjut dengan ahli waris.
Ketujuh, Administrasi kedua pihak supaya langsung dilakukan antara PT Pelindo II dan ahli waris dan ditembusi Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Kedelapan, Pemda dan PT Pelindo sebagai anak perusahaan BUMN akan memperhatikan siapa-siapa yang menjadi korban dalam kasus kemarin. Tidak hanya biaya rumah sakit, bahkan kalau perlu sampai berobat jalan.
Kesembilan, Pembahasan antara PT Pelindo dan ahli waris akan dibicarakan di kantor Komnas HAM.
Mencermati sembilan poin tersebut, persoalan telah direduksi menjadi masalah sengketa tanah antara pihak yang mengklaim diri sebagai ahli waris dengan PT. Pelindo, serta pihak-pihak terkait. Tidak terlihat muncul dalam poin-poin tersebut masalah penggusuran simbol-simbol dan kepentingan masyarakat di sana. Dalam hal ini, sudut pandang pihak penggusur telah memenangkan pertarungan. Andai saja yang mewakili kepentingan masyarakat tersebut bukan mereka yang yang mengklaim diri sebagai ahli waris tetapi figur yang memahami aspirasi dan berusaha memperjuangkannya, poinnya pasti tidak demikian.
Demikian jadinya jika kekuatan “ayah” kosong di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat selamanya termarginalkan dalam setiap pertarungan politis.
Menarik Pelajaran
Merenungkan tragedi tersebut, setidaknya kita dapat menarik beberapa poin berikut. Pertama, jiwa perlawanan kolektif masyarakat atas setiap kesewenang-wenangan ternyata belum pupus. Ini pertanda baik bagi setiap usaha transformasi yang membawa perubahan nasib masyarakat. Dan ini juga menjadi jawaban atas pandangan yang menyatakan bahwa masyarakat sekarang berada di puncak budaya konsumtif yang serba tidak peduli dan apatis. Ditengarai bahwa pandangan tersebut dilontarkan oleh salah seorang pemimpin di DPP Partai Demokrat.
Kedua, mengantisipasi tragedi akan berulang di kemudian hari yang tidak memberi dampak perbaikan posisi politis masyarakat akibat kosongnya kepemimpinan, sudah sebaiknya tokoh-tokoh masyarakat mencurahkan pikiran dan tenaganya terhadap masalah krusial ini. Mereka harus membangun kepemimpinan dan menyediakan kekuatan “ayah” bagi masyarakat. Hanya dengan itu masyarakat tidak terjebak pada tragedi-tragedi pilu yang tidak menghasilkan perubahan apa-apa. Cukuplah kiranya tragedi berdarah terjadi dua kali di Tanjung Priok (1984 dan 2010). [hidayatullah.com]
Penulis adalah Sekretaris Yayasan Bumi Ummah Center