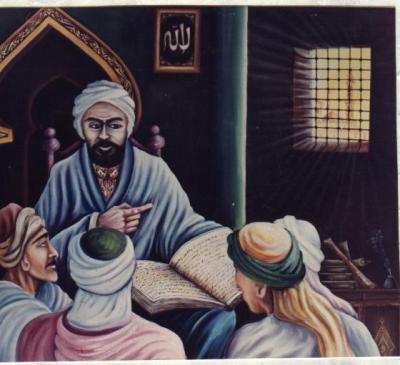Oleh: Fatih Madini
Hidayatullah.com | BEBERAPA saat yang lalu, pemerintah –melalui 3 menteri—mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait atribut dan seragam sekolah. Berikut enam keputusan utama penggunaan pakaian seragam di sekolah negeri yang telah diputuskan oleh tiga menteri tersebut:
- SKB 3 Menteri ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pemda).
- Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama. Seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
- Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
- Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak SKB 3 Menteri ini ditetapkan.
- Jika terjadi pelanggaran terhadap SKB 3 Menteri ini, maka saksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar:
- Pemda bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, atau tenaga kependidikan.
- Gubernur memberikan sanksi kepada bupati/wali kota.
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi kepada gubernur.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.
- Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.”
Baca: Ketua MUI Pusat: SKB Tiga Menteri Soal Atribut Keagamaan Wajib Ditinjau Ulang
*****
Kenapa ketika ada peraturan agama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari semacam pemakaian jilbab, dianggap melanggar HAM dan kebebasan manusia, sedangkan ketika ada pemaksaan untuk memakai helm, masker, menjaga jarak, dll tidak dianggap demikian? Kalau alasannya adalah karena kebebasan dan selama tidak menganggu orang lain, silakan saja diyakini dan dijalani. Namun keyakinan itu hanya cocok untuk kaum sekular, bukan untuk orang Islam.
Dalam pandangan Islam, hak yang paling utama untuk dipenuhi terlebih dahulu adalah hak Allah, salah satunya untuk dipatuhi segala perintahnya dan dijauhi segala larangannya. Tidak memakai jilbab memang tidak menganggu orang lain, tapi ia mengganggu dan melanggar aturan Tuhannya.
Bukannya hendak merendahkan nilai hasil cipta akal dan kesepakatan masyarakat. Hanya saja, Islam menuntut kita untuk mengutamakan dan mendahulukan nilai-nilai yang bersumber dari Wahyu. Lagipula, kalaupun dua nilai sebelumnya sesuai dengan Islam, dengan senang hati akan umat Islam jalankan.
Karena prinsip kita: “Islam tidak bersumber dari akal (namun wahyu) tapi tidak juga menafikan akal. Dan dalam Islam, wahyu di atas akal sehingga bisa selalu memandu akal. Kalau akal di atas wahyu, maka wahyu akan diakal-akalkan”
Tenang saja, nilai-nilai dalam Islam juga sudah sempurna dan universal sejak awal. Entah itu masalah relasi antara dirinya dengan Allah maupun orang lain, Islam sudah lebih dulu memberikan solusi dan nilai-nilai yang lengkap dan baku.
Soal toleransi antar umat beragama misalnya. Melalui wahyu (QS 2: 2, 22: 39-40, dan 109: 1-6) dan sejarahnya (sejak Nabi Muhammad ﷺ mendirikan negara Madinah bersama orang-orang Yahudi, penaklukkan Yerussalem tanpa darah oleh Umar bin Khattab, sampai perlindungan kekhalifahan Abbasiyah dan Turki ‘Utsmani kepada orang-orang Yahudi selama beratus-ratus tahun), umat Islam sudah lebih dulu menunjukkan betapa toleransinya mereka kepada kaum selain mereka.
Begitulah Islam memandang kemanusiaan. Berbeda dengan HAM, bukan berarti kita tidak manusiawi. Sebab bagi kita, antara hak Allah dan manusia, mestilah Allah didahulukan, Hak Allah adalah untuk dijadikan Tuhan satu-satunya dan disembah dengan cara yang dicontohkan Nabi Muhammad ﷺ, dan ditaati aturan, hukum, atau nilai-nilainya.
Baca: Untuk Siapakah HAM Hadir?
Maka bagi kita, yang pantas disebut manusiawi itu bukan hanya yang selalu menghormati perbedaan agama namun mengamini kebenaran semua agama atau yang melegalkan perkawinan sesama jenis, tapi orang yang secara konsisten menghargai dan menghormati segala perbedaan (khususnya agama), dengan tetap meyakini bahwa hanya agamanya yang benar, pernikahan lintas agam dan sesama jenis itu haram, dan murtad adalah Tindakan haram yang sangat jahat terhadap Allah.
Lagipula, sebagaimana ucapan Prof Dr al-Attas, kalau mau “fair”, kata “hak” itu sendiri berasal dari kosa kata Islam, “حق”, yang berarti benar. Tentu benar menurut Islam. Maka, “apakah hak itu bisa disebut hak kalau ia tidak benar menurut Islam?” Sehingga, dapatkah aktivitas membuka aurat disebut hak (suatu hal yang benar) dalam Islam?
Bahkan dalam penggunaan bahasa Arab dan peristilahan Islam, “hak” juga bermakna kewajiban, keperluan, tugas, sesuai dengan tabi’at, tidak bisa tidak ada dan lain-lain yang tentu saja dalam perspektif Islam:
“Kebenaran, ertinya sesuai yang benar yang sesuai dengan keperluan ilmu dan hikmat; dia juga sesuatu yang betul yang sesuai dengan keperluan keadilan (terletaknya segala sesuatu pada tempat yang tepat sesuai kehendak Allah); dan dia juga terbukti wujud tiada dapat tiada. Yang benar itu mewajibkan dia diakui kebenarannya; dan yang benar itu mewajibkan bagi pihaknya menyesuaikan kebenarannya dengan keperluan ilmu dan hikmat dan keadilan.” (Syed Muhammad Naquib al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin, 2001: 118-119).
Keterkaitan antara hamba dan Allah dalam seluruh aspek itulah yang juga tidak membebaskan manusia untuk berbuat apapun. Manusia hanya dibebaskan berbuat baik, sesuai perintah Allah. Itulah alasan mengapa konsep ikhtiar dikaitkan dengan akar katanya: “Khair” oleh Prof. Al-Attas dalam Prolegomena To The Metaphysics of Islam“-nya:
“The activity that is called ‘freedom’ is in ikhtiyar, which is an act, not in hurriyyah, which is a condition. The act that is meant in ikhtiyar is that of making a choice, not between many alternatives but between two alternatives: the good or the bad. Because ikhtiyar is bound in meaning with khayr, meaning ‘good’, being derived from the same root khaara (khayara), the choice that is meant in ikhtiyar is the choice of what is good, better, or best between the two alternatives. This point is most important as it is aligned to the philosophical question of freedom. A choice of what is bad of two alternatives is therefore not a choice, rather it is an act of injustice (zulm) done to oneself. Freedom is to act as one’s real and true nature demands—that is, as one’s haqq and one’s fitrah demands—and so only exercise of that choice which is of what is good can properly be called a ‘free choice’. A choice for the better is therefore an act of freedom, and it is also an act of justice (‘adl) done to oneself… whereas a choice for the worse is not a choice as it is grounded upon ignorance urged on by the instigation of the soul that inclines toward the blameworthy aspects of the animal power; it is then also not an exercise of freedom because freedom means precisely being free of domination by the powers of the soul that incites to evil.” (Syed Muhammad Naquib a-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam, 1995: 33).
Di sinilah Tuhan dan akhirat menduduki posisi yang sangat urgen dalam Islam, berbeda dengan sekularisme yang hanya fokus pada aspek keduaniaan semata.
Kalaupun sampai saat ini kita sebagai orang Islam masih merasa dipaksa oleh Allah dalam mentaati-Nya, menanrik kalam Dr. Adian Husaini bahwa, “Lebih baik saya dipaksa masuk Surga daripada dengan ikhlas masuk Neraka.” Lagipula, bukankah konsekuensi dari membaca dua kalimat syahadat adalah tunduk dan berserah diri kepada Allah?
Baca: Akhir Zaman, Ditandai Memburu Dunia dan Menjual Akhirat
Kalau saja Allah dan keselamatannya di dunia dan akhirat selalu ia kaitkan dalam memandang segala realitas dan kebenaran, maka ia akan dengan sukarela menutup aurat, shalat, puasa, zakat, dan syariat lainnya. Sebab akan timbul kesadaran dalam dirinya bahwa semua itu merupakan bentuk ibadah kepada-Nya dan syarat untuk bisa selamat di dunia dan akhirat.
Bahkan dalam pandangan Islam, alasan utama dan terkuat mengapa orang Islam mesti memenuhi hak sosialnya dengan mengikuti peraturan yang berkaitan dengan kehidupan sosial semacam memakai helm, memakai masker dan perbuatan baik pada umumnya (yang sesuai dengan Islam) pun adalah karena Allah, bukan supaya tidak mengganggu dan menyakiti orang lain.
Kurang lebih seperti ini: “Karena Allah memerintahkan saya untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, apapun suku, nasab, dan agamanya, dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan-Nya, dan demi mengharap ridha-Nya, maka saya pun berbuat demikian.”
Begitulah Islam memandang. Dan karena inilah, sebagaimana ucap al-Attas, dengan berasas pada perjanjian pribadi seluruh manusia dengan Allah di alam Azali (QS 3: 172), Islam hanya menerima konsep “individual contract” (yang berkaitan langsung dengan Tuhan dan universalitas nilai-nilai nya), bukan “social contract” (yang landasan utamanya bukan nilai-nilai wahyu, melainkan apa yang diproduksi oleh manusia). Lebih-lebih ketika nilai-nilai dalam Islam sudah sempurna dan universal sejak awal, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal.
“In the Islamic political and social organization—be it in one form or another—the same covenant (QS 3: 172) becomes their very foundation. The man of Islam is not bound by the social contract, nor does he espouse the doctrine of Social Contract. Indeed, though he lives and works within the bound of social polity and authority and contributes his share towards the social good, and though he behaves as if a social contract were in force, his is, nevertheless, and individual contract reflecting the Covenant his soul has sealed with God; for the Covenant is in reality made for each and every individual soul. The purpose and end of ethics in Islam is ultimately for the individual; what the man of Islam does here he does in the way he believes to be good only because God and His Messenger say so and he trusts that his actions will find favour with God.” (Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism, 1993: 74-75).
Islam, memandang manusia tidak lebih tinggi dari Tuhan, sehingga Tuhan jangan sampai dimanusiakan dan manusia jangan sampai dituhankan. Dan Islam memandang dunia tidak lebih tinggi dari akhirat, sehingga urusan yang berkaitan dengan akhirat mesti didahulukan dan diutamakan.
Tentu, seluruh pandangan yang dikemukakan di atas hanya untuk orang Islam. Adapun selainnya, tidak ada paksaan dari Islam. *
Mahasiswa STID Mohammad Natsir Jakarta