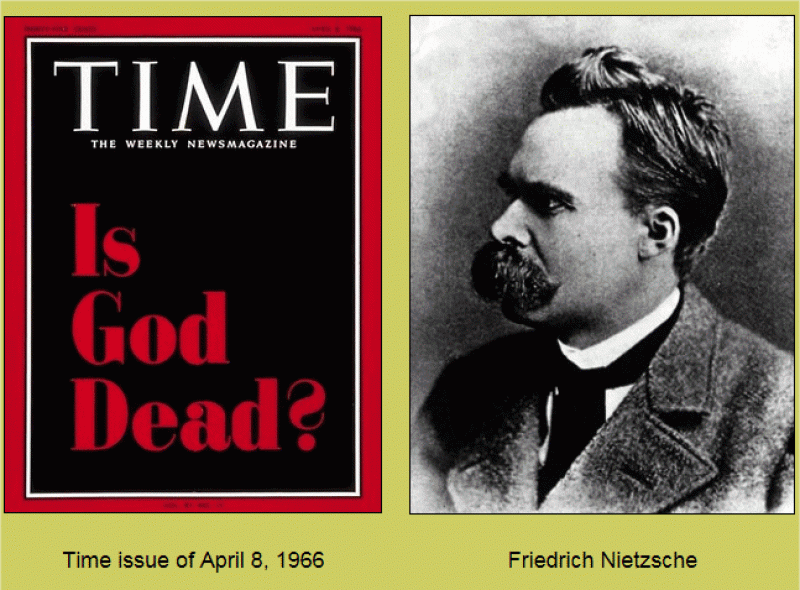Oleh: Muhammad Iswardani Chaniago
ANANDA Sukarlan menjadi tenar, kali ini bukan karena skill musiknya tapi karena sikap walk out-nya dari arena pertemuaan tepat saat Gubernur Jakarta, Anies Baswedan hendak berpidato pada acara ulang tahun Kolese Kanisius. Apa pasal? Ia menganggap Anies berkompetisi secara tidak sehat dalam pilgub Jakarta. “Walaupun saya tahu bahwa mungkin kita harus mengundang seseorang karena jabatan itu tapi saya kira untuk next time kita harus melihat sosok itu seperti apa dan bagaimana dia mendapatkan jabatan itu,” demikian papar Ananda.
Kuat dugaan pernyataannya itu terkait al-Maidah effect yang menerpa Ahok, sehingga gagal menjadi gubernur. Fenomena Ananda Sukarlan menambah panjang daftar tokoh sekuler-liberal dengan luka ideologis yang belum sembuh pascapilgub DKI.
Selain itu, fenomena ini juga semakin kuat mematahkan mitos bahwa kelompok sekuler-liberal adalah kelompok toleran dan tidak emosional. Selama ini aktor-aktor religius terutama dari kelompok kanan sering mendapat stigma negatif bahwa mereka adalah kelompok emosional, tidak rasional dan intoleran. Bahkan dengan bahasa yang agak kasar kerap disebut kaum sumbu pendek. Sebuah cap yang ingin mendeskripsi bahwa kelompok religi kanan kurang menggunakan akalnya dan sering meledak-ledak.
Terminologi dengan karakter yang negatif tersebut tidak hanya ditemukan dalam karya ilmiah yang serius, sematan tersebut juga muncul di ruang-ruang publik seperti medsos, artikel lepas atau wawancara, sehingga keberadaannya bisa diraba dengan jelas.
Khamami Zada dalam bukunya, Islam Radikal, mendeskripsikan Islam radikal dengan salah satu ciri, “kuatnya keyakinan kaum radikalis akan keyakinan program atau ideologi yang mereka bawa…Akan tetapi kuatnya keyakinan ini dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional dan menjurus pada kekerasan.” (Hal 17)
Baca: Hamid Fahmi: “Penggunaan Istilah ‘Moderat, ‘Radikal’ dan ‘Toleran
Bisa disimak pula bagaimana paparan Burhanuddin Muhtadi (BM) pengamat politik, saat ia merelasikan fakta keengganan masyarakat Jakarta memilih gubernur Jakarta disebabkan kasus al-Maidah dengan sematan emosi: “Faktor rasional (evaluasi atas kinerja petahana) dan faktor emosional (al Maidah) secara bersama-sama dan signifikan pengaruhnya terhadap pilihan.” (Burhanuddin Muhtadi, Rasionalitas Pemilih Jakarta, Kompas.com, 21/2/2017)
Jadi faktor kasus al-Maidah dilekatkan dengan karakter emosional. Secara tak langsung BM hendak mempredikatkan agama dan kelompok religius dengan predikat emosional yang miskin rasionalitas. Sementara di pihak seberang, kelompok sekuler-liberal sering digambarkan sebagai grup pemikir yang rasional, tidak emosional dan toleran.
Wajah Sekuler-Liberal
Sejatinya wajah sekuler-liberal yang konon dipandang positif itu bisa dikatakan tidak benar sepenuhnya. Bahkan bisa dikatakan kamuflase dan mitos. Secara historis bukti emosionalisme dan intoleran sekuler-liberal bisa ditangkap dari sejarah mereka yang tidak bisa dikatakan selalu damai. Revolusi Prancis bisa dijadikan sebuah sampel politik bagaimana sisi emosionalisme dan intoleransi tumbuh di kalangan sekuler-liberal.
Tahun-tahun awal sekularisme Prancis adalah tahun yang menyedihkan bagi kelompok religi Katolik. Pada tahun 1790, Majelis Nasional mengundangkan sebuah regulasi yang keras agar para agamawan (bishop dan priest) bersumpah setia pada negara. Bila menolak konsekuensinya adalah penjara. Pada periode awal tersebut yang namanya pengambilalihan tanah milik gereja dan pembunuhan para agamawan adalah lumrah.
Kabarnya sekitar 3000-an agamawan mati di bawah pisau guillotine sepanjang periode ini. Yang menjadi sebabnya menurut Tocqueville, sejarawan Prancis, adalah sikap anti Katolik dan menghubungkan agama ini dengan rezim sebelumnya. Bahkan ketika Undang-undang Kebebasan Beragama diundangkan tahun 1791, sikap emosional dan sadis belum bisa dilepaskan dari sekularisme Prancis. Agama masih dipandang sebagai ancaman dengan pelarangan upacara keagamaan dan segala perwujudannya di area publik. (Ahmed T. Kuru, Secularism and State Policy Toward Religion, 2009, 139-140)
Demikian pula yang terjadi di Turki. Sekularisme Turki sangat emosional diwujudkan dalam bentuk pembubaran sekolah agama dan pengadilan agama, pelarangan huruf arab, dan semua yang berbau Islam dan arab menjadi sesuatu yang terlarang.
Bahkan di Amerika Serikat sendiri, sisi emosionalisme juga tak terhindarkan. Itu terrefleksikan ketika capres Partai Demokrat, Hillary Clinton, dikalahkan Donald Trump dari Partai Republik. Negara bagian California yang merupakan basis pendukung Partai Demokrat, yang cenderung sekuler-liberal, sempat mengancam akan memisahkan diri dari pemerintahan federal AS.
Di Indonesia gambaran kelompok sekuler-liberal yang emosional dan intoleran bukan tidak ada. Lebih parahnya bisa dikatakan tidak sedikit. Era Soeharto awal 1970-1980-an, ketika sang penguasa begitu kental nuansa sekularismenya dan akrab dengan kelompok sekuler, kebijakan yang dihasilkan juga menyeramkan. Pelarangan jilbab di sekolah, kewajiban asas tunggal, dan sikap rezim yang keras terhadap umat Islam adalah contohnya.
Kasus Ahok yang terbukti menista agama, sematan kebodohan terhadap pemilih yang memilih berdasarkan agama, dan yang terakhir adalah sikap yang ditunjukkan Ananda Sukarlan, merupakan bukti emosionalisme dan intoleran itu melekat dalam tubuh kelompok sekuler-liberal di era reformasi. Belum lagi fenomena caci-maki di medsos yang tak kalah marak. ** (BERSAMBUNG)