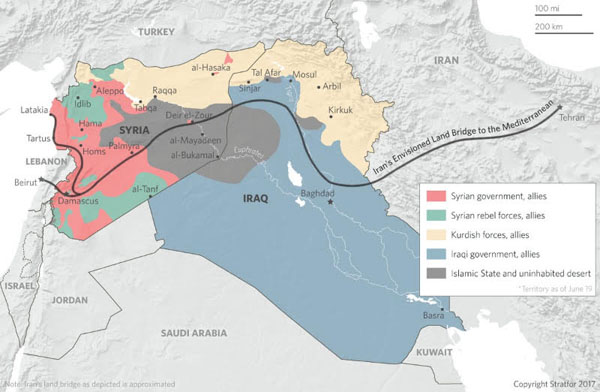Oleh: Dinar Kania
Hidayatullah.com | Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memainkan peranan penting dalam diplomasi terkait isu ‘Israel’- Palestina maupun perang sipil di Suriah dan Yaman atau konflik di dunia Islam lainnya. Pada isu Palestina, Indonesia berperan sebagai fasilitator, co-sponsor, partisipator, motivator, inisiator, dan justifikator dalam usaha membantu penyelesaian konflik Palestina-’Israel’ (Mundore, 2019).
Tahun 2019 lalu, Indonesia terus menggalang dukungan internasional untuk menolak rencana aneksasi wilayah Palestina oleh ‘Israel’, diantaranya dengan mengirimkan surat kepada negara anggota GNB, G-77, OKI, Uni Eropa, dan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Terkait isu Suriah, Indonesia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada tahun 2019 ketika membahas isu kemanusiaan Suriah, Indonesia menekankan misi kemanusiaan di Suriah perlu menjadi prioritas DK PBB.
Rekam jejak Indonesia dalam konflik di Timur Tengah melalui kementerian Luar Negeri untuk menyuarakan isu-isu tersebut cukup beragam. Namun pertanyaan pentingnya adalah, mengapa Indonesia sepertinya kurang memiliki pengaruh di dunia Islam dalam menyelesaikan konflik tersebut?
Faktor Internal
Indonesia secara kuantitas memang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, namun nilai-nilai Islam tidak pernah secara signifikan mempengaruhi kebijakan negara Indonesia. Saat ini, negara-negara berpenduduk muslim, termasuk Indonesia, tidak lagi memiliki kesatuan suara akibat berbagai konfllik kepentingan terkait ekonomi dan politik sehingga melupakan visi peradaban Islam yang berbasis ilmu dan etika.
Menurut Franz Rosenthal dalam bukunya “Knowledge Triumphant” , tidak pernah ada peradaban di dunia ini yang sangat berfokus kepada ilmu selain peradaban Islam (Makdisi, 2009). Tentunya hal tersebut sangat berbeda dengan visi negara-negara muslim di zaman sekarang yang hanya mengejar aspek-aspek material atau fisikal dan melupakan budaya ilmu sebagai asas utama peradabannya.
Hal tersebut pada akhirnya membuat konflik internal di tubuh umat Islam menjadi runcing karena masing-masing berusaha menguasai dan mendominasi. Padahal dalam tradisi Islam, konsep ilmu dan adab (etika) akan mentransformasikan visi kepemimpinan sebagai sebuah amanah yang harus dipertanggujawaban di hadapan Allah swt, dan bukan menjadi alat untuk menindas sesama.
Konsep amanah yang berdimensi metafisik tersebut selama beradab-abad telah menghasilkan para pemimpin yang adil dan menjadi faktor pemersatu umat Islam. Menurut al-Attas, hilangnya orientasi terhadap ilmu dan adab (etika ) di dunia Islam akibat confusion of knowledge, pada gilirannya akan menghasilkan para pemimpin palsu yang justru menjadi sebab bagi munculnya berbagai persoalan, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial. (Al-Attas, 1993).
Meskipun pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenlu telah memperjuangkan isu Pelestina, Suriah dan Yaman, namun kenyataannya, banyak politisi di Indonesia yang memanfaatkan isu -isu tersebut sebagai alat politik untuk sekedar menarik suara umat Islam ketika masa kampanye. Konflik Arab-’Israel’ tidak bisa dipungkiri sangat menarik perhatian publik, khususnya muslim di Indonesia, sehingga dapat dikategorikan sebagai arena konstituensi, yang berarti bahwa kekuatan politik dapat memanipulai isu Palestina ini untuk mendapatkan simpati publik (M. Muttaqien, 2013).
Menurut Umar, meskipun Islam diikuti oleh mayoritas orang Indonesia, posisi kebijakan luar negeri Indonesia tentang Konflik Arab-’Israel’ selama rezim Sukarno tidak didasarkan pada nilai-nilai Islam tetapi dipengaruhi oleh gagasan dialektis Sukarno tentang tatanan dunia. Islam telah digunakan dalam fungsi instrumentalnya untuk melegitimasi kebijakan luar negeri tertentu di Indonesia.
Instrumentalisasi Islam dapat dilihat sebagai hasil dari wacana hegemonik yang beroperasi dalam tatanan politik Indonesia, yaitu tatanan politik “nasionalis”. Meskipun Soekarno dan Soeharto memegang posisi ideologis yang berbeda dalam mengartikulasikan wacana nasionalis mereka, namun keduanya berbagi posisi yang sama tentang cara melihat “Islam”.
Di era mereka, Islam hanya diartikulasikan sebagai “penanda” ketika Indonesia menjalin komunikasi dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya. “Penanda utama” tentunya adalah nasionalisme, meskipun dengan konteks dan rezim politik yang berbeda (Umar, 2016).
Faktor Eskternal
Secara geopolitik, hubungan yang sangat erat antara negara superpower AS dengan ‘Israel’ menjadikan konflik di Timur-tengah semakin sulit untuk diselesaikan. AS selalu memanfaatkan hegemoni ekonominya pada negara-negara Arab untuk membela kepentingan ‘Israel’ (Pradana & Yulianti, 2018).
Posisi AS sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, sering dimanfaatkan untuk menolak berbagai resolusi yang merugikan AS, maupun ‘Israel’. Akhirnya PBB sebagai organisasi internasional yang seharusnya dapat bersikap adil kepada negara-negara anggotanya, namun pada kenyataannya menerapkan double standard dalam mensikapi berbagai pelanggaran terhadap hukum internasional yang dilakukan AS maupun ‘Israel’.
Amerika dan negara-negara Barat menurut Slaughter telah membajak makna HAM dan terorisme yang telah merugikan perjuangan rakyat Palestina. Konsep awal terorisme pada awalnya lebih banyak mengacu pada state terrorism dan bukan kepada tindakan individu, tetapi setelah tahun 1970, terorisme didefinisikan ulang sehingga akhirnya berhasil mendeskriditkan national liberation struggle sebagai gerakan terorisme, salah satunya adalah perjuangan Palestina untuk memerdekakan diri dari penjajahan ‘Israel’.
Kritik terhadap hukum Internasional dan PBB juga datang dari kelompok Marxist. Menurut Mieville, pada kenyataannya, hukum internasional merupakan pertarungan ekonomi negara-negara kapitalis dalam perlombaan menguasai sumber-sumber produksi (Miéville, 2004).
Oleh karena itu, selama umat Islam masih berharap besar pada PBB atau hukum internasional untuk menyelesaikan konflik di dunia Islam dan tidak berusaha mengatasi permasalahan internal mereka, tentunya perdamaian di wilayah Palestina, Suriah dan lain-lain, hanyalah sebuah utopia. Instrumen internasional sering menjadi alat politik Barat untuk menyudutkan negara-negara Islam.
Bahkan Zizek berpendapat, kejahatan besar yang dinisbatkan pada etnik Muslim Turki pada abad 20, yaitu genosida Armenia dan presekusi suku Kurdi, sebenarnya bukan dilakukan oleh kekuatan politik Islam tradisional, namun dilakukan oleh para tantara turki modern yang ingin menjadikan Turki sebagai European nation-state (Žižek, 2005).
Oleh karena itu, kekurangan di tubuh umat Islam bukan menjadi faktor satu-satunya yang menghambat penyelesaian berbagai konflik di dunia Islam-khususnya di Timur-tengah. Namun ada faktor eksternal yang pengaruhnya sangat signifikan sehingga konflik tersebut terus memanas dan sulit untuk diselesaikan jika negara-negara Islam tidak bersatu dan segera memperbaiki diri.*
Penulis peneliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSITS)
Referensi
Al-Attas, S. M. N. (1993). Islam and Secularism. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.
Muttaqien, S. (2013). Domestic Politics and Indonesia’s Foreign Policy on the Arab-’Israel’i Conflict. Global & Strategis, 7(1), 57–72.
Makdisi, G. (2009). Knowledge Triumphant : The Concept of Knowledge in Medieval Islam. American Anthropologist, 75, 483–485.
Miéville, C. (2004). The Commodity-Form Theory of International Law: An Introduction. Leiden Journal of International Law, 17(2), 271–302. https://doi.org/10.1017/S0922156504001827
Mundore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik ‘Israel’ – Palestina. Jurnal CMES, XII(2), 170–181.
Pradana, A. M. N., & Yulianti, D. (2018). Peran Liga Arab Pada Konflik di Timur Tengah dalam Perspektif Ekonomi-Politik Internasional. Jurnal ICMES, 1(1), 99–120. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v1i1.7
Umar, A. R. M. (2016). A Geneolgy of Moderate Islam : Governmentality and Discourses of Islam in Indonesia’s Foreign Policy, 23(3).
Žižek, S. (2005). Against Human Right. New Left Review, 34, 115–131.