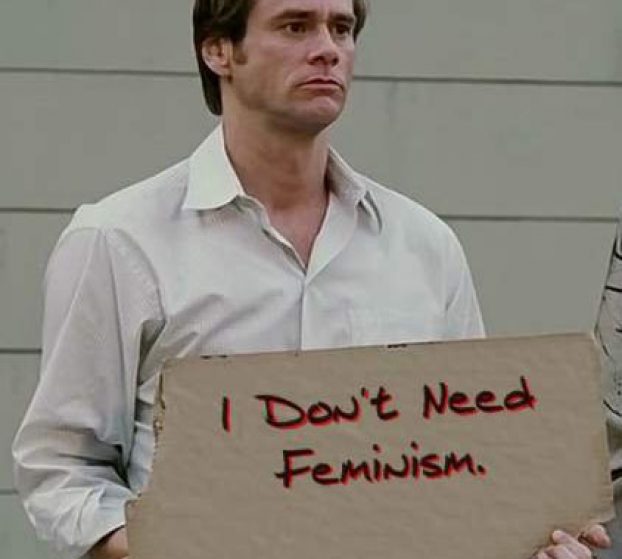#KaburAjaDulu bukan sekadar tagar. Ini adalah keputusan rasional dari generasi sandwich yang merasa bahwa negeri ini meminta terlalu banyak, tetapi memberi terlalu sedikit, kehidupan layak janji-janji kosong kampanye
oleh: Agus Maksum
Hidayatullah.com | TAGAR #KaburAjaDulu melesat di jagat maya, bukan sekadar tren iseng, tetapi potret nyata kekecewaan anak muda terhadap negeri ini.
Di media sosial, seruan itu menggema, dari keluhan akan sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya upah, hingga kegelisahan atas kebijakan yang terasa lebih seperti eksperimen daripada solusi.
Dalam setiap cuitan dan unggahan, ada rasa frustrasi yang tertumpuk dari waktu ke waktu. Mereka bertanya, “Mengapa harus bertahan di negeri yang seolah tak memberi ruang bagi kami untuk tumbuh?” Angka-angka berbicara: di Jepang, dengan modal 30-50 juta, seseorang bisa memperoleh gaji 15-25 juta rupiah per bulan. Di Korea, dengan modal lebih kecil, gaji bahkan bisa mencapai 50 juta. Sementara di Indonesia? Gelar S1, S2, S3, dengan gaji 3-5 juta—tergantung calo.
Lebih dari sekadar angka, fenomena ini adalah gejala sosial yang harus diperhatikan dengan serius. Tidak sedikit yang menuturkan, “Aku tak lagi melihat masa depan di sini.”
Pindah ke luar negeri menjadi seperti pelarian yang rasional. Mereka tak sekadar menghindar, tetapi mencari kehidupan yang lebih layak, yang di sini hanya terasa seperti janji-janji kosong dalam pidato-pidato kampanye.
Kebijakan pemerintah kadang terasa seperti menambah garam pada luka. Larangan pengecer menjual LPG 3 kg bersubsidi, misalnya, membuat masyarakat kelas bawah semakin tercekik.
Mau bertahan di Indonesia menjadi pengangguran? Atau mencoba peruntungan di luar negeri, meski penuh risiko?
Namun, apakah kabur adalah satu-satunya jalan? Tidak juga. Ada anak muda yang memilih bertahan dan mencari solusi di tanah sendiri. Ada harapan pada ekonomi digital, yang membuka peluang kerja lintas negara tanpa harus meninggalkan rumah.
Anak-anak muda mulai menyadari bahwa coding, desain grafis, atau menjadi virtual assistant bisa membuka pintu rezeki dari klien di New York atau Amsterdam. Inilah peluang yang belum sepenuhnya disentuh oleh kebijakan pemerintah.
Meskipun begitu, tantangan besar tetap ada—bahasa Inggris, keterampilan komunikasi, dan kepercayaan diri. Jika ini bisa diatasi, kita bisa melihat generasi muda yang tak lagi harus kabur untuk merasa dihargai, tetapi menjadi pionir yang membangun dari tanah air.
Tagar #KaburAjaDulu adalah peringatan bagi kita semua. Bukan hanya sekadar curahan hati yang bisa diabaikan. Jika tidak direspon dengan tepat, fenomena ini bisa menjadi ancaman serius bagi mimpi besar Indonesia Emas 2045.
Kita membutuhkan lapangan kerja yang layak, kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan kepercayaan bahwa di sini—di tanah kita sendiri—ada masa depan yang masih bisa diperjuangkan.
Jadi, sebelum kabur, mari kita pikirkan kembali: apakah kita ingin meninggalkan negeri ini, ataukah justru membangunnya kembali dari puing-puing kekecewaan?
Generasi Sandwich Dobel Kuadrat
Di suatu tempat yang kini mulai ditinggalkan, ada desa yang pernah penuh tawa. Sawah terbentang luas, sungai mengalir jernih, dan anak-anak berlarian mengejar layang-layang di sore hari. Di sana, Puteri lahir.
Ia tumbuh dengan cerita tentang kerja keras. Orang tua dan kakeknya selalu berkata, “Sekolah yang tinggi, kerja yang giat, dan hidupmu akan lebih baik.” Maka, Puteri mengikuti nasihat itu. Ia bekerja sejak fajar, memikul harapan yang terlalu besar di pundaknya. Ia bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri.
Ia menghidupi orang tua yang sudah menyerah pada hidup. Ia menyekolahkan dua adiknya yang lebih sibuk bermain game daripada menulis masa depan mereka sendiri. Ia membantu paman, bibi, keponakan—keluarga yang tak pernah lepas dari hutang. Tetapi ia bertahan. Karena begitulah kehidupan berjalan di sini.
Hingga suatu hari, ia menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan: Negeri ini tidak hanya menuntutnya menghidupi keluarganya. Negeri ini juga menuntutnya menghidupi mereka yang bahkan tidak ia kenal.
Ngeri prihatin gemes dan ngenes membaca narasi Tere Liye berjudul “Generasi Sandwich Dobel Kuadrat”.
Setiap bulan, gajinya dipotong pajak. Pajak penghasilan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Tapera. Setidaknya Rp 600.000 hilang begitu saja. Dalam setahun, lebih dari Rp 7,2 juta raib tanpa pernah ia tahu ke mana perginya.
Ia bertanya-tanya, apa yang didapatkannya dari semua itu?
Ketika ia membutuhkan gas 3 kg, negeri ini berkata, “Tidak boleh, kamu mampu.”
Ketika adiknya ingin mengajukan bantuan pendidikan, negeri ini berkata, “Tidak bisa, keluargamu sudah cukup kaya.”
Tetapi setiap bulan, uangnya terus diambil. Ia bukan hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga jutaan orang miskin yang entah mengapa tetap miskin. Negeri ini berkata bahwa pajak itu untuk kesejahteraan rakyat, tetapi Puteri tidak pernah merasakan sejahtera.
Dan sementara ia bekerja dari pagi hingga malam, ada orang-orang yang bahkan tidak perlu bekerja keras seperti dirinya. Mereka flexing.
Anak pejabat, anak komisaris, anak-anak yang hidupnya sudah pasti di atas, memamerkan jam tangan seharga rumah, tas seharga tanah, mobil yang harganya bisa memberi makan satu kampung.
Mereka hidup nyaman. Dan ketika akhirnya terbongkar bahwa uang mereka berasal dari korupsi, negeri ini tidak benar-benar marah. Hukuman mereka lebih ringan dari beban yang setiap hari dipikul Puteri.
Pergi atau Bertahan?
Dari layar ponselnya, Puteri melihat dunia lain. Kanada, Australia, Jepang, Korea. Di sana, kerja keras dihargai.
Tidak ada yang mengatakan, “Kamu harus berbagi dengan negara,” hanya untuk melihat pejabat-pejabatnya hidup dalam kemewahan.
#KaburAjaDulu bukan sekadar tagar. Ini adalah keputusan rasional dari mereka yang merasa bahwa negeri ini telah meminta terlalu banyak, tetapi memberi terlalu sedikit.
Mereka tidak ingin meninggalkan rumah mereka. Tetapi jika rumah ini tidak lagi memberi mereka tempat untuk bertahan, apa yang bisa mereka lakukan?
Mereka pergi dengan hati yang berat. Meninggalkan sawah yang pernah mereka cintai. Sungai tempat mereka bermain. Aroma tanah basah setelah hujan.
Mungkin, suatu hari, mereka akan kembali. Mungkin, suatu hari, negeri ini akan berubah.
Tetapi sampai hari itu tiba, mereka harus terus berjalan. Karena bertahan di sini berarti menerima bahwa hidup mereka hanya untuk menanggung beban yang tak pernah mereka pilih.
Catatan untuk Negeri Ini
Gambaran tentang “Generasi Sandwich Dobel Kuadrat” ini bukan sekadar fiksi. Tere Liye menuliskannya sebagai kenyataan yang dialami banyak anak muda di negeri ini.
Anak muda yang bekerja keras tetapi tetap miskin. Anak muda yang harus menghidupi keluarga mereka sendiri, sekaligus menopang sistem yang tidak pernah berpihak pada mereka. Anak muda yang akhirnya memilih pergi, bukan karena mereka ingin, tetapi karena negeri ini tidak memberi mereka pilihan lain.
Dan ketika akhirnya mereka benar-benar pergi, siapa yang akan tersisa di sini? Mungkin hanya mereka yang sudah nyaman di atas sana.
Dan negeri ini?
Ia akan terus berjalan, kehilangan sedikit demi sedikit anak-anak terbaiknya.*
Penulis pegiat StartUp digital berbasis Economic Community Platform. Pemegang hak patent platform digital komunitas