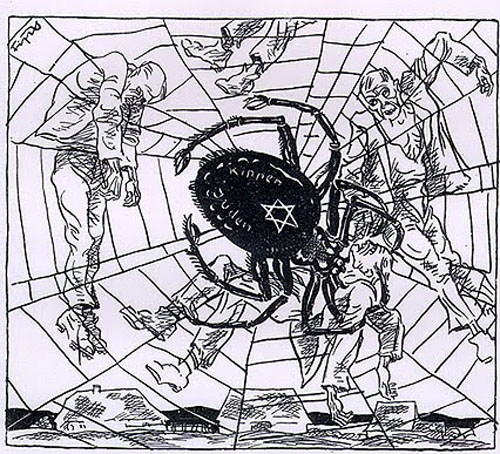Oleh: Muh. Nurhidayat
SEORANG reporter TV One membuat berita eksklusif yang ternyata fiktif tentang makelar kasus (‘markus’). Si reporter menyuap pegawai instansi hukum agar mau diajak wawancara akal-akalan tentang ‘markus’ yang sempat menghebohkan itu. Entah bagaimana kelanjutannya, apakah si reporter itu dipecat atau tidak dari saluran ‘merah’.
Beberapa tahun kemudian, tepatnya awal 2016, Metro TV memberitakan Wahdah Islamiyah dan pimpinannya, Muhammad Zaitun Rasmin sebagai—salah satu—jaringan teroris di Indonesia. Pemberitaan fiktif tersebut menuai kecaman dari ulama dan umat muslim lintas ormas maupun parpol yang bersimpati kepada Rasmin dan ormasnya.
Bahkan Polri serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun menyangkal berita tanpa data dan fakta yang dilaporkan Metro TV. Entah bagaimana ganjaran untuk si wartawan pembuat berita palsu tersebut, apakah ia dipecat atau tidak dari televisi ‘biru’.
Jika kedua televisi mainstream Indonesia di atas tidak jelas apakah memberi sanksi tegas atau tidak kepada wartawannya yang membuat berita bohong, maka Jawa Pos—induk jaringan koran berpusat di Surabaya—sangat tegas terhadap wartawannya yang membuat berita bohong. Koran tersebut memecat reporternya yang kedapatan menulis hasil wawancara eksklusif—yang ternyata—fiktif dengan istri Dr. Azahari, tersangka terorisme asal Malaysia. Ternyata istri Dr. Azahari yang berdomisili di Kuala Lumpur sedang sakit dan tengah menjalani operasi bedah mulut, sehingga mustahil bisa diwawancara, apalagi wawancara eksklusif pula (Syah, 2011)
Kasus berita bohong memang sering terjadi di era kebebasan pers ini. Padahal pemerintahan BJ Habibie pada 1998 memberikan kebebasan pers untuk meningkatkan kualitas informasi di negara kita. Namun kebijakan mulia ini disalahgunakan segelintir media atau wartawan tidak beretika. Sehingga semangat kebebasan pers berubah tanpa terkendali menjadi fenomena kebablasan pers.
Pakar komunikasi Universitas Hasanuddin, Mansyur Semma (1999) merisaukan kebablasan pers dengan ungkapan, “Ketika pers bebas tanpa pengawasan, maka pers akan sangat liar dan tidak dapat dikendalikan.”
Hoax Amien Rais
Pada awal reformasi, sejumlah tokoh 2 ormas Islam terbesar Indonesia menjadi korban berita bohong oleh media tak beretika. Tabloid X-File pernah memberitakan adanya (maaf) perselingkuhan mantan ketua umum Muhammadiyah, Muhammad Amien Rais dengan Zarima Mirafsur—yang dijuluki masyarakat sebagai ‘ratu ekstasi’. Semua sumber beritanya anonim dan setelah diselidiki ternyata berita tersebut hoax.
Dewan Pers: Penilaian Terhadap Situs Media Tidak Boleh Sepihak
Selain Amien Rais, Gus Dur—mantan ketua umum NU, diberitakan majalah GAMMA telah (maaf) berselingkuh dengan Aryanti Sitepu. Namun diduga ada muatan-muatan politis pada pemberitaan kedua tokoh untuk merusak cita Muhammadiyah dan NU, yang merupakan ormas Islam terbesar di negara kita.
Tidak hanya itu, bahkan presiden BJ Habibie sekalipun menjadi korbannya. Padahal beliaulah yang membuka kebebasan pers. Media-media mainstream dan gurem yang tidak menyukai Habibie—secara pribadi maupun karena keislamannya—secara sporadis ataupun massif merusak citranya melalui berita-berita bohong. Namun Habibie adalah pengikut sikap Thomas Jefferson, presiden AS yang tidak marah apalagi menghukum wartawan dan media yang menyerang citra baiknya.
Sejak munculnya distorsi kebebasan pers menjadi kebablasan pers, tidak sedikit akademisi maupun praktisi jurnalistik yang mewacanakan pentingnya standarisasi profesi wartawan dan standarisasi ‘kesehatan’ media. Sebab wartawan yang tidak profesional, apalagi bekerja di media yang tidak ‘sehat’ akan memunculkan banyak masalah di bidang informasi. Bukan hanya berita bohong saja yang muncul, tetapi juga kriminalitas lainnya yang dilakukan oknum tak beretika yang mengatasnamakan dirinya sebagai wartawan. Sehingga ada orang mengaku wartawan tetapi melakukan pencurian, pemerasan, bahkan perampasan atas nama pers.
Oknum-oknum tak beretika seperti inilah yang kemudian dikenal sebagai ‘wartawan bodrex’, wartawan ‘muntaber’ (muncul tanpa berita), bahkan juga WTS (wartawan tanpa suratkabar). Istilah wartawan ‘bodrex’ sendiri berasal dari anekdot bahwa oknum-oknum yang mengaku wartawan tersebut sering memeras sejumlah instansi. Para pejabat instansi sering pusing menghadapi mereka. Sehingga para pejabat harus minum bodrex (salah satu merk obat sakit kepala) agar tidak pusing lagi.
Guru besar ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin, Andi Muis adalah akademisi senior yang mewacanakan pentingnya standarisasi media dan jurnalis agar kualitas informasi kita terjaga. Beliau pun berkomentar, “Saat ini banyak oknum mengaku wartawan agar kebal hukum. Padahal wartawan juga manusia biasa. Jika ada wartawan yang mencuri jemuran tetangganya, maka harus dihukum penjara karena tergolong perbuatan pidana, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas jusnalistik,” (Muis, 2001)
Kepedulian Umat
Dewan Pers atas permintaan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) mulai tahun 2017 menerbitkan hasil verifikasi media. verifikasi media merupakan pengakuan tentang standarisasi yang telah dicapai oleh media. Pada tahan pertama baru terdapat 74 media massa yang telah diverifikasi. SPS berharap ribuan media—cetak, radio, televisi, dan internet—untuk mengurus varifikasi media.
Harapan SPS dan Dewan Pers patut didukung bersama, Sebab verifikasi media adalah ikhtiar untuk mengontrol agar kebebasan pers tidak melenceng dari niat mulia untuk memajukan kehidupan informasi Indonesia yang sehat, bebas dari berita bohong (hoax) serta bebas dari segala bentuk kriminalitas yang mengatasnamakan pers.
Media massa Islam pun diharapkan turut mengurus verifikasinya. Sebab meskipun hanya merupakan lembaga independen, namun Dewan Pers—yang dibiayai APBN—merupakan representasi pemerintah, yang harus ditaati selama mengajak kita kepada hal ma’ruf (kebaikan). Bukankah verifikasi media merupakan kebijakan yang ma’ruf?
Sebagai representasai pemerintah di bidang informasi, Dewan Pers memang perlu ditaati, karena Allah subhanahu wata’ala berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu.” (QS. 4 : 5)
Seorang redaktur senior sebuah media Islam berpengaruh sangat mendukung verifikasi media oleh Dewan Pers, meskipun medianya sendiri belum—memperoleh jatah—diverifikasi.
Menurutnya, verifikasi media adalah kebaikan yang perlu diawasi umat Islam. Seperti SIUPP di zaman Orde Lama dan Orde Baru, verifikasi media yang tidak diawasi ibarat pisau bermata dua, sehingga sewaktu-waktu bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik penguasa. Namun demikian, aturan verifikasi media tetap patut didukung karena jauh lebih baik ada aturan—meskipun terdapat kekurangan—daripada tanpa aturan yang mengakibatkan anarkisme media.
Pendapat redaktur senior tersebut sangat beralasan. Oleh karena itu, kepedulian umat, khususnya para akademisi dan praktisi jurnalisme Islam sangat diperlukan demi kelancaran program verifikasi media oleh Dewan Pers. Umat Islam perlu mendorong Dewan Pers agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik secara independen tidak menjadi alat kekuasaan dan tidak diintervensi oleh pihak lain, termasuk penguasa sekalipun.
Kita tidak ingin Dewan Pers terjebak dalam intervensi oknum penguasa, seperti yang menimpa Menkominfo era Pemerintahan Jokowi saat ini. Dimana Menkominfo telah 3 kali melakukan ‘pembredelan’ dengan memblokir secara sepihak —dan bertentangan dengan konstitusi maupun UU—kepada sejumlah media Islam online, hanya karena tekanan segelintir oknum penguasa, yang tidak ingin kaum muslimin eksis di bidang informasi. Wallahua’lam.*
Dosen Ilmu Komunikasi Universias Ichsan Gorontalo