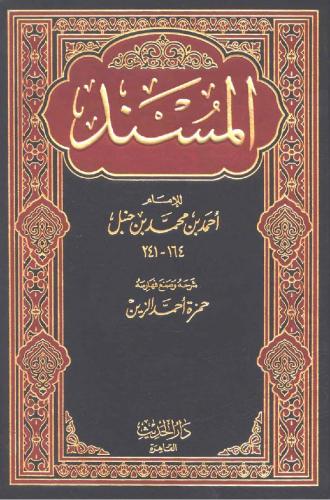Oleh: Andi Ryansyah
TOPIK intoleransi agama sering diperbincangkan dan diangkat oleh media. Walaupun ada kasusnya, tapi secara umum, kerukunan umat beragama di Indonesia masih terjaga. Hasil survei Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2017 terhadap 7.140 responden di 34 provinsi di Indonesia menyatakan, skor kerukunan umat beragama sebesar 72,27. Skor ini menunjukkan sikap keberagamaan di Indonesia tergolong rukun (Republika.co.id, 22/3/2018).
Kita patut bersyukur dengan keadaan rukun ini dan harus terus menjaganya. Jangan malah kasus intoleransi agama ini dibuat-buat. Yang toleran malah dianggap intoleran. Ini bisa membuat masyarakat jadi tidak tenang dan bingung.
Intoleransi Ekonomi
Ketimbang membuat-buat kasus intoleransi agama, mending kita menaruh perhatian lebih pada kasus intoleransi ekonomi. Kasus ini juga berbahaya bagi kerukunan warga. Di mana yang konglomerat tidak ingin yang melarat maju ekonominya. Di mana yang raksasa modal membunuh usaha rakyat kecil. Di mana segelintir orang menguasai ekonomi bangsa ini. 1% orang terkaya, menurut data Credit Suisse 2016, menguasai 49,3% kekayaan nasional. Masya Allah!
Kalau keadaannya seperti ini, bagaimana yang kaya tidak makin kaya dan yang miskin makin masuk got? Bagaimana tidak menimbulkan kecemburuan sosial? Bagaimana tidak berpotensi berontak dan memisahkan diri? Bagaimana tidak mengancam keutuhan NKRI? Bagaimana tidak bahaya?
Karenanya, masalah intoleransi ekonomi ini penting dan genting untuk segera diatasi. Perlu diungkap siapa saja orang atau kelompok yang intoleran di bidang ekonomi. Agar bisa kita ingatkan, jangan dzalim kepada orang kecil. Syukur mereka jadi insyaf.
Masalah intoleransi ekonomi ini jadi kompleks manakala masyarakat kita memandang bahwa saudara-saudara etnis Tionghoa (China) lah yang menguasai —untuk tidak menyebut menjajah— ekonomi bangsa ini. Sebab dari sini, masalah bisa merembet ke rasis. Tak dapat dipungkiri ketika api amarah berkobar dan konflik sosial meletus, umpatan rasis kadang keluar. Etnis Tionghoa jadi dianggapnya seperti orang luar. Bukan warga negara Indonesia.
Sebenarnya, tidak semua etnis Tionghoa berdompet tebal. Ada juga yang kantongnya kering. Ekonomi bangsa ini sebetulnya tidak hanya dikuasai mereka, tapi juga Amerika, Eropa, dan Jepang. Tapi mungkin karena Amerika, Eropa, dan Jepang relatif hanya modalnya yang masuk, sementara Tionghoa masuk bersama modal dan orangnya —baik di level atas, menengah, maupun bawah, maka muncul tambahan perasaan terancam dan lebih cepat menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat awam.
Soal penetrasi ekonomi asing, masyarakat awam tidak terlalu paham tentang hal itu. Mereka lebih mudah kesal dengan pelaku-pelaku yang tampak di depan matanya, yakni etnis Tionghoa.
Boleh dikatakan, masalah utama masyarakat kita dengan etnis Tionghoa sekarang ini sebenarnya bukanlah rasis, melainkan kesenjangan ekonomi. Inilah yang membangun tembok pemisah di antara keduanya. Oknum penguasa turut membangun tembok itu dengan lebih memberikan kesempatan kepada sejumlah pengusaha etnis Tionghoa untuk mengembangkan bisnisnya. Ada perlakuan diskriminasi ekonomi di sini. Tentu ini membuat rasa keadilan di dada masyarakat berontak. Kekesalan mereka kepada sebagian etnis Tionghoa ini didasari argumen ekonomi yang jelas, bukan berpijak pada sentimen ras.
Pikiran Bung Hatta
Untuk mengatasi masalah ini, pikiran Mohammad Hatta yang tertuang di majalah Star Weekly, 26 Januari 1957, agaknya masih relevan untuk dijadikan solusi. Dalam tulisannya yang berjudul “Warganegara Indonesia Turunan Tionghoa” itu, juga dituturkan bahwa kala itu, masyarakat memandang golongan Tionghoa lah yang menguasai ekonomi. Karenanya, mereka menuntut pemerintah untuk melindungi ekonomi nasional dan memberi kesempatan kepada pengusaha nasional untuk memperoleh kedudukan yang layak dalam perekonomian masyarakat.
Menurut Bung Hatta, masalah ini bisa diatasi dengan politik perekonomian yang tegas dengan menaikkan ekonomi rakyat yang lemah ke tingkat perekonomian golongan maju. “Dengan dasar-dasar jang berlaku di dalam kapitalisme masalah ini tidak dapat diselesaikan,” tegasnya.
Itu artinya, politik harus digunakan untuk menelurkan kebijakan dan tindakan yang dapat memperbaiki nasib rakyat miskin menjadi makmur. Bukan hanya satu golongan saja yang bisa menikmati hidup makmur. Pemerintah harus adil dan menyejahterakan semua warganya. Politik jangan malah digunakan untuk kepentingan, keuntungan, dan kekayaan diri, kelompok, partai, dan pemodal saja.
Bung Hatta mengakui tidak sedikit WNI keturunan Tionghoa yang telah berjasa untuk Indonesia. Di masa mendatang, kata Bung Hatta, mereka diperlukan lebih banyak lagi untuk membantu pembangunan negara. Mereka diajaknya untuk ikut serta membangun Indonesia yang adil dan makmur. “Ini hanja dapat dilaksanakan, apabila ia sanggup dalam segala usahanja menempatkan kepentingan umum di muka dan kepentingan diri sendiri di belakang,” terangnya.
Bung Hatta juga mengakui kepintaran WNI keturunan Tionghoa di bidang ekonomi. Sarannya kepada mereka agar kepintarannya itu dipakai untuk membantu perekonomian negara, seperti dengan melancarkan jalan ekspor ke pasar dunia. Selain itu, Bung Hatta juga menyarankan mereka agar membawa masyarakat ke dalam usaha bersama dengan rasa tanggung jawab bersama. Bung Hatta ingin jiwa baru disuntikkan dalam perekonomian dengan menjunjung tinggi moralitas dagang dan kejujuran, serta memberantas kecurangan dan penyelundupan.
Saran Bung Hatta ini akan menciptakan suasana kekeluargaan dalam berwirausaha. Dengan bekerjasama dan memajukan ekonomi golongan lemah, usaha golongan yang ekonominya kuat akan disokong pula oleh golongan yang ekonominya lemah. Walhasil keduanya jadi saling menguatkan. Inilah insan-insan toleran di bidang ekonomi.
Dengan adanya toleransi di bidang ekonomi serta didukung kebijakan ekonomi pemerintah yang adil, jurang kesenjangan ekonomi antara etnis Tionghoa dan rakyat pun akan menyempit. Tembok pemisah antara kita akan roboh. Sentimen ras akan sirna, dan bangsa ini akan semakin rukun. Salam damai dan persatuan.*
Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB)