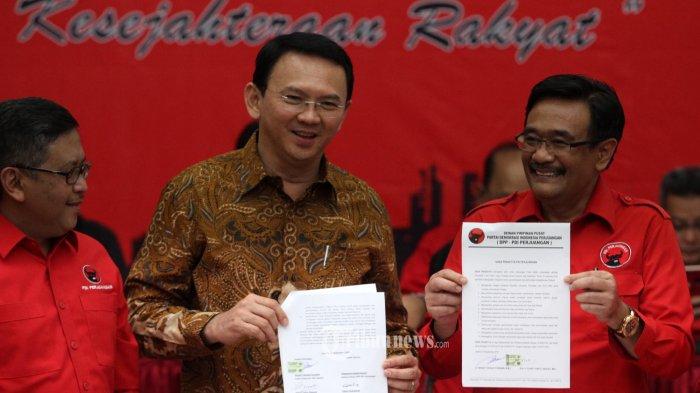Oleh: TGH M Hasanain Juaini
TERPILIHNYA Sadiq Khan, Wali Kota London yang dikenal seorang Muslim menjadi hiruk-pikuk. Sesuatu yang sangat lumrah.
Setelah satu dekade terjadinya peristiwa 9/11, Stasiun TV ABC, dengan ijin resmi pemerintah melakukan Live Survey. Survey dilakukan dengan skenario beberapa anak gadis dari keluarga non muslim memberi tahu keluarganya bahwa si gadis akan menikah dengan seorang pemuda muslim. Respons yang umum terjadi adalah keluarga si gadis murka dan bahkan ada yang mengamuk, main bentak dan usir.
Mari kita konfirmasi kasus itu melalui sisi terbalik, bahwa tidak diragukan perkembangan jumlah muallaf asli Amerika justru bertambah puluhan kali lipat setelah peristiwa 9/11. Padahal pada tahun pertama tragedi itu masyarakat Amerika mengalami perasaan horor dan teror terhadap Islam dan kaum muslimin.
Pada kasus pertama, imajinasi dominan yang berperan pada spontanitas keluarga non-muslim Amerika adalah penolakan nurani pada apa yang dirasakan sebagai suatu dukungan pada kejahatan, rasa tidak rela anaknya menjadi bagian dari kejahatan. Manusia berakal sehat tetap akan melakukannya serasional apapun dia. Sedangkan pada kasus ke dua adalah terkuaknya ketidak benaran tuduhan yang mendiskreditkan Islam sebagai idiologi yang mendalangi serangan pada World Trade Center telah melahirkan simpati dan keberterimaan Islam di hati sebagian masyarakat Barat.
Kesimpulannya, rasionalitas tidak dapat ditipu kecuali dengan keterkejutan yang melumpuhkan daya nalar. Setelah kebenaran terkuak, maka rasional bisa bekerja dengan baik dan benar.
Kembali kepada judul tulisan ini, terpilihnya Sadiq Khan sebagai Wali Kota London Muslim yang pertama, sebetulnya heboh dan ribut tentang muslim-muslim yang dapat memasuki jajaran pemegang public policy dimulai dari seorang Jack Ellis menyatakan masuk Islam pada bulan Desember 2007.
Pemberitaannya menghiasi berbagai media massa AS dan sejumlah media massa internasional. Penyebabnya adalah karena pada saat itu Ellis masih menjabat sebagai Wali Kota Macon, negara bagian Georgia, AS.
Belum berhenti keributan di Macon muncul lagi kasus hebohnya Dewan Kota Hamtramck, yang mayoritasnya akan dipegang oleh orang Muslim. Head line koran Washington Post kala itu menyalak keras: “Tinggal menunggu waktu saja sebelum kita melihat seorang Wali Kota Muslim.”
Hal itu memang kemuadian terbukti, tidak hanya di Amerika tetapi disekujur dunia Barat.
Italia memulainya pada tahun 2008, Mohamed Arturo Cerulli yang akrab dipanggil Arturo terpilih menjadi Wali Kota (Sindaco) di Kota Monte Argentario. Beberapa bulan setelahnya Ahmed Aboutaleb, seorang Muslim Belanda keturunan Maroko berhasil memenangkah pemilihan Wali Kota Rotterdam, Oktober 2008.
Diujung tahun 2008, Liverpool City, sebuah kota di negara bagian New South Wales yang mayoritas berpenduduk Katholik, memilih Ned Mannoun, pemuda muslim keturunan Lebanon (Libanon) sebagai Wali Kota mereka.
Teaneck, yang masuk wilayah Bergen, New Jersey, kota yang berpenduduk mayoritas Yahudi memilih Wali Kota Muslim pertama (tahun 2010) bernama Mohammed Hameeduddin. Kanada tidak mau ketinggalan, tahun 2010 Naheed Nenshi, mereka dapuk menjadi Wali Kota Calgary.
Lebih fenomenal lagi Naheed terpilih dalam World Mayor Prize 2014 sebagai wali kota terbaik dunia berbarengan dengan Tri Rismaharini.
Berikutnya (tahun 2013) di South Windsor, Connecticut, New England, Seorang muslim kembali terpilih menjadi Wali Kota, dialah Dr Anwar, seorang Demokrat. Dan tentu saja yang paling baru adalah Terpilihnya Sadiq Khan sebagai Wali Kota London Muslim pertama.
Tetapi ada hal aneh yang terjadi di Indonesia dalam menanggapi fenomena terpilihnya pemimpin-pemimpin Muslim di tengah komunitas non muslim.
Keanehannya adalah pada endorsing peristiwa itu sebagai suatu rasionalitas berdemokrasi masyarakat Barat. Inti yang mau mereka katakan adalah: “Lihatlah Barat yang rasional, mereka non-muslim tetapi memilih muslim sebagai pemimpin mereka.”
Atau jika dibalik bisa bermakna, “Kalau kalian muslim tetapi tidak mau memilih non-muslim sebagai pemimpin kalian maka kalian irrasional.” Lebih tegasnya dianggap bodoh karena sektarian/SARA.
Logika jumpalitan, itulah ungkapan yang cocok untuk kasus endorsing fenomena ke-terpilihan sosok-sosok muslim sebagai pemimpin di negeri Barat itu. Bagaimana tidak?
Sejatinya titik tolak peradaban Modern Barat itu dibangun di atas dendam terhadap disfungsialisasi agama. Itulah sebabnya para kandidat politik di Barat tidak mendekati pimpinan agama mayoritas saat berkampanye. Sebaliknya mereka mendekati tokoh-tokoh minoritas Yahudi yang menguasai uang atau tokoh-tokoh pendukung liberalisme yang memang digandrungi mayoritas.
Dari berbagai berita yang dilansir media terkait keterpilihan muslim di Barat itu kita mendapatkan jawaban bahwa faktor determinannya adalah, mereka ketika menjadi kandidat berhasil meyakinkan akan melayani dengan sebaik-baiknya ‘kehendak mayoritas’. Mayoritas percaya, karena secara rasional telah mengkaji dengan baik kredibiltas sang calon. Sang kandidatpun terpilih-lah.
Sadiq Khan misalnya, sebelumnya telah menjadi menteri dan anggota dewan kota melalui partai buruh selama bertahun-tahun. Sadiq berhasil menjembatani antara petugas security dengan para ekstrimis, bahkan sangat jauh, bersama anggota Partai Buruh dia juga menyetujui dan menandatangani persetujuan pada undang-undang perkawinan sejenis (LGBT), suatu yang dalam ajaran agamanya atau pribadinya sendiri sebagai hal yang diharamkan.
Wali Kota London Terpilih Sadiq Khan Pernah Dukung Perkawinan Sejenis
Idem ditto dengan calon wali kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb yang mendukung legalisasi narkotika.
Seorang Votters Sadiq memberikan alasan dalam komentarnya: “Seandainya lawan dari kandidat dari kubu Konservatif Zac Goldsmith, 41 adalah seorang imigran China (Bukan Sadiq Khan), saya akan memilihnya juga karena Goldsmith bukanlah pemuda yang dapat diandalkan untuk melayani masyarakat London.”
Singkatnya, urusan agama adalah faktor tidak DIHITUNG dalam urusan elektabilitas di negara-negara Barat. Kita jangan under estimated bahwa gereja dan para pemuka agama non-Islam tidak melakukan perlawanan.
Bukalah Youtube, Anda akan terperanjat dengan khutbah-khutbah, seminar, debat sampai orasi-orasi pinggir jalan yang luar biasa rasisnya. Buktinya itu tidak mempan dan itulah bukti bahwa isu agama “tidak nendang” di sana.
Sebaliknya di Indonesia, dasar bernegaranya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya dominasi mutlak elektabilitas ada pada urusan agamanya.
Oleh karenanya para kandidat di negeri ini (ibu pertiwi kita terinta) selalu membangun kesan kepribadian yang religius; Kunjungan ke masjid dan pondok pesantren, atau pergi umrah di saat selingan kampanye bahkan untuk mempengaruhi psikologis para hakim selalu kita saksikan para pesakitan kursi panas selalu memakai peci, jilbab atau sampai burqah.
Memang seperti yang dikatakan Ichsanuddin Noorsy, bahwa elektabilitas dalam berdemokrasi (semu) ditentukan oleh (2)Uang, (2) Media dan (3) para pemodal. Faktor-faktor itu bisa membalikkan keadaan tak peduli mayoritas suatu masyarakat pemilih itu sekuler atau religius.
Nampak jelas ketiga faktor tersebut di atas sedang bekerja untuk mencuri kehendak tradisi, budaya dan rasionalitas masyarakat Indonesia, karena jika dikumpulkan semua isi berita-berita yang mengusung kredo “demokrasi rasional” itu sebenarnya bisa diperas dalam seuntai kalimat: Kalau kalian tidak bisa memilih orang yang berbeda agama dengan anda sebagai pemimpin, maka anda tidak pintar.
Bukti paling kongkrit tentang kuatnya pengaruh keyakinan beragama di Indonesia adalah digunakannya para “representasi Muslim” untuk mengangkat tafsir minor yang telah tenggelam didasar lautan khilafiyah (perbedaan pendapat). Narasinya macam-macam tetapi maunya satu “Islam tidak mensyaratkan agama dalam memilih pemimpin”.
Mediapun ramai-ramai memuat, tak lupa komen-komen membanjir dengan dengan strategi, fans yang perempuan memakai potho berjilbab untuk sementara waktu sekalipun tidak muslimah.
Jawaban sekaligus pertanyaan terkait urusan tafsir minor terhadap ayat dan hadits kepemimpinan adalah: “Mengapa tidak dimuat tegas semua-semua pendapat para ulama, agar pembaca bisa memilih sesuai logika dan keyakinan mereka. Dan ini juga penting. Mengapa diributkan sekarang? Padahal urusan tafsir-menafsir sudah sedemikian rupa jelasnya di dalam Kitab-Kitab Tafsir Babon?
Pendapat akhir saya tentang fenomena Sadiq Khan adalah, mari kita simak saja ulasan ahli sejarah Barnaby Rogerson dalam bukunya “The Prophet Muhammad: A Biography“, bahwa menurutnya keberhasilan penaklukan-penaklukan yang dilakukan penguasa-penguasa muslim dahulu lebih pada kerinduan masyarakat taklukan kepada keadilan sejati yang selama ini hilang dari raja-raja mereka.
Tinggal yang harus difahami adalah bahwa konsep adil dalam Islam itu tidak boleh dilepaskan dari keimanan dalam artian tidak ada keadilan ketika keyakinan agama tidak disertakan di dalam anasir kepemimpinan. Wallahua’lam.*
Penulis adalah alumni PP Darussalam Gontor. Sekarang Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Lombok Barat