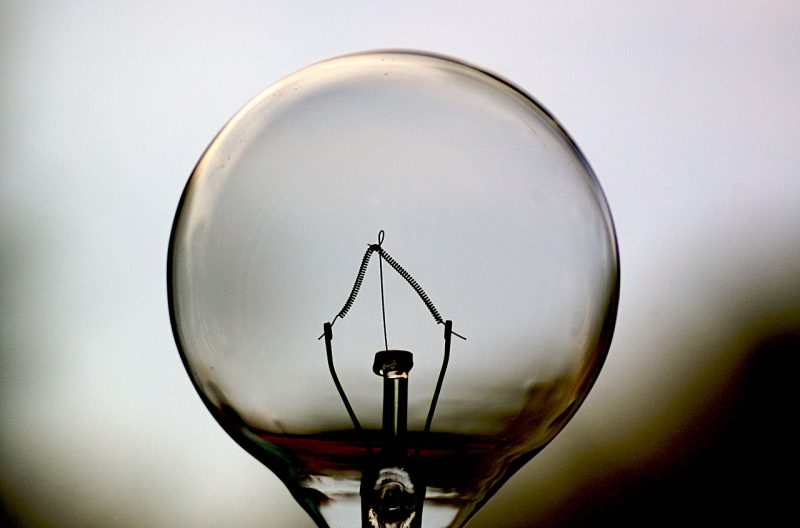SUDAH tiga-puluh-lima tahun telah berlalu sejak almarhum Cak Nur pada 2 Januari 1970 dalam diskusi yang diadakan oleh HMI, PII, GPI, dan Persami, di Menteng Raya 58 menyatakan, bahwa Islam sebenarnya mendukung sekularisasi dalam arti apa yang duniawi (‘sekular’) tidak perlu disakralkan. Khususnya urusan politik dan negara, yang merupakan perkara duniawi, dan karena itu jangan diagamakan: Gema gagasan seperti ini masih terdengar hingga kini, seperti pada ungkapan: “Jangan mempolitisir agama” atau “Jangan mencampur-adukkan agama dan politik”.
Dalam konteks Indonesia ketika itu, pemikiran Cak Nur dapat dengan mudah dipahami. Namun, untuk tidak mendogmakannya, gagasan tersebut layak dipikirkan kembali keabsahannya secara epistemologis maupun secara empiris. Memang benar, menurut para sosiolog, modernisasi tanpa sekularisasi tak ubahnya bagai merokok tanpa menghirup asap. Mustahil menjadi modern kalau tidak sekuler dulu. Contohnya, ya Negara-negara modern di Eropa dan Amerika, yang berhasil membangun dan maju di segala bidang dengan mengamalkan sekularisasi. Dan ini, konon, bertolak dari ajaran agama mereka sendiri, dimana tercatat ucapan Yesus: “Urusan Kaisar serahkan saja kepada Kaisar, dan urusan Tuhan serahkan kepada Tuhan.” (Gospel Matius XXII:21).
Implikasinya, agama tidak perlu ikut campur dalam urusan politik dan negara, sehingga muncul dikotomi antara regnum dan sacerdotium, pemisahan antara kekuasaan raja dan otoritas gereja, antara wewenang negara dan wewenang agama. Doktrin ini mendapat legitimasi dari St. Augustin membuat distingsi antara Kota Bumi (civitas terrena) dan Kota Tuhan (civitas dei). Faktor lain yang mendorong sekularisasi di Barat ialah gerakan Reformasi Protestan sejak awal abad ke-16, sebuah reaksi terhadap maraknya korupsi di kalangan Gereja yang dituduh memanipulasi dan mempolitisir agama untuk kepentingan pribadi (Philip Schaff, History of the Christian Church, 1997).
Belakangan, sejumlah peneliti seperti C.G. Brown dan Peter L. Berger mulai menyanggah apa yang disebut sebagai tesis sekularisasi itu. Sebabnya, fakta empiris justru menunjukkan betapa agama ataupun kecenderungan padanya (religiositas) tetap mewarnai kehidupan masyarakat dan seringkali bahkan ikut menentukan kebijakan ekonomi, hukum maupun politik (lihat buku American Theocracy (2006) karya Kevin Phillips), seakan membenarkan apa yang pernah dikatakan Alexis de Tocqueville satu setengah abad silam: “Aku tak habis pikir bagaimana bisa upaya menyusutkan pengaruh agama [di Amerika] ternyata malah memperbesar kekuatannya”.
Kelemahan tesis sekularisasi sebagai sebuah paradigma terletak pada sifatnya yang terkesan deterministik: Kalau sudah modern, pasti akan sekular. Kalau sekular, tentu modern. Agar modern, mesti sekular. Kalau tidak sekular, tidak bisa modern, dan seterusnya. Padahal, ‘masyarakat manusia’ jelas sangat dinamis dan karenanya amat sulit untuk dipatok arah maupun coraknya. Contoh empiris Turki dan Mesir menarik untuk kita renungkan.
Pengalaman Turki dan Mesir
Menyusul kekalahannya dalam perang melawan Russia pada tahun 1774 dan gagal mempertahankan Mesir dari invasi Napoleon pada tahun 1798, Imperium Turki Osmani terpaksa melakukan modernisasi militer, ekonomi dan sosial lewat serangkaian program yang dinamakan Tanzimat: bermula dengan menghapuskan pasukan khusus (janissaries), membubarkan tarekat Bektashi, regulasi pajak langsung, hingga memperkenalkan undang-undang anti-diskriminasi sipil (menghapus status dzimmi bagi non-Muslim).
Proyek modernisasi Turki itu dilanjutkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Setelah berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1923, Atatürk mencanangkan program pembangunan Turki modern lewat ‘enam anak panah’ (Altı Ok). Yaitu, pertama, prinsip republikanisme (cumhuriyetcilik), bahwa negara Turki modern menerapkan sistem demokrasi parlementer yang dipimpin oleh seorang presiden, bukan sultan atau khalifah. Kedua, nasionalisme (milliyetcilik), bahwa bukan agama atau mazhab tertentu yang menentukan kewarganegaraan. Ketiga, prinsip kenegaraan (devletcilik), dimana pemerintah berkuasa penuh dalam pengelolaan ekonomi dan berhak intervensi demi kepentingan rakyat. Keempat, prinsip populisme (halkcılık) yang dimaknai sebagai perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum. Kelima, sekularisme (laiklik), dan terakhir, prinsip revolusionisme (inkilapcılık).
Dari keenam sila ini, sekularisme adalah yang paling berpengaruh. Pada tanggal 3 Maret 1924, Imperium Osmani yang telah berkuasa selama lebih dari 700 tahun (1299-1922M) itu resmi dihapuskan. Tidak lama kemudian, pengadilan agama dan pondok-pondok pesantren dibubarkan. Begitu juga tarekat-tarekat sufi. Selanjutnya, pakaian ala Barat digalakkan, poligami dilarang, dan undang-undang baru (ala Swiss untuk hukum sipil, ala Itali untuk hukum pidana, dan ala Jerman untuk hukum perdata) mulai resmi diberlakukan, menggantikan undang-undang (Syariah) Islam. Selain itu, kalender Hijriah diganti dengan kalender Gregorian (Masehi), lalu penggunaan huruf Arab untuk bahasa Turki dilarang dan diganti dengan huruf Latin.
Pada perkembangan selanjutnya, ideologi sekular Atatürk –terkenal dengan sebutan “Kemalisme”- menjelma jadi sangat anti-agama dan ultra-nasionalistik. Segala yang bercirikan Islam atau berbau Arab dilecehkan sebagai keterbelakangan, kemunduran dan kebiadaban (barbarism). Siapa yang berani mempersoalkan sekularisme dituduh sebagai pengkhianat negara, tidak rasional dan sektarian. Selain itu, untuk menjamin kelanggengan ideologi ini, rezim Kemalis menciptakan apa yang mereka sebut sebagai ‘Islam yang tercerahkan’ (cagdas Islam), mirip dengan gagasan Islam progresif di Amerika Serikat, Islam modernis di Pakistan, atau Islam hadhari di Malaysia.
Proyek Atatürk ini pada intinya bertujuan mencabut Islam dari akar-akarnya (to promote ‘disestablishment’ of Islam), tulis sejarawan politik Hakan Yavuz. Namun sekularisme sebagai ideologi negara dinilai banyak pengamat telah gagal mencapai tujuannya. Buktinya, hingga saat ini belum banyak kemajuan yang diraih. Setelah lebih setengah abad berusaha menjadi sekular, Turki masih saja dianggap belum semaju, semodern dan sedemokratis negara-negara Eropa. Jangankan melampaui, menyamai Imperium Osmani pun belum bisa. Justru diam-diam namun pasti, Islam sebagai kekuatan politik nampak mulai bangkit melawan kekuatan sekular dan berusaha merebut kembali tampuk kekuasaan dari tangan mereka (Lihat: Heinz Kramer, A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United States, Washington, D.C., 2000).
Di Mesir, proses sekularisasi berlangsung sejak masuknya penjajah Perancis pada tahun 1798 dan Inggris pada tahun 1802. Tidak sampai seratus tahun kemudian lahirlah tokoh-tokoh yang menyerukan pembaharuan ala Barat. Di antara pionirnya ialah Rifa‘ah al-Tahtawi (1801-1873) yang pernah tinggal di Paris selama lima tahun. Dialah tokoh yang mengobarkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air (hubbul watan). Baginya, persaudaraan sebangsa dan setanah air (ukhuwwah wataniyyah) sama pentingnya atau bahkan lebih utama daripada persaudaraan atas dasar agama. Hanya dengan nasionalisme dan modernisasi, menurutnya, negara seperti Mesir bisa maju seperti Eropa. Qasim Amin (1863-1908) melangkah lebih jauh.
Murid Syekh Muhammad Abduh ini tidak hanya mengecam praktik despotisme ketika itu, tetapi juga menganggap Syariat Islam sebagai kendala kemajuan. Lantas ia pun menyerukan pembebasan perempuan lewat kesetaraan gender, kebebasan dalam berbusana (tidak wajib berjilbab), dan pelarangan poligami.
Kemudian muncul ‘Alī ‘Abdur-Rāziq dengan bukunya, al-Islam wa ushul al-hukm (Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan), dimana ia mengklaim bahwa Islam khilafah tidak ada dasarnya dalam Al-Qur’an, Hadits maupun ijma‘ ulama. Islam tidak memberikan aturan yang pasti tentang sistim pengelolaan negara. Muhammad SAW hanyalah seorang nabi, bukan penguasa, cuma ditugaskan untuk mengajarkan akhlak dan agama, bukan politik dan tata negara. Karena itu, agama tidak mesti dibawa-bawa dalam urusan kenegaraan. Urusan politik, pola pemerintahan, administrasi negara dan lain-lain tidak ada sangkut-pautnya dan karena itu tidak perlu dikaitkan dengan agama. Tidak hanya itu, Abdur-Raziq bahkan menuding sistem khilafah bertanggung-jawab atas ketertinggalan Umat Islam. Terlepas dari upaya-upaya tersebut, kenyataannya peran agama dalam kehidupan politik di Mesir tetap sukar dinafikan, seperti tercermin pada kemenangan Ikhwanul Muslimin belum lama ini.
Sekularisasi Mustahil
Dari paparan ringkas di atas dapat kita simpulkan bahwa sekularisasi bukanlah prasyarat mutlak transformasi masyarakat dari tradisional menjadi modern, tidak pula dapat menyulap negara dari tertinggal menjadi maju dan terkemuka.
Seperti diakui banyak sosiolog, tidak sedikit masyarakat negara modern yang tetap religius, baik secara individual maupun konstitusional (Islam sebagai agama resmi negara), seperti Libya dan Malaysia. Sebaliknya, tidak sedikit negara yang telah menyatakan diri sekular namun hingga kini masih saja belum tergolong sebagai negara maju, seperti Marokko dan Turki.
Di samping itu, sekularisme sebagai ideologi politik pada dasarnya tidak dapat bersenyawa dengan ajaran Islam yang hakiki, yang menganggap kekuasaan politik sebagai sarana penegakkan agama. Sebagaimana disinyalir oleh Bernard Lewis, sejak zaman Nabi Muhammad saw, umat Islam merupakan entitas politik dan agama sekaligus, dengan Rasulullah sebagai kepala Negara. Dengan kata lain, Nabi Muhammad saw tidak mempolitisir agama, melainkan mengagamakan politik, dalam arti politik untuk kepentingan agama, bukan agama untuk kepentingan politik.
“Dalam pengalaman Umat Islam generasi pertama, sebagaimana telah dilestarikan dan direkam untuk generasi sesudahnya, kebenaran agama dan kekuasaan politik terkait erat tak terpisahkan. Yang disebut pertama mensucikan yang terakhir, sedang yang disebut terakhir mendukung yang pertama,” tegas Lewis dalam bukunya, the Crisis of Islam ( London , 2003, hlm. 6). Akhirul kalam, masyarakat tidak mesti menjadi sekular untuk menjadi modern.
*)Penulis adalah peneliti INSISTS, dan dosen Perbandingan Agama di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia