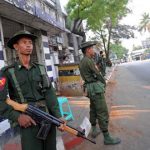Oleh: Abdul Rachman Thaha`
Hidayatullah.com | “Kalimat-kalimat vulgar di situs www.aishaweddings.com justru memantik kecurigaan. Apakah Aisha Wedding benar-benar nama sebuah wedding organizer? Atau sebatas situs propaganda tanpa sungguh-sungguh ada perusahaan atau organisasi di belakangnya?
Karena itu, saya mendesak Polri untuk serius menginvestigasi siapa di balik aishaweddings.com. Saya khawatir, situs semacam itu diadakan dengan maksud tidak baik, yakni mendiskreditkan kalangan agama tertentu. Bahwa, seolah ada agama yang semena-mena mempraktikkan kesemena-menaan terhadap anak-anak dan perempuan dewasa dengan selubung pernikahan.
Patut pula diduga ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin memengaruhi proses pembahasan legislasi. Dengan menyebarkan informasi berbau propaganda, kepentingan tersebut ingin membangun persepsi publik bahwa pembahasan legislasi sudah seharusnya dilakukan dengan mengikuti opini sang pemilik kepentingan.
Saya yakin, jumlah anak yang melakukan seks tanpa pernikahan jauh lebih banyak daripada jumlah anak yang menikah pada usia muda
Membangun opini, pada dasarnya, merupakan hal lumrah. Tapi ketika dilakukan dengan siasat mendiskreditkan pihak lain lewat informasi-informasi menyesatkan, ini tidak bisa dibenarkan. Ini tidak sehat. Dan karenanya harus diluruskan.
Pada sisi lain, seandainya diasumsikan bahwa wedding organizer bernama Aisha Wedding benar-benar ada, pertanyaannya adalah, ketika dilaporkan ke polisi, apa persoalan pidananya?
Baca: 54% Remaja Bandung Pernah Berhubungan Seks
Jika kalimat-kalimat pada situs Aisha Wedding dinilai bertentangan dengan kampanye pencegahan pernikahan anak-anak, maka KPAI, KPPPA, dan para pemangku kepentingan lainnya sepatutnya meninjau cermat: Apakah hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang pelakunya bisa dijatuhi sanksi baik pidana maupun perdata. Tanpa ancaman sanksi apa pun, sulit kiranya pelanggaran atas UU Perkawinan bisa ditegakkan secara maksimal.
Saya selaku anggota DPD RI siap duduk bersama KPAI dan KPPPA membahas hal tersebut. Sekaligus, kita kaji ulang kesiapan UU Perlindungan Anak dalam mengatasi pernikahan anak-anak.
Satu lagi, situs www.aishaweddings.commenyebut usia 12-21 tahun sebagai usia harus nikah. Pernikahan usia 12 sampai sebelum 19 tahun memang bertolak belakang dengan UU Perkawinan. Tapi UU tersebut masih memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah 19 tahun.
Sebagai ilustrasi, pernikahan anak 14 terbenarkan oleh UU Perkawinan apabila seluruh syaratnya terpenuhi. Poin tentang ini saja menambah sumir keberadaan pelanggaran hukum–apalagi pidana–dalam pernikahan anak-anak.
Penolakan pernikahan anak patut dinilai positif. Tapi saya sudah bertahun-tahun mempertanyakan ketidakhadiran negara untuk menekan fenomena seks di luar pernikahan. Yang lebih mengemuka justru kesan kuat bahwa seks di luar pernikahan adalah sah-sah saja sepanjang dilakukan atas dasar mau sama mau, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki.
Dengan tiga ciri “seks legal” semacam itu justru semakin marak program kondomisasi, toleransi terhadap ‘pasutri’ tanpa pernikahan, serta penerimaan terhadap orientasi dan perilaku seks sejenis. Padahal, ketiganya adalah gaya hidup yang jauh Pancasila.
Saya yakin, jumlah anak yang melakukan seks tanpa pernikahan jauh lebih banyak daripada jumlah anak yang menikah pada usia muda. Seks di luar nikah merupakan satu dari sekian banyak faktor pendorong pernikahan anak-anak.
Baca: Selain Narkoba, Persoalan Utama Remaja Seks Bebas
Atas dasar itu, tidaklah memadai pernikahan anak-anak disikapi sebagai masalah yang tidak berhubungan dengan masalah-masalah lain. Selama negara tidak menekan fenomena seks di luar nikah dan melegalkan seks berdasarkan prinsip konsensual dan tanpa paksaan semata, apalagi jika terjadi kehamilan, saya sama sekali tidak optimis bahwa kampanye mencegah pernikahan anak-anak akan memenuhi harapan kita semua.
Bahkan, dalam situasi kadung terjadi kehamilan akibat seks di luar nikah, menikahkan anak-anak justru menjadi jalan keluar yang getir. Jalan keluar setidaknya agar anak yang dilahirkan memperoleh kejelasan status, mengatasi aib susulan yang bisa dihadapi keluarga, sekaligus mendorong agar anak-anak tersebut bisa tetap bertanggung jawab atas status tambahan mereka selaku orang tua atas bayi hasil seks di luar pernikahan tersebut.
Sekaligus, pada titik itu muncul satu lagi panggilan kepada negara: ketika anak-anak terlanjur menikah, apa yang negara lakukan terhadap pasutri berusia anak-anak itu? Tidak boleh tidak; betapa pun mereka sudah menikah, hak-hak mereka selaku anak-anak tetap harus dipenuhi oleh negara.*
Penulis adalah Anggota DPD RI asal Sulawesu Tengah