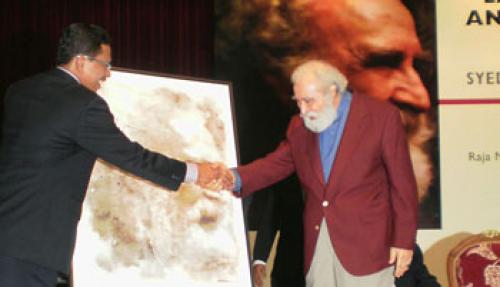oleh: Fiqih Risalah
DALAM pandangan Prof. al-Attas ada beberapa elemen mendasar dalam metafisika Islam yang tidak berubah. Hal ini didasarkan pada sejarah dan fakta, tidak hanya bersifat teoritis. Ini mengenai sesuatu yang konstan, misalnya, konsep Allah; makna wahyu; sifat agama; sifat manusia dan psikologi kejiwaannya; makna pengetahuan; kebebasan; khalifah, nilai-nilai kebajikan, serta makna kebahagiaan. Ini semua adalah kata kunci yang menggambarkan pandangan hidup Islam yang melandasi sistem metafisika dalam Islam; yang tidak berubah sepanjang masa, tidak seperti yang berlaku di Barat.
Di Barat, mereka telah berubah setiap saat. Perubahan yang berkelanjutan ini, membuat pandangan hidup mereka, yang sebenarnya sebuah system yang besar, menjadi hanya sebuah skema (paradigma). Apa yang mereka sebut sebagai ‘paradigma’ juga harus kita gunakan, seolah-olah worldview dalam Islam juga seperti sebuah paradigma yang harus berubah dan berkembang.
Dalam sejarahnya, mereka mengembangkannya karena seperti itulah yang telah terjadi kepada mereka. Hal ini disebabkan karena sebuah ‘kekecewaan’, kegagalan misi Kristiani untuk mengkristenkan orang-orang Barat, dengan kata lain ini adalah suatu penolakan orang-orang Barat akan keimanan Kristen. Hal ini sebenarnya pandangan yang tragis dalam melihat kehidupan; dan bahwa cara pandang yang sedemikian rupa, tampaknya diusahakan untuk mereka paksakan kepada para intelektual di dunia Muslim.
Hal lain yang dikritik oleh Prof. al-Attas mengenai kejiwaan manusia modern adalah, seperti adanya sistem parlemen di dunia yang mengharuskan semua keputusan yang dibuat harus diketahui oleh publik, maka komunitas ilmiah dan para teknokrat kita yang hidup di abad ini telah mengubah lebih daripada yang telah dilakukan oleh suatu sistem parlemen.
Mereka tidak merasa berkewajiban untuk memberikan alasan apapun atau melakukan sesuatu tanpa menjelaskannya kepada masyarakat. Ini semua adalah hasil dari gagasan ‘development’ dan kebangkitan ‘metode ilmiah’ yang telah diterapkan pada perilaku manusia.
Oleh karenanya, mereka telah merendahkan martabat manusia. Tentu saja, hal tersebut tidak membahayakan para teknokrat karena mereka telah melupakan bagaimana untuk menjadi manusia. Hal tersebut justru membahayakan mereka yang masih memiliki jiwa kemanusiaan di dalam diri mereka.
Ironisnya, mereka juga tidak tahu, menurut cendekiawan dan filosof Barat sendiri, bagaimana caranya untuk menjadi manusia. Mereka tidak tahu di mana kita berada sekarang dan dari mana kita berasal serta ke mana kita akan beranjak. Mereka tidak ingin tahu hal tersebut karena jenis pengetahuan yang mereka miliki menghalangi mereka untuk berbuat yang demikian. Pandangan Prof. al-Attas tersebut juga telah dikatakan oleh para filosof, pemikir, serta psikolog Barat. Seperti yang terangkum dalam The Development Dictionary (ed. Wolfgang Sachs), mereka mengkritisi “development” sebagai suatu persepsi yang menirukan kenyataan yang ada, sebagai suatu mitos yang menyenangkan masyarakat, dan sebagai suatu fantasi untuk memenuhi hasrat nafsu insaniah.
Di antara para psikolog modern, ada yang mengatakan akan adanya penghapusan makna. Misalnya, Jeffrey Burke Satinover mengatakan bahwa ada hal yang terus berubah serta telah kehilangan maknanya dan akhirnya tentu saja arti dari keberadaan manusia itu sendiri. Jadi hal ini terjadi karena munculnya ‘anarki sosial’.
Beberapa ilmuwan sosial dalam pandangan Prof. al-Attas bertanggung jawab atas ini, karena mengisyaratkan seolah-olah masyarakatlah yang memiliki wewenang (otoritas).
Penting sekiranya bagi para pemimpin Muslim untuk mengetahui, selama ilmu pengetahun dijadikan alat ukur, bahwa kekuasaan tidak seharusnya diberikan kepada rakyat karena umumnya mereka tidak memiliki ilmu. Dan tragisnya, kadangkala masyarakat awam diminta untuk mengambil suatu keputusan. Karena itulah kemunculan ‘anarki sosial’ dan juga ‘anarki intelektual’ yang semuanya tampak subjektif.
Menurut Attas, kita akan kembali ke zaman Yunani kuno di mana terdapat orang-orang memanggil diri mereka dengan ‘sophists’ yang menolak kemungkinan adanya pengetahuan. Demikianlah masyarakat kita sekarang, ketika mereka bertanya akan sesuatu, mereka akan mengutarakan satu pandangan dan yang lain juga akan mmengutarakan pandangan yang lain juga.
Jadi, pada kenyataannya mereka menolak kemungkinan adanya pengetahuan. Dengan kata lain, mereka tidak pernah mengakui adanya otoritas apapun. Satu hal yang harus diingat, otoritas apapun —baik otoritas politik, agama, budaya, sastra— harus dihormati, terutama yang berada di posisi kekuasaan, para pemimpin kita. Tetapi jika mereka tidak menghormati suatu otoritas, sebagai misal, ada beberapa kesalahan dalam hal bahasa, dan orang-orang mengatakan bahwa ini adalah salah sedangkan orang-orang yang berpengetahuan tentang hal tersebut juga berkata bahwa ini adalah salah, namun para pemimpin mereka tetap bersikeras mengatakan bahwa ini adalah benar, hal ini berarti sebuah penolakan terhadap kekuasaan.
Demikian juga dalam hal-hal lain terutama dalam perkara agama, Prof. al-Attas berpendapat bahwa bagi seseorang yang tidak cukup bekal dalam hal agama sebaiknya untuk idak berbicara tentang perkara agama terutama di khalayak ramai karena akan membawa mudharat yang bisa menimbulkan pertikaian.
Akhirnya Prof. al-Attas menyatakan bahwa kehormatan suatu bangsa pada pangkalnya akan bergantung pada integritas dan keluhuran ilmu pengetahuan yang ada pada mereka, karena dengan ilmu pengetahuanlah yang akan membawa kepada kerendahan hati.
Dengan pengertian bukan tunduk kepada kejahilan. Beliau mengungkapkan satu peribahasa Melayu, “ikut rasmi padi jangan ikut rasmi lalang.” Dengan kata lain, karena tangkai ‘padi’, bila penuh dengan gandum, dia menunduk ke bawah sebagai ibarat untuk segala hal yang baik. Analogi ini pada hakikatnya bersumber dari al-Qur’an. Al-Qur’an berbicara tentang pohon yang sarat dengan buah-buahan dan bila ada buah-buahan, semacam menggantung ke bawah, sebagaimana halnya hikmah dan otoritas. Itulah yang dimaksud dengan kerendahan hati. Berkaitan dengan kata “tawaddu” yang berasal dari bahasa Arab “wada’a”.
Tentu saja, dalam kamus-kamus pada umumnya mengartikan “tawaddu” dengan membuatnya rendah diri atau merendahkan diri. Namun dalam kenyataannya, kamus-kamus tersebut tidak begitu tepat dalam mengartikannya. Arti yang tepat berdasarkan pengamatan beliau adalah ‘meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai’, itulah arti yang sebenarnya karena berarti ‘meletakkan sesuatu’. Adalah satu kesalahan dalam menyalahartikan kewenangan, sebagai contoh, Jika seorang pemimpin diajak untuk rapat, tidak benar bagi orang tersebut untuk membiarkan dirinya duduk di belakang.
Dia harus menempati posisi depan karena itu adalah tempat yang sesuai baginya. Jika tidak, berarti dia tidak memiliki rasa hormat terhadap dirinya, tidak ada rasa hormat terhadap ilmu pengetahuan yang ia punya, yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Jadi, kata tawaddu’ berarti mengerti dan memahami serta menempatkan diri kita di tempat yang semestinya. Ini berarti kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang tepat.
Sebagai kesimpulan, Prof. al-Attas menyinggung tentang hak atas sesuatu (right places) sebagai inti dari semua karya-karyanya; bahwa adab adalah kesesuaian dengan hak atas sesuatu tersebut, bahwa keadilan adalah kondisi sesuatu yang berada di tempat yang tepat dan sesuai, bahwa keberadaan (eksistensi) adalah tempat segala sesuatu apapun yang tersusun dalam suatu keteraturan dari kenyataan ini. Jadi, ide tentang mengetahui tempat yang jelas dan sesuai (proper place) memerlukan ilmu pengetahuan yang mana seseorang selanjutnya harus bertindak berdasarkan hal tersebut.
Jadi, kerendahan hati tidak berarti bahwa kita harus sujud di hadapan kejahilan dan ketidakadilan. Beliau menegaskan bahwa kita harus menyatakan apa yang benar meskipun kadangkala merugikan diri kita. Sehingga kita perlu membicarakan tentang agama dalam pandangan Islam dan juga filsafat ilmu (philosophy of science) karena bagaimanapun tanpa filsafat ilmu kita akan menyimpang dan kembali meletakkan diri kita pada posisi atau visi manusia Barat yang sekuler.
Oleh karenanya, dalam memahami tentang esensi dari sebuah realitas, dikarenakan hal tersebut juga dipelajari di Barat yaitu apa yang dimaksud dengan realitas itu sendiri serta apa itu kebenaran, makanya kita harus berusaha untuk menjelaskannya berdasarkan kepada sumber-sumber Islam yaitu berdasarkan apa yang ada di dalam Al Qur’an dan Hadith beserta interpretasi daripadanya (tafsir) oleh para ulama’ sejati masa silam.
Singkatnya, kita harus memahami masa lalu kita untuk mengenali diri kita sendiri karena krisis yang dialami umat Islam adalah krisis identitas. Wa ‘l-lāhu a’lam bi ‘l-Øawāb.*
Penulis adalah kandidat doktor di Centre for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization (CASIS-UTM Malaysia).Topik ini sengaja diambil untuk mengulas kembali kuliah Prof. al-Attas mengenai Islamic Worldview