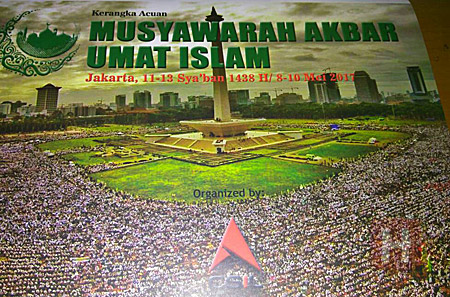Hidayatullah.com- Pemerhati Sejarah Jawa dan Islam, Susiyanto menilai Sabda Raja yang dikeluarkan oleh Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, terasa dominan nuansa politisnya terutama soal pengangkatan anak perempuan (putri Sultan, red) sebagai putra mahkota.
“Ratu yang terakhir ini tampaknya memang ingin lebih dikenal masyarakat umum sebagai “pribadi kerajaan”. Saya melihat kayaknya Sultan ini agak kalah dengan istrinya. Jadi, kebijakan-kebijakan resmi kebanyakan muncul dari istrinya,” demikian penilaian Susiyanto yang diungkapkan kepada hidayatullah.com, saat dihubungi Kamis (07/05/2015).
Menurut pengamatan Susiyanto sebelum (Sabda Raja) keluar, kraton lebih dulu mengeluarkan yang namanya Sabda Tama yang mana kedudukannya lebih rendah dibanding dengan Sabda Raja. Jadi, lanjutnya, sebelum itu di kalangan kraton sendiri memang sudah ada perbincangan tentang siapa yang akan menjadi putra mahkota.
“Kedudukan putra mahkota itu seharusnya jatuh pada adek laki-laki sultan, missal di antaranya Prabu Kusumo. Jika, saya perhatikan sepert itu,” kata Susiyanto.
Namun, lanjut Susiyanto, pembicaraan tentang putra mahkota tersebut diputus begitu saja dengan dikeluarkannya Sabda Tama. Sementara, arah selanjutnya setelah Sabda Tama dikeluarkan semakin mengerucut dengan dikeluarkannya Sabda Raja.
“Di mana poin-poin di dalamnya seperti gelar Khalifatullah dan seterusnya itu mulai diganti. Sepertinya memang ada arah bahwa kraton Jogja akan menerima raja seorang perempuan,” tegas Susiyanto.
Selain itu, Susiyanto menuturkan dalam Dhawuh Dhalem Nomor: 1/DD/HBX/Ehe-1932 yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X tanggal 8 November 1999 dinyatakan bahwa visi kraton adalah melestrikan dan mengembangkan ajaran budaya berdasarkan al-Quran dan Hadits.
“Kerajaan tersebut merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram Islam. Untuk itu, dalam hal kekuasaan seorang sultan mestinya seorang lelaki,” kata Susiyanto kepada hidayatullah.com saat menanggapi poin-poin yang terdapat dalam Sabda Raja Kraton Yogyakarta, Kamis (07/05/2015).
Susiyanto juga mengungkapkan isu krusial yang mengemuka dalam Sabda Raja tersebut berkaitan dengan perjanjian pendiri Mataram antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring. Janji ini, menurutnya, berkaitan dengan keturunan dari kedua belah pihak yaitu keturunan Pamanahan sebagai raja dan putri keturunan Giring sebagai permaisuri yang mendampingi.
“Di sini ketetapan awal kraton menunjukkan bahwa raja mestinya adalah lelaki, bukan perempuan,” tegas Susiyanto.
Dalam filosofi Jawa, lanjut Susiyanto, mestinya berlaku “sabda brahmana raja tan kena wola-wali, pindha we kresna tumetes dalancang seta” artinya sabda seorang ulama dan raja mestinya dipegang teguh dan tidak mencla-mencle. Sebab, mereka harus menjadi “pandoming bebrayan” (pedoman dan keteladanan bagi masyarakat).
“Jika mereka tidak teguh dalam sebuah pendirian maka bisa dipastikan masyarakat akan kehilangan kiblat kepemimpinan,” ujar Susiyanto.
Perkataaan raja atau ratu ini, menurut Susiyanto, mestinya seperti tinta hitam yang menetes di atas kertas putih (we kresna tumetes ing dalancang seta), sehingga menjadi sesuatu yang seharusnya sulit untuk diubah.
“Itu merupakan filosofi orang Jawa agar pemimpin umat selalu berhati-hati dalam ucapannya sehingga tidak menyesatkan,” pungkas Susiyanto.*